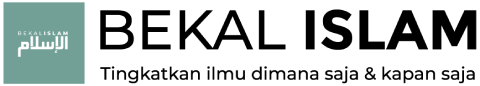Hukum-Hukum Imam Shalat
Pertama : Yang paling berhak menjadi imam
Para ulama berselisih menjadi beberapa pendapat tentang siapa yang paling berhak menjadi imam.
Pendapat pertama: Yang paling baik bacaannya, ini adalah madzhab Hanafiyah, At-Tsauri, dan Ahmad. Dalilnya adalah:
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ ”
Dari Abu Sa’id Al-Khudri, Nabi shallallāhu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika berkumpul tiga orang maka hendaklah salah satu dari mereka menjadi imam, dan yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling bagus bacaannya”. ([1])
«يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
“Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling bagus bacaan Kitabullah, jika dalam bacaan semuanya sama, maka yang paling mengetahui sunnah, jika dalam sunnah sama, maka yang paling dahulu hijrah, jika dalam hijrah sama maka yang paling dahulu masuk islam, dan tidak boleh seorang mengimami orang lain dalam kekuasaannya dan tidak boleh didik di rumahnya di tempat yang paling utama kecuali dengan izinnya”. ([2])
Pendapat kedua: Yang paling fakih, ini adalah madzhab malik dan syafi’i, dan riwayat dari Ahmad dan Abu Hanifah. Alasan mereka adalah karena sahabat yang paling bagus bacaannya adalah yang paling fakih, karena mereka tidak membaca sepuluh ayat melainkan memahaminya.
Pendapat yang kuat: Yang paling baik bacaannya adalah yang paling berhak menjadi imam, tetapi dengan syarat harus mengetahui hal-hal yang harus diketahui seputar shalat, jika tidak maka tidak bisa dijadikan imam dengan kesepakatan ulama, sebabnya adalah manusia pada zaman itu mengetahui makna Al-Qur’an karena mereka memahami Bahasa Arab, sehingga seorang yang bagus bacaannya jauh lebih faqih daripada fuqaha setelah mereka. ([3])
Kedua : Hukum shalat berjamaah dipimpin seorang anak kecil
Ada dua permasalahan berkaitan dengan hal ini :
Pertama : Apakah sah anak kecil menjadi imam?
Ulama berselisih pendapat berkaitan dengan seorang anak yang memimpin shalat, baik di dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah.
Pendapat Pertama: Sahnya seorang anak kecil yang menjadi imam shalat, baik itu shalat wajib maupun sunnah([4]).
Diantara dalil yang menjadi dasar pendapat ini adalah hadits yang telah diriwayatkan oleh ‘Amr bin Salamah radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا. فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ
“Jika telah tiba waktu shalat, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan dan orang yang paling banyak hafalan qur’annya untuk mengimami shalat kalian”.
‘Amr bin Salamah berkata, “Setelah itu mereka saling melihat dan tidak ada seorangpun yang paling banyak (hafalan) qur’annya dari pada aku, karena aku sering mendapati banyak rombongan pengendara, lalu mereka memintaku untuk mengimami mereka, sedangkan saat itu aku berusia enam atau tujuh tahun”([5])
Hadits ini menjelaskan bahwa para sahabat radhiyallahu ‘anhum mengedapankan ‘Amr untuk menjadi imam shalat, padahal saat itu dia hanyalah seorang anak yang berusia enam atau tujuh tahun. Dan hal itu terjadi di masa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Seandainya hal itu tidak diperbolehkan, tentu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjelaskannya kepada umatnya dan tidak menunda masalah tersebut (jika beliau mengetahui), karena tidak diperbolehkan menunda penjelasan suatu hukum pada saat dibutuhkan. Jadi, hal itu menunjukkan persetujuan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Jika masalah tersebut tidak disyariatkan (dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak mengetahui), tentunya sudah diturunkan wahyu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam untuk mengingkari hal itu. ([6])
Berikutnya adalah hadits Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id Al-Khudriy radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُم([7])
“Jika ada tiga orang, hendaknya salah satu dari mereka memimpin shalat dan yang berhak menjadi imam shalat adalah yang paling baik bacaannya”([8])
Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang paling berhak menjadi imam dalam shalat adalah yang paling baik dan banyak bacaan Al-Qur’annya, tanpa menyebutkan apakah harus baligh atau tidak, sehingga hadits ini umum mencakup anak yang belum baligh, karena barang kali bacaan atau hafalan Al-Qur’an lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. ([9])
Pendapat Kedua: Tidak sah seorang anak kecil memimpin dalam shalat wajib ataupun sunnah. ([10])
Berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam:
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ
Telah diangkat pena dari tiga golongan yaitu dari anak kecil hingga ia baligh. ([11])
Hadits di atas menunjukkan seorang anak yang belum baligh ataupun mumayyiz tidak diwajibkan ibadah yang berkaitan dengan badan seperti shalat, puasa dan haji. ([12])
Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan:
إِلَى صِحَّة إِمَامَة الصَّبِيّ ذَهَبَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق وَكَرِهَهَا مَالِك وَالثَّوْرَيْ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة وَأَحْمَد رِوَايَتَانِ وَالْمَشْهُور عَنْهُمَا الْإِجْزَاء فِي النَّوَافِل دُونَ الْفَرَائِض
Mengenai sahnya seorang anak kecil yang menjadi imam shalat, merupakan pendapat Al-Hasan Al-Bashri, As-Syafi’i dan Ishaq. Malik dan Ats-Tsauriy memakruhkannya. Ada dua riwayat dari Abu Hanifah dan Ahmad, dan yang masyhur dari pendapat mereka adalah bahwa anak kecil sah menjadi imam dalam shalat sunnah dan bukan shalat wajib. ([13])
Kesimpulan : Yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat madzhab As-Syafi’i, bahwasanya anak kecil yang mumayyiz (bisa membedakan) sah menjadi imam meskipun belum dewasa, berdasarkan hadits ‘Amr bin Salamah yang mengatakan bahwa sahnya seorang anak kecil menjadi imam shalat. Karena yang menjadi dasar pendapat yang kedua tidak menunjukkan pada pokok permasalahan. Dan hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang menjelaskan tentang diangkatnya pena dari seorang anak kecil hingga usia baligh sejatinya menunjukkan kepada gugur dan tidak diwajibkannya kewajiban dalam beribadah bagi mereka akan tetapi tidak menafikan sahnya ibadah mereka. Jadi tidak dibenarkan jika hadits tersebut menunjukkan tidak sahnya seorang anak kecil menjadi imam dalam shalat. ([14])
Permasalahan Imam Shalat
Pertama : Jika Imam lupa bacaan surat, apakah mengganti bacaan surat atau langsung ruku’?
Maka dalam permasalahan ini perlu diperinci, kesalahan dalam membaca surat al-Fatihah dan selain al-Fatihah.
Pertama: jika lupa satu ayat dari surat al-Fatihah atau lupa satu surat secara keseluruhan maka tidak sah shalatnya karena al-fatihah termasuk rukun shalat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shomit:
«لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ»
“Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca al-Fatihah.” ([15])
Dan berkata an-Nawawi:
مذهبنا أَنَّ الْفَاتِحَةَ مُتَعَيَّنَةٌ لَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْقَادِرِ عَلَيْهَا إلَّا بِهَا وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ
“Madzhab kami bahwa al-Fatihah wajib tidah sah shalat orang yang mampu membacanya kecuali harus membacanya, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabu’in, dan orang-orang yang setelahnya (tabi’ut tabi’in)”.” ([16])
Begitu juga yang difatwakan oleh dewan fatwa al-lajnah ad-Daimah ketika seseorang lupa satu ayat dari surat al-Fatihah:
إذا نسي الإمام آية من سورة الفاتحة ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة – فإنه يجب عليه إعادة الصلاة إذا كانت فريضة؛ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» أما إن ذكرها قبل طول الفصل فإنه يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك قراءة آية من الفاتحة فيها ويسجد للسهو، أما إذا كانت الآية المنسية من غير الفاتحة فصلاته صحيحة ولا شيء عليه ولا على من خلفه في ذلك، لأن قراءة ما زاد على الفاتحة مستحب وليس بواجب.
“Jika seorang imam lupa sebuah ayat dari surat al-fatihah dan ia tidak ingat kecuali setelah jeda waktu yang lama (setelah selesai shalatnya) maka ia wajib mengulang shalatnya jika shalat tersebut shalat wajib, hal ini dikarenakan membaca surat al-fatihah salah satu rukun dari rukun-rukun shalat, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca al-Fatihah. Adapun jika ia teringat dalam jangka waktu yang pendek maka cukup baginya untuk mendatangkan satu raka’at yang ia meninggalkan membaca satu ayat dari surat al-fatihah kemudian sujud sahwi. Adapun jika ayat yang dilupakan bukan dari surat al-fatihah maka shalatnya sah dan tidak membatalkan shalatnya juga shalat orang yang di belakangnya, karena membaca selebihan dari al-fatihah hukumnya mustahab dan bukan wajib.” ([17])
Kedua: jika terlupa pada surat selain al-Fatihah maka hukum bacaan surat selain al-fatihah adalah sunnah bukan wajib, berkata An-Nawawi:
وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ السُّورَةِ بَعْدَهَا وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِي الصبح والجمعة والأولين مِنْ كُلِّ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ
“Dan didalamnya menunjukkan mustahabnya membaca surat setelahnya (al-fatihah), dan ini adalah perkara yang disepakati ketika shalat subuh, jum’at, dan dua raka’at pertama disetiap shalat, dan dia sunnah menurut para ulama.” ([18])
Maka boleh bagi orang yang lupa untuk mengganti dengan surat yang lain jika ia tidak mampu untuk melanjutkannya dan tidak ada dari makmum yang memberitahunya dan juga boleh baginya untuk langsung ruku, shalatnya sah dan tidak batal, karena bacaan surat selain al-Fatihah hukumnya adalah sunnah. Berkata Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz:
هُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ كَبَّرَ وَأَنْهَى الْقِرَاءَةَ، وَإِنْ شَاءَ قَرَأَ آيَةً أَوْ آيِاتٍ مِنْ سُوْرَةٍ أُخْرَى … أَمَّا الْفَاتِحَةُ فَلاَ بُدَّ مِنْ قِرَاءَتِهَا جَمِيْعِهَا؛ لِأَنَّ قِرَاءَتَهَا رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ
“Dia bisa memilih, jika ia mau boleh bertakbir dan mengakhiri bacaannya, dan jika mau ia boleh membaca suatu ayat dari dari ayat-ayat surat lain…. Adapun surat al-Fatihah maka harus dibaca semuanya, karena bacaannya adalah salah satu rukun dari rukun-rukun shalat.” ([19])
Kedua : Jika imam batal apakah makmum batal?
Terdapat hadits dari Abu Hurairah:
«يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ»
“Para imam shalat memimpin kalian. Maka jika mereka (para imam) benar, maka kalian mendapatkan pahala shalat kalian. Namun bila mereka salah kalian tetap mendapatkan pahala dan mereka yang menanggung kesalahan.” ([20])
Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar membawakan perkataan Ibnu Mundzir:
قَالَ ابن الْمُنْذِرِ هَذَا الْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ صَلَاةُ من خَلفه
“Berkata Ibnu Mundzir: hadits ini membantah terhadap orang yang menganggap bahwa shalat imam jika rusak/batal maka shalat makmum juga ikut batal.” ([21])
Lalu bagaimana jika shalat imamnya batal?
Maka dalam masalah ini ada beberapa cara:
Pertama: imam menunjuk seseorang untuk menggantikannya sebagai imam (istikhlaf)
Maka ini boleh berdasarkan kisah Umar bin Al-Khotthob ketika beliau ditusuk ketika mengimami shalat subuh lalu beliau menarik tangan Abdurrahman bin ‘Auf untuk menggantikannya menjadi Imam, hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh ‘Amr bin Maimun:
قَالَ: إِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ غَدَاةَ أُصِيبَ، وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ، قَالَ: اسْتَوُوا، حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِنَّ خَلَلًا تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ، وَرُبَّمَا قَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ، أَوِ النَّحْلَ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ , فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِي – أَوْ أَكَلَنِي – الكَلْبُ، حِينَ طَعَنَهُ، فَطَارَ العِلْجُ بِسِكِّينٍ ذَاتِ طَرَفَيْنِ، لاَ يَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ يَمِينًا وَلاَ شِمَالًا إِلَّا طَعَنَهُ، حَتَّى طَعَنَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا، فَلَمَّا ظَنَّ العِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ، وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ، فَمَنْ يَلِي عُمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى، وَأَمَّا نَوَاحِي المَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لاَ يَدْرُونَ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ، وَهُمْ يَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ، فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَلاَةً خَفِيفَةً
“Di pagi peristiwa penusukan itu, saya sholat berdiri di belakangnya (Umar bin al-Khattab) hanya tepat di depan saya ada Abdullah bin Abas (maksudnya Amr Bin Maimun berada di shaf kedua). Saat itu ketika Umar melewati diantara dua shaf shof dia berkata: luruskan shaf kalian, sampai tidak ada celah dalam shaf-shaf tersebut, kemudian Umar maju dan takbir. Biasanya Umar membaca Surat Yusuf, Surat Nahl atau sejenisnya pada rakaat pertama sambil menunggu jamaah lain datang. Dan ketika beliau bertakbir saya mendengarkannya berkata: “Seseorang membunuhku” atau “Seekor anjing telah memakanku”, ketika itu seseorang menusuk Umar, seorang lelaki([22])menyerang dengan pisau bermata ganda. Tidaklah ia melewati seseorang yang berada di sisi kanan maupun kirinya kecuali Ia tusuk, hingga ia menusuk tiga belas orang yang akhirnya mati dari mereka tujuh orang. Ketika seseorang laki-laki Muslim melihat hal tersebut ia menyergap si pembunuh dengan bajunya([23]). Ketika sipembunuh menyadari dirinya telah terperangkap ia membunuh dirinya sendiri. Lalu Umar menarik tangan Abdurahman bin Auf dan memajukannya. Orang-orang yang dekat Umar maka dapat melihat apa yang aku lihat, sedangkan yang berada di pojok-pojok maka mereka tidak mengetahui apa yang terjadi selain mereka tidak mendengarkan suara Umar, hingga mereka mengucapkan: “Subhanalloh, subhanalloh!”. Maka Abdurahman mengimami jamaah dengan sholat yang ringan.” ([24])
Kedua: jika imam tidak mengambil pengganti dari makmum sebagai imam, maka salah satu dari makmum boleh maju menjadi imam, ini adalah fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz, beliau berkata:
فَإِنْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ بِهِمُ الإِمَامُ تَقَدَّمَ بَعْضُ مَنْ وَرَاءَهُ فَأَكْمَلَ بِالنَّاسِ
“Jika imam tidak menunjuk penggantinya dari kalangan makmum, maka maju salah satu yang berada di belakangnya (menjadi imam) kemudian menyempurnakan shalatnya.” ([25])
Ketiga: jika imam tidak menunjuk pengganti, maka makmum boleh menyempurnakan shalatnya sendiri-sendiri. Berkata imam Ahmad bin Hanbal:
إِنِ اسْتَخْلَفَ الإِمَامُ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ عُمَرُ وَعَلِيُّ، وَإِنْ صَلَّوْا وَحْدَانًا فَقَدْ طُعِنَ مُعَاوِيَةُ وَصَلَّى النَّاسَ
“Jika imam menunjuk pengganti maka Umar dan Ali telah menunjuk pengganti, dan jika makmum shalat sendiri-sendiri maka sungguh Muawiyah telah ditusuk (ketika menjadi imam) dan orang-orang pun menyempurnakan shalat mereka masing-masing.” ([26])
Keempat: imam memerintahkan makmum untuk tetap pada posisi mereka masing-masing, lalu ia bersuci dan kembali melanjutkan menjadi imam, hal ini berdasarkan hadits Abu Bakroh:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ، ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ»
“Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengimami pada shalat subuh. Tiba-tiba beliau berisyarat dengan tangannya kepada para sahabat agar tetap berada di tempatnya (kemudian beliau pergi), lalu beliau kembali, sementara kepalanya meneteskan air, dan beliau shalat jamaah bersama mereka”([27])
Ketiga : Jika Imam tetap melanjutkan rakaat kelima setelah ditegur oleh makmum
Ini seperti yang pernah ditanyakan kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah:
وَسُئِلَ – رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَنْ إمَامٍ قَامَ إلَى خَامِسَةٍ فَسَبَّحَ بِهِ فَلَمْ يَلْتَفِتْ لِقَوْلِهِمْ وَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَسْهَ. فَهَلْ يَقُومُونَ مَعَهُ أَمْ لَا؟ .
فَأَجَابَ:
إنْ قَامُوا مَعَهُ جَاهِلِينَ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُمْ؛ لَكِنْ مَعَ الْعِلْمِ لا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُتَابِعُوهُ بَلْ يَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يُسَلِّمَ بِهِمْ أَوْ يُسَلِّمُوا قَبْلَهُ وَالِانْتِظَارُ أَحْسَنُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
“Beliau (Ibnu Taimiyyah) rahimahullah ditanya tentang seorang imam yang bangkit ke raka’at kelima dan makmum sudah bertasbih namun imam tidak menggubris tasbih makmum, dan dia menyangka bahwasanya ia tidak lupa, apakah para makmum bangkit bersamanya atau tidak?
Beliau menjawab:
“Seandainya para makmum bangkit bersamanya dalam keadaan tidak memiliki ilmu tentangnya maka shalat mereka tidak batal, akan tetapi ketika mereka memiliki ilmu maka tidak sepantasnya bagi mereka untuk mengikutinya, akan tetapi menunggunya hingga imam salam atau boleh bagi mereka para makmum untuk salam sebelum imam, dan menunggu lebih baik. Wallahu a’lam.” ([28])
Dan dijelaskan oleh al-lajnah ad-daimah:
وأما المأموم الذي تيقن أن الإمام زاد ركعة – مثلا- فلا يجوز له أن يتابعه عليها، وإذا تابعه عالما بالزيادة، وعالما بأنه لا تجوز المتابعة بطلت صلاته. أما من لم يعلم أنها زائدة فإنه يتابعه، وكذلك من لا يعلم الحكم
“Dan adapun makmum yang yakin bahwa imam telah menambah raka’at contohnya, maka tidak boleh baginya untuk mengikutinya, dan jika tetap mengikutinya dalam keadaan ia tahu bahwasanya ia tidak boleh untuk mengikutinya maka shalatnya batal. Dan adapun makmum yang tidak tahu bahwasanya ini rakaka’at tambahan maka baginya untuk mengikuti imam, begitu juga orang yang tidak mengetahui hukumnya.” ([29])
Adapun bagi masbuk maka rakaat tersebut maka raka’at tambahan imam tersebut tetap dihitung rakaat untuknya, hal ini sebagaimana yang dikatakan Syaikh Utsaimin:
وأما بالنسبة للمسبوق الذي دخل مع الإمام في الثانية فما بعدها فإن هذه الركعة الزائدة تحسب له، فإذا دخل مع الإمام في الثانية مثلاً سلم مع الإمام الذي زاد ركعة، وإن دخل في الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام من الزائدة، وذلك لأننا لو قلنا بأن المسبوق لا يعتد بالزائدة للزم من ذلك أن يزيد ركعة عمداً، وهذا موجب لبطلان الصلاة، أما الإمام فهو معذور بالزيادة، لأنه كان ناسياً فلا تبطل صلاته.
“Dan adapun untuk makmum masbuk yang masuk bersama imam di raka’at keduadan setelahnya maka raka’at tambahan ini dihitung untuknya, maka jika ia masuk bersama imam di raka’at kedua contohnya maka ia salam bersama imam yang telah menambha raka’at, dan jika ia masuk di raka’at ketiga maka baginya untuk mendatangkan satu raka’at setelah salamnya imam dari raka’at tambahan, dan hal tersebut karena seandainya kita katakana bahwasanya makmum yang masbuk tidak dihitung untuknya raka’at tambahan maka akan melazimkan dari hal tersebut ia akan menambahkan satu raka’at secara sengaja, dan ini melazimkan batal shalatnya. Adapun imam maka dia diberikan udzur dengan tambahan tersebut, karena dia lupa maka tidak batal shalatnya.” ([30])
Keempat : Makmum memisahkan diri dari imam (membatalkan niatnya jadi makmum) lalu shalat sendiri (dengan niat sholat munfarid/sendirian)
Hal ini seperti ketika seorang imam membaca terlalu panjang, apakah boleh bagi makmum untuk merubah niatnya untuk melanjutkan shalat sendiri?
Terdapat sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah
كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَرْجِعُ، فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَصَلَّى العِشَاءَ، فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ، فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَكَأَنَّ مُعَاذًا تَنَاوَلَ مِنْهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «فَتَّانٌ، فَتَّانٌ، فَتَّانٌ» ثَلاَثَ مِرَارٍ وَأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ المُفَصَّلِ
“Bahwasanya Mu’adz bin Jabal shalat bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, dia lalu kembali pulang dan mengimami kaumnya shalat ‘Isya dengan membaca surah Al Baqarah. Kemudian ada seorang laki-laki keluar dari shalat jamaah, Mu’adz seakan menyebut orang tersebut dengan keburukan. Kejadian ini kemudian sampai kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, maka beliau pun bersabda: “Apa engkau akan membuat fitnah? Apa engkau akan membuat fitnah? Apa engkau akan membuat membuat fitnah?” Beliau ucapkan hingga tiga kali. Lalu beliau memerintahkannya (Mu’adz) untuk membaca dua surah saja dari pertengahan Al Mufashshal.” ([31])
Dan juga dalam riwayat lain:
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمُ الصَّلاَةَ، فَقَرَأَ بِهِمُ البَقَرَةَ، قَالَ: فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلاَةً خَفِيفَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا البَارِحَةَ، فَقَرَأَ البَقَرَةَ، فَتَجَوَّزْتُ، فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ – ثَلاَثًا – اقْرَأْ: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَنَحْوَهَا ”
bahwa Mu’adz bin Jabal radliallahu ‘anhu pernah shalat bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam kemudian dia mendatangi kaumnya untuk mengimami shalat bersama mereka dengan membaca surat Al Baqarah, Jabir melanjutkan; “Maka seorang laki-laki pun keluar (dari shaf) lalu ia shalat dengan shalat yang ringan (yaitu ia menyelesaikan shalat sendiri), ternyata hal itu sampai kepada Mu’adz, ia pun berkata; “Sesungguhnya dia adalah seorang munafik.” Ketika ucapan Mu’adz sampai ke laki-laki tersebut, laki-laki itu langsung mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sambil berkata; “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami adalah kaum yang memiliki pekerjaan untuk menyiram ladang, sementara semalam Mu’adz shalat mengimami kami dengan membaca surat Al Baqarah, hingga saya keluar dari shaf, lalu dia menganggapku seorang munafik.” Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wahai Mu’adz, apakah kamu hendak membuat fitnah.” -Beliau mengucapkannya hingga tiga kali- bacalah surat asy-syams dan al-a’la atau yang serupa dengannya.” ([32])
Maka dari hadits-hadits diatas menunjukkan bahwasanya seseorang boleh membatalkan shalatnya ketika shalat berjama’ah lalu shalat sendiri, berkata an-Nawawi dalam membahas hadits di atas:
فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي فِيهَا أَنَّهُ سَلَّمَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ قَطَعَ الصَّلَاةَ مِنْ أَصْلِهَا ثُمَّ اسْتَأْنَفَهَا فَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ قَطْعِ الصَّلَاة وإبطالها لعذر
“Dalam riwayat yang didalmnya menyebutkan bahwa lelaki tersebut mengucapkan salam (yaitu untuk membatalkan shalatnya) menunjukkan bahwasanya ia memutuskan shalatnya dari asalnya kemudian memulai dari awal, maka ini menunjukkan bolehnya memutus shalat berjamaah dan membatalkannya jika terdapat udzur.” ([33])
Demikian juga riwayat yang lain menunjukan bolehnya makmum memisahkan diri dari imam dan meneruskan shalat sendirian dengan ringan jika ada udzur. Ibnu Qudamah berkata :
وَإِنْ أَحْرَمَ مَأْمُومًا، ثُمَّ نَوَى مُفَارَقَةَ الْإِمَامِ، وَإِتْمَامَهَا مُنْفَرِدًا لِعُذْرٍ، جَازَ
“Jika ia bertakbiratul ihram dengan niat sebagai makmum, lalu ia berniat untuk memisahkan diri dari imam dan ingin menyelesaikan shalatnya dengan niat shalat sendiri karena ada udzur, maka boleh”
Ibnu Qudamah berdalil dengan hadits Jabir di atas, tentang kisah Muádz, setelah itu beliau berkata :
وَلَمْ يَأْمُرْ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الرَّجُلَ بِالْإِعَادَةِ، وَلَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ فِعْلَهُ، وَالْأَعْذَارُ الَّتِي يَخْرُجُ لِأَجْلِهَا، مِثْلُ الْمَشَقَّةِ بِتَطْوِيلِ الْإِمَامِ، أَوْ الْمَرَضِ، أَوْ خَشْيَةِ غَلَبَةِ النُّعَاسِ، أَوْ شَيْءٍ يُفْسِدُ صَلَاتَهُ، أَوْ خَوْفِ فَوَاتِ مَالٍ أَوْ تَلَفِهِ، أَوْ فَوْتِ رُفْقَتِهِ، أَوْ مَنْ يَخْرُجُ مِنْ الصَّفِّ لَا يَجِدُ مَنْ يَقِفُ مَعَهُ، وَأَشْبَاهُ هَذَا.
“Dan Nabi shallallahu álaihi wasallam tidak memerintahkan lelaki tersebut (yang memisahkan diri dari jamaáh) untuk mengulangi shalatnya, bahkan Nabi tidak mengingkari perbuatannya tersebut. Dan udzur-udzur yang membolehkan seseorang memisahkan diri dari imam seperti kesulitan/keberatan karena imamnya yang terlalu lama/panjang bacaannya, atau karena sakit, atau kawatir dikuasai kantuk yang berat, atau kawatir sesuatu bisa membatalkan shalatnya, atau kawatir hilangnya hartanya atau rusaknya hartanya, atau ketinggalan rombongan, atau seseorang yang keluar dari shaff karena tidak mendapatkan orang yang berdiri bersamanya, dan yang semisal ini” (Al-Mughni 2/171)
Kelima : Makmum masbuk menjadi imam untuk makmum masbuk yang lain
Contohnya: jika ada dua orang atau lebih masbuk di pertengahan shalat, lalu ketika imam salam, salah satu dari makmum masbuk maju menjadi imam. Apakah hal ini diperbolehkan?
Permasalahan ini dijelaskan dalam madzhab Hanbali, salah satunya yang dijelaskan oleh Al-Mirdawi ia berkata:
(وَإِنْ سُبِقَ اثْنَانِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فَائْتَمَّ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ فِي قَضَاءِ مَا فَاتَهُمَا، فَعَلَى وَجْهَيْنِ) وَحَكَى بَعْضُهُمْ الْخِلَافَ رِوَايَتَيْنِ….أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ ذَلِكَ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ … بِنَاءً عَلَى الِاسْتِخْلَافِ، وَتَقَدَّمَ جَوَازُ الِاسْتِخْلَافِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، …
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَجُوزُ … هَذَا مَنْصُوصُ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ
“(jika ada dua orang masbuk terhadap sebagian raka’at shalat, kemudian (setelah imam salam) salah satu diantara keduanya bermakmum dengan temannya dalam mengqodho raka’at yang telaj luput dari mereka berdua maka ada dua pendapat), dan sebagian mereka (ulama hanabilah) menghikayatkan perbedaan ada dua riwayat….pertama: bolehnya hal tersebut, dan ini adalah pendapat madzhab Hanbali…hal ini dibangun atas masalah istikhlaf (ditengah shalat imam berhalangan lalu menunjuk makmum untuk menggantikan posisinya sebagai imam-pen), dan telah berlalu pembahasan akan bolehnya istikhlaf menurut pendapat yang shohih dalam madzhab…
Pendapat kedua: Tidak boleh, … ini yang dinaskan dari Ahmad dalam riwayat Shalih dari Imam Ahmad” ([34])
Dan pendapat pertama adalah pendapat yang dipilih dalam kitab ad-duror as-saniyyah fil ajwibatin najdiyyah:
والذي يترجح عندنا هو الوجه الأول، سواء نويا ذلك في حال دخولهما مع الإمام، أو لا، والله أعلم.
Dan yang rajih menurut kami adalah pendapat pertama, sama saja mereka berdua meniatkan hal tersebut ketika mereka masuk bersama imam atau tidak. Wallahu a’lam. ([35])
Adapun syaikh Utsaimin mengatakan bahwa hal tersebut boleh namun tidak disyariatkan atau disunnahkan, karena beliau membedakan antara mengatakan hal tersebut disyariatkan dengan hal tersebut dibolehkan, sehingga beliau tidak menyarankan hal tersebut dilakukan, namun jika dikerjakan hal tersebut tidaklah membatalkan shalatnya. ([36])
Keenam : Apakah harus ikut imam dalam hal-hal yang diperselisihkan?
Yaitu :
– Apakah jika imam menggerak-gerakan jarinya tatkala tasyahhud maka makmum juga harus ikut menggerak-gerakan jarinya, padahal sang makmum tidak meyakini akan sunnahnya menggerak-gerakan jari tatkala tasyahhud? Dan jika sebaliknya?
– Apakah jika imam mengangkat kedua tangan tatkala hendak sujud maka makmum juga harus mengangkat kedua tangannya (padahal sang makmum tidak meyakini disunnahkannya hal tersebut)? Dan jika sebaliknya?
– Apakah jika imam hendak sujud dengan meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum kedua tangannya apakah makmum juga harus demikian?, sementara makmum meyakini didahulukannya kedua tangan sebelum kedua lutut?, dan jika sebaliknya?
– Apakah jika imam melakukan duduk istirahat -tatkala hendak berdiri ke rakaat ke dua atau ke rakaat ke empat- maka makmum juga harus duduk istirahat (padahal sang makmum tidak meyakini adanya duduk istirahat)?, dan jika sebaliknya?
– Apakah jika imam qunut subuh maka sang makmum juga harus qunut subuh? (padahal sang makmum meyakini tidak disyari’atkannya qunut subuh)
Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka kita harus paham apa saja perkara-perkara yang sang makmum harus mengikuti imam dan tidak boleh menyelisihinya?
Dalil yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah sabda Nabi :
إنما جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فإذا صلى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا فإذا رَكَعَ فَارْكَعُوا وإذا رَفَعَ فَارْفَعُوا وإذا قال سمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وإذا صلى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وإذا صلى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ
“Hanyalah dijadikan imam adalah untuk diikuti, maka jika imam sholat berdiri maka sholatlah kalian (wahai para mekmum-pent) berdiri juga, jika imam ruku’ maka ruku’lah kalian, dan jika imam bangkit maka bangkitlah, dan jika imam berkata “Sami’allahu liman hamidahu” ucapkanlah “Robbanaa wa lakalhamdu”. Jika imam sholat berdiri maka sholatlah berdiri, dan jika imam sholat duduk maka sholatlah kalian seluruhnya dengan duduk” ([37])
Rasulullah juga bersabda:
إنما جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فلا تَخْتَلِفُوا عليه فإذا رَكَعَ فَارْكَعُوا …
“Hanyalah dijadikan imam untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya, jika ia ruku’ maka ruku’lah kalian…”([38])
Ibnu Hajar berkata, “Dan kondisi pengikut (makmum) adalah tidak mendahului orang yang diikutinya (imam), dan juga tidak menyertainya, dan juga tidak berdiri lebih maju di hadapannya, akan tetapi ia memperhatikan gerakan dan kondisi sang imam lalu ia segera menyusul sebagaimana gerakan sang imam” ([39])
Berkata An-Nawawi : “Hadits ini dalil akan wajibnya makmum untuk mengikuti imam dalam takbir, berdiri, duduk, ruku’, sujud, dan hendaknya ia melakukannya setelah imam. Maka ia bertakbirotul ihroom setelah imam selesai bertakbirotul ihrom. Jika bertakbirotul ihrom sebelum imam bertakbirotul ihrom maka tidak sah sholatnya. Ia ruku’ setelah imam mulai ruku’ dan sebelum imam berdiri dari ruku’. Jika ia menyertai imam (dalam ruku’-pent) atau mendahului imam maka ia telah berbuat keburukan akan tetapi sholatnya tidak batal. Demikian juga sujud. Dan ia member salam setelah imam selesai salam, jika ia salam sebelum imam salam maka sholatnya batal, kecuali jika ia berniat untuk memisahkan diri dari jama’ah sholat. Dan ada khilaf dalam permasalahan ini…”([40])
An-Nawawi juga berkata, “Adapun sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam Hanyalah dijadikan imam untuk diikuti maka maknanya menurut Imam As-Syafi’i dan sekelompok ulama yaitu (diikuti) pada perbuatan-perbuatan (gerakan-gerakan) yang dzohir (nampak), karena boleh saja seseorang yang sholat fardu bermakmum kepada orang yang sholat sunnah dan sebaliknya, demikian juga seorang yang sholat asar bermakmum kepada orang yang sholat dzuhur dan sebaliknya.
Malik dan Abu Hanifah radhiallahu ‘anhumaa dan para ulama yang lain berkata bahwasanya hal ini tidak diperbolehkan. Mereka berkata bahwasanya makna hadits adalah imam diikuti pada gerakan-gerakan dan juga pada niat (jadi niat harus sama antara imam dan makmum-pent). As-Syafii –radhiallahu ‘anhu- dan para ulama yang sepakat dengannya berdalil dengan bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengimami (dua kelompok dari) para sahabat di Batn Nakhl tatkala sholat khouf dua kali, sekali bersama kelompok pertama dan yang kdua bersama kelompok yang kedua. Maka sholat beliau yang kedua adalah sunnah adapun (para sahabat dari kelompok yang kedua) yang bermakmum di belakang Nabi sholat mereka adalah fardhu. Demikian juga hadits Mu’adz tatkala beliau setelah sholat isya bersama Nabi maka beliaupun setelah itu mendatangi kaum beliau lalu mengimami mereka, maka sholat tersebut sunnah di sisi Mu’adz dan wajib di sisi kaumnya.
Hal ini menunjukan bahwa mengikuti imam hanya wajib pada perbuatan-perbuatan (gerakan-gerakan) yang dzohir([41])
Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa yang lebih menguatkan pendapat Imam An-Nawawi ini (madzhab As-Syafi’i) bahwasanya kewajiban mengikuti imam yang pada gerakan-gerakan yang dzhohir karena yang disebutkan oleh Nabi dalam hadits adalah ruku’, takbir, bangkit dari ruku’ dan semacamnya, adapun niat maka tidak disebutkan dalam hadits ([42])
Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa makmum hanya wajib mengikuti gerakan-gerakan dzohir sang imam, jika sang imam bertakbir maka ia bertakbir pula, jika imam rukuk maka ia segera ruku’ juga dan demikian juga jika imam duduk atau berdiri. Hal ini dimaksudkan agar makmum tidak mendahului imam atau terlambat mengikuti imam.
Adapun gerakan-gerakan yang tidak mengakibatkan penyelisihan terhadap imam berupa mendahului atau keterlambatan maka tidak wajib bagi makmum untuk mengikuti imam.
Sebagai contoh jika sang imam tatkala duduk tasyahhud sholat subuh dengan tawarruk sedangkan sang makmum meyakini sunnahnya duduk iftirosy maka tidak wajib bagi sang makmum untuk meniru cara duduk sang imam. Karena hal ini sama sekali tidak berkaitan dengan penyelisihan berupa mendahului atau keterlambatan.
Demikian juga jika ternyata sang imam tidak menggerak-gerakan jarinya sementara sang makmum meyakini sunnahnya menggerak-gerakan jari tatkala tasyahhud maka tidak wajib bagi sang makmum untuk mengikuti sang imam.
Syaikh Al-‘Utsaimiin berkata, “Adapun perkara yang mengantarkan kepada penyelisihan imam maka imam harus diikuti (tidak boleh diselisihi-pent), adapun perkara yang tidak menyelisihi imam –seperti mengangkat kedua tangan tatkala hendak ruku’ jika ternyata sang imam tidak mengangkat kedua tangannya sedangkan makmum memandang disyari’atkannya mengangkat kedua tangan- maka tidak mengapa bagi makmum untuk mengangkat kedua tangannya. Karena hal ini tidak mengakibatkan penyelisihan terhadap imam atau keterlambatan (dalam mengikuti imam).
Demikian juga halnya dalam masalah duduk, jika imam tidak duduk tawarruk sedangkan sang makmum memandang disyari’atkannya duduk tawarruk atau sebaliknya maka sang makmum tidak mengikuti sang imam, karena sang makmum tidak menyelisihi sang imam dan juga tidak terlambat (dalam mengikuti sang imam). ([43])
Bagaimana jika sang imam tidak duduk istirahat?
Jika sang imam tidak duduk istirahat tatkala bangkit ke rakaat ke dua atau ke rakaat ke empat, sedangkan makmum memandang disyari’atkannya hal ini, maka apakah makmum tetap boleh duduk istirahat menyelisihi imam? Dan bagaimana jika perkaranya sebaliknya?
Syaikh Al-‘Utsaimiin rahimahullah berkata, “Adapun jika (penyelisihan gerakan-pent) mengakibatkan keterlambatan makmum –misalnya makmum memandang disyari’atkannya duduk istirahat sementara sang imam tidak- maka makmum tidak duduk istirahat. Karena jika sang makmum duduk istirahat maka ia akan terlambat dari imam, padahal Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintah kita untuk bersegera dalam mengikuti imam, beliau bersabda, “Jika imam bertakbir maka bertakbirlah kalian, dan jika imam ruku maka ruku’lah…”. Demikian juga jika perkaranya sebaliknya. Jika imam memandang disyari’atkannya duduk istirahat sementara sang makmum tidak, maka jika imam duduk istirahat hendaknya sang makmum juga duduk meskipun sang makmum tidak memandang disyari’atkannya duduk istirahat, namun demi mengikuti imam. Inilah kaidah dalam mengikuti imam, yaitu makmum tidak melakukan hal yang menyebabkan penyelisihan atau keterlambatan” ([44])
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, “Telah valid bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam duduk istirahat, akan tetapi para ulama berselisih antara apakah Nabi melakukannya karena beliau sudah tua sehingga butuh untuk duduk istirahat?, ataukah Nabi melakukannya karena duduk istirahat merupakan sunnah dalam sholat?. Barangsiapa yang berpendapat dengan kemungkinan kedua maka menganggap duduk istirahat hukumnya mustahab sebagaimana pendapat As-Syafi’i dan salah satu riwayat dari Ahmad. Dan barangsiapa yang berpendapat dengan kemungkinan pertama maka tidak menganggap mutahabnya duduk istirahat kecuali jika memerlukannya sebagaimana pendapat Abu Hanifah, Malik, dan salah satu riwayat dari Ahmad.
Barangsiapa yang melakukan duduk istirahat maka tidak boleh diingkari meskipun posisinya sebagai makmum (sementara imam tidak melakukannya-pent) karena keterlambatannya mengikuti (imam yang tidak duduk istirahat) hanya sedikit dan tidak termasuk keterlambatan yang dilarang –menurut mereka yang berpendapat akan mustahabnya duduk istirahat-. Bukankah ini perbuatan yang merupakan perkara ijtihad? Karena sesungguhnya telah bertentangan antara melakukan sunnah ini –yaitu menurutnya- dengan bersegera mengikuti imam?, sesungguhnya mengikuti imam lebih utama daripada terlamabat. Akan tetapi keterlambatan tersebut hanya sedikit, maka perkaranya seperti jika imam berdiri dari tasyahhud awal sebelum makmum menyelesaikan (bacaan) tasyahhud awal padahal makmum memandang mustahabnya menyempurnakan bacaan tasyahhud awal (sehingga akhirnya sang makmum terlambat beridiri-pent). Atau seperti jika imam salam padahal sang makmum masih ingin berdoa sedikit lagi, apakah sang makmum segera salam ataukah menyempurnakan dahulu doanya?. Permasalahan-permasalahan seperti ini termasuk permasalahan ijtihad, dan yang paling kuat adalah bersegera mengikuti imam lebih utama dari pada terlambat karena melakukan perkara yang mustahab. Wallahu A’lam([45]) .
Bagaimana jika sang imam qunut subuh?
Ibnu Taimiyyah berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ “Hanyalah dijadikan imam untuk diikuti” dan juga bersabda لاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَى أَئِمَّتِكُمْ “Janganlah kalian menyelisihi imam-imam kalian”, dan telah valid juga dalam shahih bahwasanya beliau bersabda يُصَلُّوْنَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوْا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَأُوْا فَلَكُمْ، وَعَلَيْهِمْ “Mereka (para imam) sholat bagi kalian, jika mereka benar maka pahalanya buat kalian dan buat mereka, dan jika mereka salah maka pahalanya bagi kalian dan kesalahan bagi mereka. Bukankah jika imam membaca surat setelah membaca Al-Fatihah pada dua rakaat yang terakhir dan memanjangkan bacaan surat tersebut maka wajib bagi makmum untuk mengikutinya (menunggunya-pent)?. Adapun mendahului imam maka hal ini tidak diperbolehkan, maka jika imam qunut maka tidak boleh makmum mendahuluinya, akan tetapi harus mengikuti imam. Oleh karenanya Abdullah bin Mas’uud mengingkari Utsman karena sholat empat rakaat (tatkala safar-pent) akan tetapi beliau sholat empat rakaat diimami oleh Utsman. Maka dikatakan kepada beliau kenapa beliau berbuat demikian, maka beliau berkata الخِلاَفُ شَرٌّ Perselisihan itu buruk” ([46])
Beliau juga berkata, “Wajib bagi makmum untuk mengikuti imam pada perkara-perkara yang diperbolehkan ijtihad msekipun sang makmum tidak sependapat. Sebagaimana jika imam qunut subuh atau menambah jumlah takbir tatkala sholat janazah hingga tujuh kali. Akan tetapi jika sang imam meninggalkan satu perkara yang perkara tersebut menurut makmum adalah rukun atau syarat sholat maka ada khilaf (apakah makmum tetap mengikuti imam atau tidak?-pent)” ([47])
Syaikh Ibnu ‘Utsaimin berkata, “Lihatlah para Imam (kaum muslimin) yang benar-benar memahami nilai persatuan. Imam Ahmad rahimahullah berpendapat qunut shalat Subuh adalah bid’ah. Meskipun demikian beliau berkata, “Jika engkau shalat di belakang Imam yang qunut maka ikutilah qunutnya, dan aminkanlah doa imam tersebut.” Semua ini demi persatuan barisan dan hati, serta agar tidak timbul kebencian antara sebagian kita terhadap sebagian yang lain.” ([48])
FOOTNOTE:
========================================
([3]) Lihat penjelasan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 2/171
([4]) Ini adalah pendapat ulama Syafi’iyyah, mereka berpendapat bahwa: anak kecil yang telah mencapai tamyiiz, maka sah menjadi imam secara muthlaq, baik dalam shalat wajib maupun shalat sunnah. Dan Al-Buwaitiy menetapkan dimakruhkannya menjadikan seorang anak kecil sebagai imam (Nihayatul Muhtaj Li As-Syirbini 2/168 dan Kassyaful Qina’ Li Al-Buhutiy 1/480). Adapun salah satu riwayat dari Imam Ahmad hanya sah untuk shalat sunnah saja, seperti shalat gerhana atau tarawih. (Mughni Al-Muhtaj Li As-Syirbini 1/229,240, Nihayatul Muhtaj Li Ar-Ramliy 2/168 dan Kassyaful Qina’ Li Al-Buhutiy 1/480.)
([6]) Lihat: Syarh Al-Bukhari Li Ibni Batthal 2/299,307 dan Syarh Sunan Abu Dawud Li Ibni Ruslan 3/638.
([7]) (أَقْرَؤُهُم) artinya adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur’annya sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang disebutkan dalam shahih Bukhari no.4302:
وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآناً
Hendaklah yang menjadi imam shalat kalian yang paling banyak hafalan Al-Qur’annya. (Fathul bari Li Ibni Rajab 6/114)
([9]) Lihat: Nailul Authar Li As-Syaukani 3/197.
([10]) Menurut Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah. Dan menurut pendapat yang paling dipilih oleh Hanafiyyah adalah bahwa seorang anak kecil secara muthlaq tidak diperbolehkan untuk memimpin shalat, meskipun telah mencapai usia baligh atau mumayyiz, baik dalam shalat fardhu ataupun shalat sunnah. (Lihat: Fathul Qadir Li Al-Kamal bin Al-Humam 1/310, Tabyinul Haqaiq Li Az-Zaila’i 1/140, Hasyiyyah At-Thahthawi ‘ala Muraqi Al-Falah hal.157, Syarh Mukhtashar Khalil 1/78 dan Kassyaful Qina’ Li Al-Buhutiy 1/480)
([11]) H.R. Abu Dawud no.4402 dan dishahihkan oleh Al-Albani
([12]) Minhaju As-Sunnah Li Ibni Taimiyyah 6/49
([13]) Fathul Bari Li Ibni Hajar 2/186 dan lihat: Al-Umm Li As-Syafi’I 1/193.
([14]) Al-Majmu’ Li An-Nawawi 4/131.
([16]) al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab 3/327
([17]) Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah No.17227 5/332
([18]) Syarhun Nawawi alaa muslim 4/105
([19]) Majmu’ fatawa Bin Baz 12/129
([22]) Disebutkan dalam Tahdzibul Lughoh 1/239:
العِلج: الرجل القويّ الضّخم
“al-‘ilju: lelaki kuat yang besar.”
([23]) Disebutkan dalam Ghoribul Hadits Libnil Jauzy 1/68
الْبُرْنُس كسَاء
“al-Burnus adalah pakaian” (yaitu kain yang lebar)
([25]) Majmu’ fatawa bin baz 12/138
([26]) Al-Asilatu Wal Ajwibatu Al-Fiqhiyyah 1/105
([27]) HR. Abu Daud no. 233 dan dishahihkan al-Albani
([29]) Fatawa al-lajnah ad-daimah 7/128
([30]) Majmu’ Fatawa Wa Rosaila Al-Utsaimin 14/20
Dan dijelaskan olehal-Buhuty bahwa hukum untuk kembalinya imam ketika bangkit ke raka’at kelima ketika diingatkan oleh makmum ada dua kondisi:
Pertama: wajib kembali, yaitu jika diingatkan oleh 2 makmum yang tsiqoh
Kedua: tidak wajib kembali, yaitu ketika diingatkan oleh makmum yang imam menyangka bahwa makmum yang telah salah, atau yang mengingatkan berbeda-beda (mungkin contohnya ada makmum yang menyalahkan dan ada yang tidak menyalahkan), dan yang lainnya.
Dan dikatakan jika imam enggan untuk kembali pada hukum yang pertama maka shalatnya batal, berkata al-Buhuty:
(فَإِنْ أَبَاهُ) أَيْ: الرُّجُوعَ (إمَامٌ) وَجَبَ عَلَيْهِ (قَامَ ل) رَكْعَةٍ (زَائِدَةٍ) مَثَلًا (بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) لِتَعَمُّدِهِ تَرْكَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ
“jika imam enggan untuk kembali kepada suatu yang telah wajib baginya untuk kembali (seperti bangkit untuk raka’at kelima) maka shalatnya batal, karena ia telah menyengaja meninggalkan suatu yang wajib baginya.” (Syarhu Muntahal Iroodaat 1/223)
([34]) Al-Inshof Fii Makrifatir Roojih Minal Khilaf 2/36, lihat juga Al-Mughni, Ibnu Qudamah 2/172
([35]) Ad-Duror As-Saniyyah Fil Ajwibatin Najdiyyah 4/277
([36]) Lihat: Asy-Syarhul Mumti’ 2/317
([42]) Lihat Fathul Baari 2/178
([43]) Majmuu’ Fataawaa wa rosaail As-Syaikh Al-‘Utsaimiin15/79
([44]) Majmuu’ Fataawaa wa rosaail As-Syaikh Al-‘Utsaimiin 15/79
([45]) Majmuu’ Al-Fataawaa, Ibnu Taimiyyah 22/452-453