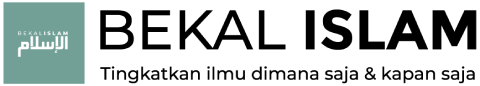Shalat Orang Yang Sakit
Pendahuluan
Shalat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh semua umat Islam, kewajibannya tidak akan pernah gugur selama orang tersebut berakal dan tidak ada penghalang syar’i yang membolehkannya untuk meninggalkan shalat. Dalil wajibnya adalah firman Allah,
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’”. ([1])
Ada beberapa kelompok yang masuk dalam golongan yang mendapatkan udzur, di antaranya adalah; orang yang sakit, musafir, wanita yang sedang haid, dan orang yang takut. Sehingga mereka tidak bisa melaksanakan shalat dengan tata cara yang sempurna atau terhalang darinya secara keseluruhan, contohnya wanita yang haid. Rasulullah shallallāhu ‘alaihi wasallam bersabda tentang wanita haid:
أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ، وَلَمْ تَصُمْ
“Bukankah bila seorang di antara kalian jika ia haid ia tidak shalat dan tidak puasa”. ([2])
Adapun orang yang sakit sedangkan dia mukallaf, maka selama kesadarannya terjaga wajib baginya melaksanakan shalat wajib. Ada beberapa perbedaan tata cara shalat antara orang yang sakit dengan orang yang sehat, karena orang yang sakit mendapat keringanan.
Batasan sakit yang mendapat keringanan
Orang yang sakit mendapatkan udzur dalam shalatnya, tetapi pertanyaannya adalah: Apakah semua orang yang sakit masuk dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan udzur?
Maka patokannya adalah: Sakit yang dapat menyebabkan bertambah rasa sakitnya atau menyebabkan lama sembuhnya jika melakukan gerakan tertentu. Lihat: Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Quwaitiyyah 27/259
Keringanan Bagi Orang Yang Sakit
Dalil-dalil secara umum bahwa syariat Islam adalah mudah:
Allah Ta’āla berfirman:
فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ
“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu” ([3])
Dalam ayat yang lain:
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini suatu kesulitan (keberatan)” ([4])
Dalam ayat yang lain:
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” ([5])
Dan juga dalam ayat yang lain:
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” ([6])
Juga dijelaskan dalam hadits Abu Huroiroh bahwa Rasulullah shallallāhu ‘alaihi wasallam bersabda:
وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ
“Dan apabila aku perintahkan kalian sebuah perkara maka kerjakanlah semampu kalian.” ([7])
Juga dalam riwayat lain:
فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ
“Dan apabila aku perintahkan kalian sesuatu maka kerjakanlah semampu kalian.” ([8])
Diperbolehkan tidak shalat berjamaah di masjid. ([9])
Dalilnya adalah ketika Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam sakit parah, beliau tidak shalat di masjid, padahal beliau adalah imam. Beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan sebagai imam. Aisyah radhiallahu’anha berkata:
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ»
“Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam ketika sakit beliau memerintahkan agar Abu Bakar mengimami shalat orang-orang.” ([10])
Ibnu Abbas radhiallahu’anhu mengatakan:
لقد رَأيتُنا وما يتخلَّفُ عن الصَّلاةِ إلا منافقٌ قد عُلِمَ نفاقُهُ أو مريضٌ
“Aku melihat bahwa kami (para sahabat) memandang orang yang tidak shalat berjama’ah sebagai orang munafik, atau sedang sakit” ([11])
Dan dalil-dalil yang lain yang menunjukan bahwa orang yang sakit apabila ia kesulitan untuk mendatangi shalat berjama’ah maka boleh baginya untuk tidak melakukan shalat berjama’ah.
Diperbolehkan menjamak shalat.
Apabila orang yang sakit mendapatkan kesulitan untuk melaksanakan shalat di setiap waktunya maka boleh baginya untuk menjamak antara zhuhur dan ashar dengan jamak taqdim atau ta’khir, menjamak antara maghrib dan ‘isya dengan jamak taqdim atau ta’khir. Adapun shalat subuh tidak bisa dijamak dengan shalat yang setelahnya atau dengan shalat yang sebelumnya, karena waktunya terpisah dengan shalat yang sebelum dan setelahnya.
Mu’adz bin Jabal radhiallahu’anhu beliau mengatakan:
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا، وَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قُلْتُ: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: ” أَرَادَ أَنْ لَا تُحْرَجَ أُمَّتُهُ ”
“Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam keluar dalam sebuah safar yaitu pada Perang Tabuk. Lalu beliau menjamak shalat Zhuhur dan shalat Ashar, dan menjamak shalat Maghrib dan Isya, lalu aku bertanya: Apa yang menyebabkan hal tersebut? Ia menjawab: Beliau tidak ingin memberatkan umatnya.” ([12])
Dibolehkan melakukan shalat dengan cara sesuai dengan kondisinya.
-
- Shalat dengan duduk
Berdiri dalam shalat fardhu adalah rukun, tidak boleh ditinggalkan. Berdiri tidak wajib dalam beberapa keadaan, di antaranya ketika shalat sunnah, ketika seorang sakit dan memberatkan baginya shalat dengan posisi berdiri, maka boleh baginya untuk shalat dengan posisi duduk. Dasarnya adalah hadits Imron bin Hushoin -radhiyallahu ‘anhu- bahwasanya Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
«صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»
“Shalatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka duduk, jika tidak mampu maka sambil berbaring”. ([13])
Imam Nawawi menjelaskan: “Shalat dengan duduk tidak disyaratkan jika seorang benar-benar tidak mampu berdiri, tetapi tidak boleh dilakukan hanya karena merasa kesulitan pada tingkatan yang paling rendah. Yang menjadi patokan adalah kesulitan yang tampak jelas, jika dia merasa khawatir mengalami kesulitan yang parah, sakitnya akan bertambah, atau yang serupa dengannya, atau bagi orang yang bepergian dengan kapal laut dan khawatir tenggelam atau pusing (mabuk laut), maka dia boleh melaksanakan shalat dengan duduk dan tidak perlu mengulangi shalatnya”. ([14])
- Shalat dengan berbaring
Jika tidak mampu duduk, dibolehkan shalat sambil berbaring, dengan cara miring menghadap kiblat dengan wajahnya([15]), dan diutamakan berbaring pada sisi kanan.
Sebagaimana hadits di atas:
«صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»
“Shalatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka duduk, jika tidak mampu maka dengan berbaring”. ([16])
Diutamakan berbaring dengan sisi kanan karena kanan lebih tepat untuk perkara-perkara yang baik. Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata:
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ
“Dahulu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam amat menyukai memulai dengan kanan dalam mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci dan dalam segala urusannya”. ([17])
Namun jika terasa susah berbaring di atas lambung kanan, dan lebih mudah berbaring di atas lambung kiri maka tidak mengapa.


- Shalat dengan terlentang
Diperbolehkan shalat dengan posisi telentang jika tidak mampu berbaring dengan posisi miring. Dasarnya hadits ‘Imron Ibn Hushoin di atas dengan tambahan pada riwayat lain:
فإن لم تستطع فمستلقياً، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها
“Apabila tidak mampu maka dengan berbaring, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. ([18])

- Shalat dengan berisyarat
Boleh shalat hanya dengan berisyarat dengan kepala sebagaimana yang dijelaskan Jabir radhiallahu’anhu:
عاد صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مريضًا فرآه يصلي على وسادةٍ، فأخذها فرمى بها، فأخذ عودًا ليصلي عليه، فأخذه فرمى به، وقال: صلِّ على الأرضِ إن استطعت، وإلا فأوم إيماءً، واجعل سجودَك أخفضَ من ركوعِك
“Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam suatu kala menjenguk orang yang sedang sakit. Ternyata Rasulullah melihat ia sedang shalat di atas bantal. Kemudian Nabi mengambil bantal tersebut dan menjauhkannya. Ternyata orang tersebut lalu mengambil kayu dan shalat di atas kayu tersebut. Kemudian Nabi mengambil kayu tersebut dan menjauhkannya. Lalu Nabi bersabda: shalatlah di atas tanah jika kamu mampu, jika tidak mampu maka shalatlah dengan isyarat. Jadikan posisi sujudmu lebih rendah dari rukukmu.“ ([19])
Dan juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Umar,
إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيضُ السُّجُودَ، أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، وَلَمْ يَرْفَعْ إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئًا
“Apabila orang yang sakit tidak mampu sujud, hendaklah dia berisyarat dengan kepalanya dan tidak mengangkat apapun ke keningnya.” ([20])
- Shalat dengan kedipan mata
Berkata Ibnu Qudamah
وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِيمَاءِ بِرَأْسِهِ، أَوْمَأَ بِطَرَفِهِ، وَنَوَى بِقَلْبِهِ، وَلَا تَسْقُطُ الصَّلَاةُ عَنْهُ مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا
“dan jika seseorang tidak mampu untuk berisyarat dengan kepalanya, maka ia berisyarat dengan matanya dan meniatkan dengan hatinya, dan shalat tidak gugur darinya selama ia masih tersadar.” ([21])
- Shalat dalam hati
Jika orang yang sakit tidak mampu shalat dengan semua keadaan yang telah disebutkan makai a shalat dengan hatinya, ia bertakbir, membaca surat dan meniatkan untuk ruku’, sujud, berdiri, dan duduk dengan hatinya, karena shalat tidak gugur darinya selama ia masih tersadar. ([22])
- Dibolehkan tidak menghadap kiblat jika tidak mampu dan tidak ada yang membantunya
Ketika ada sebuah keadaan yang menyebabkan seseorang tidak bisa menghadap kiblat maka boleh baginya untuk tidak menghadap kiblat. Salah satunya adalah orang yang sakit ketika tidak ada kemampuan juga tidak ada yang menolongnya untuk shalat menghadap kiblat maka boleh shalat semampunya. ([23])
Kesimpulan:
Orang yang sakit memiliki keadaan yang berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya. Dari keterangan di atas, kita dapati bahwasanya dalam segi gerakan shalat, orang yang sakit bisa melakukan shalat dengan cara duduk, atau berbaring ke samping, terlentang, shalat dengan isyarat, dengan kedipan mata, atau dengan hatinya. Ini sesuai kondisi yang dibutuhkan oleh orang yang sakit.
Adapun cara-cara lain, seperti dengan isyarat telunjuk maka ini tidak ada dalilnya juga tidak ada satu ulamapun yang mengatakannya. Berkata syaikh Utsaimin
فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود أشار بعينيه، فيغمض قليلاً للركوع، ويغمض تغميضاً أكثر للسجود. وأما الإشارة بالأصبع كما يفعله بعض المرضي فليس بصحيح ولا أعمل له أصلاً من الكتاب، والسنة، ولا من أقوال أهل العلم.
“dan jika seseorang tidak mampu untuk berisyrat dengan kepalanya untuk ruku’ dan sujud, makai a berisyarat dengan kedua matanya, ia memejamkan sebentar untuk ruku’ dan memejamkannya lebih lama dari sujud, dan adapun berisyarat dengan jari sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang sakit maka ini tidak benar, dan aku tidak mengetahui landasannya dari Al-Kitab, As-Sunnah, dan dari perkataan-perkataan para Ulama.” ([24])
Permasalahan Berkaitan dengan Shalatnya Orang Sakit
Shalat bagi orang yang sakit tapi mampu berdiri
Ada beberapa kondisi:
Pertama: Orang yang sakit apabila shalat dengan posisi berdiri tidak khawatir sakitnya akan bertambah, maka wajib baginya untuk berdiri dan shalat seperti biasanya.
Kedua: Apabila tidak mampu berdiri kecuali dengan bantuan tongkat, maka tetap wajib baginya shalat berdiri menggunakan tongkat atau berdiri sambil bersandar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Ummu Qois binti Mihshon:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ، اتَّخَذَ عَمُودًا فِي مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ
“Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika sudah berusia lanjut dan lemah beliau memasang tiang di tempat shalat untuk dijadikan sandaran”. ([25])
Ketiga: Ketika mampu berdiri tapi dengan membungkuk, maka wajib baginya berdiri dengan keadaan tersebut. Berdasarkan hadits ‘Imron bin Hushain radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
«صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»
“Shalatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka duduk, jika tidak mampu maka dengan berbaring”. ([26])
Keempat: Orang yang sakit mampu berdiri akan tetapi tidak mampu untuk melakukan ruku’ dan sujud, maka wajib baginya untuk shalat dengan posisi berdiri. ([27])
Shalat bagi orang yang tidak mampu berdiri
Ibnu Qudamah mengatakan bahwasanya para ulama sepakat bahwa orang yang tidak mampu shalat dengan posisi berdiri boleh baginya dengan posisi duduk ([28]).
Disunnahkan duduk dengan posisi tarobbu’ (bersila), berdasarkan hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا
“Aku melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melaksanakan shalat dengan duduk bersila”. ([29])
Shalat orang yang tidak mampu berdiri ataupun duduk
Ada beberapa kondisi:
Pertama: Orang yang tidak mampu shalat dengan posisi berdiri maupun duduk maka boleh baginya untuk shalat dengan posisi berbaring dengan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, dan lebih utama dengan posisi berbaring menyamping dengan bagian kanan.
Kedua: Apabila tidak mampu shalat dengan posisi berbaring maka diperbolehkan untuk shalat dengan posisi terlentang dengan kedua kakinya menghadap ke arah kiblat, jika mampu posisi kepalanya sedikit diangkat dengan cara diganjal sesuatu agar wajahnya bisa menghadap ke arah kiblat maka ia melakukannya, dengan meletakkan kedua tangannya di dada ketika bersedekap dan meletakkan keduanya di lutut ketika ruku’, dan apabila tidak bisa menghadap ke kiblat maka shalat semampunya. ([30])
Mampu melakukan sesuatu yang sebelumnya dia tidak mampu
Apabila orang yang sakit di tengah shalatnya mampu untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya dia tidak mampu, maka wajib untuk melakkukannya. Misalnya seorang yang sakit melakukan shalat dengan posisi duduk karena dia merasa keberatan shalat dengan posisi berdiri, lalu di tengah shalatnya dia merasa mampu untuk berdiri, maka wajib baginya untuk melanjutkan shalatnya dengan posisi berdiri tanpa harus membatalkan shalat sebelumnya.
Berkata Ibnu Qudamah
وَمَتَى قَدَرَ الْمَرِيضُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، عَلَى مَا كَانَ عَاجِزًا عَنْهُ، مِنْ قِيَامٍ، أَوْ قُعُودٍ، أَوْ رُكُوعٍ، أَوْ سُجُودٍ، أَوْ إيمَاءٍ، انْتَقَلَ إلَيْهِ، وَبَنَى عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ. وَهَكَذَا لَوْ كَانَ قَادِرًا، فَعَجَزَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، أَتَمَّ صَلَاتَهُ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ؛ لِأَنَّ مَا مَضَى مِنْ الصَّلَاةِ كَانَ صَحِيحًا، فَيَبْنِي عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ حَالُهُ.
“dan kapanpun orang yang sakit memiliki kemampuan di pertengahan shalatnya yang dia tidak mampu sebelumnya berupa berdiri, duduk, ruku’, sujud, atau berisyarat, maka ia pindah kepada yang ia mampu tersebut, dan ia tetap lanjutkan terhadap shalat yang sebelumnya, dan begitu juga seandainya ia mampu (di awal shalatnya) kemudian tidak mampu dipertengahan shalatnya, makai a sempurnakan shalatnya sesuai dengan keadaannya, karena apa yang telah lalu dari shalatnya sah, maka ia tetap membangun shalat dengan yang telah lalu sebagaimana seandainya keadaannya berubah. ([31])
Tidak mampu sujud langsung di atas lantai, bolehkah mengambil sesuatu untuk sujud di atasnya?
Orang yang tidak mampu untuk sujud di atas lantai maka tidak boleh baginya mengambil sesuatu agar bisa sujud di atasnya. Sebagaimana yang dijelaskan Jabir radhiallahu’anhu di atas:
عاد صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مريضًا فرآه يصلي على وسادةٍ، فأخذها فرمى بها، فأخذ عودًا ليصلي عليه، فأخذه فرمى به، وقال: صلِّ على الأرضِ إن استطعت، وإلا فأوم إيماءً، واجعل سجودَك أخفضَ من ركوعِك
“Rasulullah shallallāhu ‘alaihi wasallam suatu ketika menjenguk orang yang sedang sakit. Ternyata Rasulullah melihat ia sedang shalat di atas bantal. Kemudian Nabi mengambil bantal tersebut dan menjauhkannya. Ternyata orang tersebut lalu mengambil kayu dan shalat di atas kayu tersebut. Kemudian Nabi mengambil kayu tersebut dan menjauhkannya. Lalu Nabi bersabda: Shalatlah di atas tanah jika kamu mampu, jika tidak mampu maka shalatlah dengan isyarat. Jadikan kepalamu ketika posisi sujud lebih rendah dari rukukmu.“ ([32])
Apakah orang yang sakit mendapatkan udzur untuk meninggalkan shalat?
Orang yang sakit selama kesadarannya masih terjaga maka shalat tetap wajib baginya untuk melaksanakan shalat. Tidak boleh baginya meninggalkan shalat, karena ancaman orang yang meninggalkan shalat sangat besar. ([33])
Tertidur sehingga luput darinya beberapa shalat
Apabila ada shalat yang terlewat karena sakit sehingga tertidur maka ia melakukan shalat tersebut ketika ingat, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Anas Bin Malik:
إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى
“Jika salah seorang di antara kalian tertidur atau lalai dari shalat, maka hendaklah ia shalat ketika ia ingat. Karena Allah berfirman (yang artinya), “Kerjakanlah shalat ketika ingat.” ([34])
Pingsan atau koma
Salah satu pengaruh rasa sakit bisa menyebabkan seseorang kehilangan kesadarannya, entah itu pingsan atau bahkan bisa menyebabkan koma. Maka dalam keadaan seperti ini ia hanya cukup mengerjakan shalat pada waktunya yang ia sadar, adapun shalat-shalat sebelumnya yang telah berlalu waktunya maka tidak wajib baginya untuk mengqodhonya. Dalilnya perbuatan sahabat Ibnu Umar ketika ia pingsan ia tidak mengqodho shalat yang telah luput,
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَلَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ ” قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ ذَهَبَ وَأَمَّا مَنْ أَفَاقَ وَهُوَ فِي وَقْتٍ فَإِنَّهُ يُصَلِّي هَكَذَا فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ عَنْ نَافِعٍ وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَفِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
“sesungguhnya Abdullah bin Umar pingsan dan hilang kesadarannya, lalu ia tidak mengqodho shalatnya, dan berkata Malik: dan hal tersebut karena waktu telah berlalu, dan adapun orang yang tersadar dan dia berada di waktu shalat maka ia melaksanakan shalat tersebut, begitu juga dalam riwayat dari jama’ah dari Nafi’ dan dalam riwayat Ubaidillah bin Umar dari Nafi’: satu hari satu malam, dan dalam riwayat Ayyub dari Nafi’: tiga hari.” ([35])
FOOTNOTE:
======================================
([9]) Bagi yang berpendapat wajibnya shalat berjama’ah, karena seperti yang dijelaskan dalam pembahasan shalat berjama’ah bahwasanya para ulama berbeda pendapat.
([12]) HR. Ahmad no. 21997, sanadnya shohih dengan syarat muslim.
Syaikul Islam Ibnu Taimiyah berkata:
وَأَمَّا الْجَمْعُ فَسَبَبُهُ الْحَاجَةُ وَالْعُذْرُ، فَإِذَا احْتَاجَ إلَيْهِ جَمَعَ فِي السَّفَرِ الْقَصِيرِ، وَالطَّوِيلِ وَكَذَلِكَ الْجَمْعُ لِلْمَطَرِ وَنَحْوِهِ، وَلِلْمَرَضِ وَنَحْوِهِ، وَلِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْبَابِ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ رَفْعُ الْحَرَجِ عَنْ الْأُمَّةِ
“Adapun menjamak shalat, maka sebabnya adalah karena ada kebutuhan dan udzur, apabila seseorang membutuhkan untuk menjamak shalat maka boleh baginya untuk menjamak seperti dalam safar yang pedek atau yang jauh, menjamak ketika hujan, menjamak karena sakit, dan karena sebab-sebab lainnya, karena intinya adalah mengangkat kesulitan untuk ummat.” (Al Fatawa al-kubro 2/132)
([15]) lihat: sholatul maridh fii dhoui ak-kitaabi was sunnah karya Syaikh Sa’id al-Qohthoni hal 26
([18]) berkata syaikh Al-Albani mengenai hadits ini
ولم أجده في ” سننه الصغرى “؛ فلعله في ” الكبرى ” له
“Aku belum mendapatkan dalam sunan sughronya, mudah-mudahan hadits ini terdapat dalam sunan kubronya.” (Ashlu shifati sholatin nabi 1/91)
([19]) HR. Al Baihaqi dalam Al Kubra 2/306
Para ulama berbeda pendapat apakah hanya hanya iimaa’ (isyarat) dengan kepala saja atau dibarengi dengan menundukkan punggung juga?
Pendapat pertama: Isyarat dengan kepala saja. Ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Malik Ats-Tsa’alaby ketika menjelaskan macam-macam isyarat:
أَشَارَ بِيَدِهِ. أَوْمَأ بِرَأسِهِ. غَمَزَ بِحَاجِبِهِ. رَمَزَ بِشَفَتِهِ. لَمَعَ بِثَوْبِهِ. أَلاحَ بِكُمِّهِ
“Isyarat dengan tangan asyaaro, dengan kepala awma-a, dengan alis ghomaza, dengan bibir romaza, dengan baju lama’a, dan dengan lengan bajunya alaaha” (Lihat: Fiqhul Lughoh Wa Sirrul Arobiyyah 1/133)
Dan juga perkataan dari Ibnu ‘Umar:
إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيضُ السُّجُودَ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، وَلَمْ يُرْفَعْ إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئاً.
“Jika orang yang sakit tidak mampu sujud maka ia berisyarat dengan kepalanya, dan tidak diangkat sesuatu apapun ke keningnya.” (Muwaththo imam Malik no. 581)
Dan juga perkataan Ibnu Mas’ud ketika mengunjungi saudaranya yaitu ‘Utbah ketika sakit:
«أَوْمِئْ إِيمَاءً حَيْثُ مَا يَبْلُغُ رَأْسُكَ»
“Berisyaratlah sebatas kemampuan kepalamu.” (Mushonnaf Ibnu Abu Syaibah no 2835)
Pendapat kedua: Isyarat dengan kepala dan punggung. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari madzhab Malikiyyah, syafi’iyyah dan Hanabilah.
Berkata Ibnu Sahnun: Aku bertanya kepada Ibnul Qasim: Bagaimana al-ima’, apakah dengan kepala tanpa punggung? Ia menjawab: Dengan punggungnya dan kepalanya. Aku bertanya: Apakah ini perkataan Malik? Ia menjawab: Iya. (Al-Mudawwanah 1/172)
Berkata imam Syafi’i:
فإذا كان بظهره مرض لا يمنعه القيام ويمنعه الركوع لم يجزه إلا أن يقوم وأجزأه أن ينحني كما يقدر في الركوع
“Maka jika di punggungnya terdapat penyakit yang tidak menghalangi untuk berdiri, akan tetapi menghalanginya untuk ruku’, maka tidak cukup kecuali harus dengan berdiri, dan cukup dengan menunduk semampunya untuk ruku’.” (Al-umm 1/100)
Berkata Ibnu Qudamah:
فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، يقرب وجهه من الأرض في السجود قدر طاقته
“Maka jika seseorang tidak mampu untuk ruku’ dan sujud ia berisyarat dengan keduanya, dan menjadikan sujudnya lebih rendah dari ruku’nya, ia dekatkan wajahnya ke tanah ketika sujud sebatas kemampuannya.” (Al-Kafi 1/314)
Dan juga terdapat atsar yang menguatkan pendapat mayoritas ulama yaitu atsar dari ‘Atho:
«إِذَا صَلَّى الْمَرِيضُ جَالِسًا فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا اسْتَطَاعَ»
Asy-Syaikh al-‘Utsaimin berkata, “Dalil akan hal ini, bahwasanya kita diperintahkan untuk sujud, dan kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah semampu kita. Maka jika kita mampu untuk mendekat (menunduk) hingga mendekati sujud yang sempurna maka wajib bagi kita untuk mendekat…. adapun jika kita tidak mampu untuk mendekat ke tanah…maka kita diwajibkan tatkala itu untuk sekedar memberi isyarat” (Asy-Syarh al-Mumti’ 3/117)
([21]) Al-Mughni libni Qudamah 2/109-110
([22]) lihat: shalatul maridh fii dhouil kitab was sunnah hal:28
“Jika orang yang sakit shalat dalam keadaan duduk, jika ruku’ maka ia letakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, dan jika sujud maka ia letakkan kedua tangannya di atas tanah jika mampu.” (Mushonnaf Abdurrozzaq no. 4133)
Dan ketika meletakkan kedua tangan ke tanah, ini melazimkan tidak hanya kepala yang ditundukkan, akan tetapi melazimkan untuk menundukkan punggung juga. Begitu juga atsar dari Qotadah:
«إِذَا رَكَعَ الْمَرِيضُ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ»
“Dan jika orang yang sakit ruku’ maka ia letakkan kedua tangannya di atas lututnya, dan jika sujud ia letakkan kedua tangannya di atas tanah.” (Mushonnaf Abdurrozzaq no. 4134)
Nampak pendapat kedua lebih kuat, yaitu pendapat bahwa isyarat dengan kepala dan punggung.
([23]) Menghadap kiblat adalah salah satu syarat sah shalat, ketika seorang meninggalkannya secara sengaja maka shalatnya tidak sah, tetapi perlu diketahui bahwa syarat-syarat sah shalat bisa gugur dalam beberapa keadaan (kecuali niat karena tidak ada udzur yang bisa menghalangi niat) adapun selainnya maka ada kemungkinan gugur, seperti contohnya “menghadap kiblat”. Berdasarkan firman Allah Ta’āla:
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (QS. Al-Baqarah : 286)
([24]) Fatawa Arkanul Islam Hal 379
([25]) HR. Abu Daud No. 948, dishohihkan oleh Al-Albani
Hamlul lahm adalah lemah atau banyak daging (gemuk). (Lihat ‘Aunul Ma’bud Syarh Sunan Abu Daud 3/158)
Berkata Badruddin Al-Aini: Berdasarkan hadits ini, ashab (ulama Hanafiyah) mengatakan: “Sesungguhnya orang yang lemah atau orang yang tua apabila mampu (shalat) berdiri dengan bersandar kepada sesuatu, maka ia shalat berdiri dengan bersandar dan tidak shalat sambil duduk”. Dan disebutkan dalam kitab Al-Khulashoh: “Jika seseorang mampu berdiri dalam keadaan bersandar maka ia shalat dengan berdiri dan bersandar, dan tidak boleh shalat dengan cara lain, begitu juga apabila mampu untuk bersandar kepada tongkat atau dia memiliki pembantu jika bersandar kepadanya dia mampu untuk shalat sambil berdiri, maka dia shalat dengan berdiri.” (Lihat: Syarh Sunan Abu Daud 4/217)
‘Iroq bin Malik berkata:
«أَدْرَكْتُ النَّاسَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تُرْبَطُ لَهُمُ الْحِبَالُ يَتَمَسَّكُونَ بِهَا مِنْ طُولِ الْقِيَامِ»
“Aku menjumpai orang-orang pada Bulan Ramadhan mengikatkan tali untuk berpegangan dengannya karena lamanya berdiri.” (Lihat: ‘Aunul Ma’bud Syarh Sunan Abu Daud 3/158)
‘Ashim bin Samih berkata: “Aku melihat Abu Sa’id Al-Khudry shalat dengan bersandar pada tongkat”. (Lihat: Syarh Sunan Abu Daud 4/217)
([27]) Adapun untuk ruku’nya maka boleh dengan menundukkan badannya sedikit dalam keadaan masih berdiri, dan ketika datang waktu untuk sujud, maka dia mengambil posisi duduk dan meletakkan tangannya di lantai dengan menundukkan kepalanya dan mendekatkan ke tempat sujud semampunya. Apabila tidak mampu meletakkan tangannya di atas lantai maka boleh meletakkan di atas lutut. Karena dalam sujud wajib bagi seseorang untuk meletakkan 7 anggota sujudnya di lantai, apabila tidak bisa meletakkan semuanya maka letakkan apa yang mampu diletakkan, sebagaimana dalam hadits Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ – وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ – وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ
“Aku diperintahkan bersujud dengan tujuh bagian anggota badan: (1) Dahi (termasuk juga hidung, beliau mengisyaratkan dengan tangannya), (2,3) telapak tangan kanan dan kiri, (4,5) lutut kanan dan kiri, dan (6,7) ujung kaki kanan dan kiri.” (HR. Bukhari No. 812)
([29]) HR. Nasa’I No. 1661, dan dishahihkan oleh Al-Albani.
Dan posisi duduk ini sebagai pengganti dari posisi berdiri dan ruku’nya. Maka dia shalat dengan posisi duduk dan tangan bersedekap di atas dada sebagai pengganti dari posisi berdirinya, adapun ketika ruku’ maka dia meletakkan kedua tangannya di atas lututnya dengan sedikit menundukkan kepalanya, adapun ketika sujud maka hendaknya meletakkan semua anggota sujudnya di atas lantai sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma tentang sujud di atas anggota badan tujuh.
Akan tetapi ketika dia tidak mampu meletakkan keningnya di atas lantai, maka hendaknya meletakkan kedua tangannya di atas lantai dan menundukkan kepalanya untuk sujud, dan apabila dia tidak bisa juga meletakkan tangannya di atas lantai, maka meletakkan tangannya di atas lutut dan menundukkan kepalanya untuk sujud dan mejadikan sujudnya lebih rendah dari ruku’nya. (Lihat:shalatul maridh fii dhouil kitab was sunnah hal: 26)
([30]) Fatawa Arkanul Islam Hal 378
([32]) HR. Al Baihaqi dalam Al Kubra no. 3718. Namun hadits ini diperselisihkan oleh para ulama, sebagian ulama condong kepada lemahnya hadits ini, diantaranya Az-Zailaí (lihat Nashbur Rooyah 2/175) dan al-Haitsami (lihat Majma’ az-Zawaaid 2/148).
Dan sebagian ulama memandang kuatnya hadits ini, diantaranya adalah Ibnu Hajar (lihat Ad-Dirooyah fi Takhriij Ahaadiits al-Hidaayah 1/209 dan Bulughul Maram no 329)
([33]) Dalilnya adalah firman Allah Ta’ala dalam surat Al-Muddatstsir:
كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (39) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (40) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43)
“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan, berada di dalam surga, mereka tanya menanya, tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, “Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?” Mereka menjawab: “Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat”.
Firman Allah ‘Azza wa Jalla:
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (59) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
“Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh.” (QS. Maryam: 59-60)
Rasulullah pernah ditanya tentang apa itu “ghoyyun” dan “aatsaamun”, beliau menjawab:
بِئْرَانِ في أسْفَلِ جَهَنَّمَ يَسِيلُ فِيهِما صَدِيدُ أهْلِ النَّارِ
“dua sumur yang terletak di bawah Jahannam yang mengalir di keduanya nanah penduduk neraka.” HR. Ath-Thobroni no. 7731, Al-Baihaqi no 474 dengan lafaz “Nahroon”.
Abdullah bin Amr berkata bahwa ghoyyun ada lembah di Jahannam. (Lihat Jami’ul bayan fii takwiilil qur-an 18/218)
Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ
“Sesungguhnya (batas) antara seseorang dengan syirik dan kekafiran adalah meninggalkan shalat”. (HR. Muslim no. 82)
Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلاَمُ وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ
“Pokok urusan (agama) itu adalah Islam, tiangnya shalat, dan puncak ketinggiannya adalah jihad.” (HR. Tirmidzi no. 2616)
Dalam hadits ini kita ketahui bahwa shalat adalah tiang bagi agama Islam, suatu bangunan ketika tidak ada tiangnya maka dipastikan akan roboh, begitu pula agama Islam ketika tiangnya tidak ditegakkan maka sudah dipastikan tidak akan tegak agama seseorang. Walaupun demikian, orang yang sakit mendapatkan keringanan-keringanan dalam shalatnya.
([35]) HR. Al-Baihaqy No. 1818
Dan dalam Ad-Daruquthni menyebutkan dalam sunannya bahwa Ibnu Umar pingsan lebih dari 2 hari dan ia tidak mengqodonya. (Lihat: sunan ad-daruquthni No. 1862). ia juga menyebutkan bahwa Ibnu Umar pingsan tiga hari tiga malam. (No. 1863).
Khilaf Dalam Pingsan :
Pendapat pertama, Hanafiyah menyatakan, jika pingsannya melebihi shalat lima waktu, tidak wajib qadha. Sebaliknya, jika pingsannya hanya meninggalkan shalat lima waktu atau kurang darinya maka wajib qadha. Berkata Al-Jasshosh membawa perkataan Abu Ja’far:
قال أبو جعفر: ومن أغمي عليه خمس صلوات أو أقل منها، ثم أفاق: قضاها، ومن أغمي عليه أكثر من ذلك، ثم أفاق: لم يقض.
“Berkata Abu Ja’far: dan siapa yang pingsan (dan tertinggal) shalat lima waktu atau kurang darinya kemudian tersadar, maka ia harus mengqodho, dan siapa yang pingsan lebih dari shalat lima waktu maka ia tidak mengqodho.” (Syarh mukhtashor At-thohawi 1/544)
Berkata Ibnu Hazm:
قَالَ عَلِيٌّ: أَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فَفِي غَايَةِ الْفَسَادِ؛ لِأَنَّهُ لَا نَصَّ أَتَى بِمَا قَالَ، وَلَا قِيَاسَ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ عَنْ الْمُغْمَى عَلَيْهِ سِتَّ صَلَوَاتٍ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءَ شَيْءٍ مِنْهُنَّ
“Berkata Ali (Ibnu Hazm): adapun perkataan Abu Hanifah maka sangat salah: karena tidak ada nash dan qiyas yang datang sesuai dengan perkataannya, karena ia menggugurkan dari orang yang pingsan enam shalat dan tidak berpendapat ada qodho sama sekali. (Al-Muhalla bil atsar 2/8-9)
Pendapat kedua: orang yang pingsan sama sekali tidak wajib mengqadha shalatnya, berapapun jeda waktunya. Kecuali ia siuman di waktu shalat tersebut, maka ia wajib menunaikan shalat tersebut. Hal ini dikarenakan orang yang pingsan disamakan dengan orang yang hilang akal. Sementara orang yang hilang akal, tidak terkena kewajiban syariat. Dan ini adalah pendapat madzhab Malikiyah, Syafi’iyyah, dan salah satu pendapat madzhab Hanabilah.
Ibnu Abdil Bar berkata:
ولا يقضي المغمى شيئا من الصلوات لأنه ذاهب العقل ومن ذهب عقله عليه في وقت صلاة يدرك منها ركعة لزمه فليس بمخاطب فإن افاق المغمى عليه في وقت صلاة يدرك منها ركعه لزمه قضاءها
“Orang yang pingsan, tidak wajib mengqadha shalatnya. karena dia hilang akal. Dan orang yang hilang akalnya di waktu shalat yang ia bisa mendapatkan satu raka’at yang wajib ia kerjakan maka dia tidak terkena kewajiban shalat tersebut. Jika orang yang pingsan sadar di waktu shalat yang ia dapati darinya hanya sebatas satu raka’at maka ia wajib menunaikannya.”(Al-Kafi fi Fiqh Ahli al-Madinah, 1/237).
Berkata Al-Mawardi:
وَأَمَّا الْإِغْمَاءُ فَيُسْقِطُ فَرْضَ الصَّلَاةِ إِذَا اسْتَدَامَ جَمِيعَ وَقْتِهَا وَإِنْ كَانَتْ صَلَاةً وَاحِدَةً
“Adapun orang yang pingsan maka gugur kewajiban shalatnya jika menghabiskan seluruh waktu shalat tersebut, walaupun hanya satu shalat.” (Al-Hawi Al-Kabir 2/38)
Dari penjelasan beliau dapat dipahami jika ia pingsan dalam waktu yang masih tersisa untuk melaksanakan shalat maka kewajibannya tidak gugur. Karena gugurnya shalat tersebut jika pingsannya menghabiskan waktu shalat tersebut.
Dan ini juga salah satu pendapat dalam madzhab hanabilah sebagaimana yang disampaikan oleh al-Mardawi:
وَقِيلَ: لَا تَجِبُ عَلَيْهِ كَالْمَجْنُونِ، وَاخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ
“Dan dikatakan: tidak wajib baginya untuk mengqodho seperti orang gila, dan beliau memilihnya dalam kitab “al-faiq”.” (Al-inshaf 1/390)
Yang menjadi dalil mereka adalah, hadits ‘Aisyah ketika bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam tentang lelaki yang pingsan hingga luput darinya shalat, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam menjawab:
«لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَضَاءٌ إِلَّا أَنْ يُغْمَى عَلَيْهِ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَيَفِيقُ وَهُوَ فِي وَقْتِهَا فَيُصَلِّيهَا»
“tidak ada qodho sedikitpun kecuali ia pingsan di waktu shalat kemudian siuman dan dia masih mendapati waktu shalat tersebut maka hendaknya ia melaksanakan shalat tersebut.” (HR. Ad-Daruquthni no. 1860 dan Al-Baihaqy no 1820)
Namun dijelaskan oleh Ibnu Qudamah bahwa dalam hadits tersebut batil, karena terdapat di dalamnya perowi bernama Al-Hakim bin Sa’ad, dan imam Ahmad telah melarang dari mengambil hadits darinya, dan juga Ibnul Mubarok melemahkannya, berkata Imam Bukhori: ditinggalkan. Dan juga di dalamnya terdapat perowi bernama Khorijah bin Mush’ab. (Lihat: al-Mughni 1/290)
Dan juga yang menjadi dalil mereka adalah berdasarkan perbuatan Ibnu ‘Umar sebagaimana yang diriwayatkan oleh Malik dari Nafi’:
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَلَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ ” قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ ذَهَبَ وَأَمَّا مَنْ أَفَاقَ وَهُوَ فِي وَقْتٍ فَإِنَّهُ يُصَلِّي هَكَذَا فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ عَنْ نَافِعٍ وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَفِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
“Sesungguhnya Abdullah bin Umar pingsan dan hilang kesadarannya, lalu ia tidak mengqodho shalatnya, dan berkata Malik: dan hal tersebut karena waktu telah berlalu, dan adapun orang yang tersadar dan dia masih menjumpai waktu shalat tersebut, maka ia harus melaksanakan shalat tersebut. Begitu juga dalam riwayat dari jama’ah dari Nafi’ dan dalam riwayat Ubaidillah bin Umar dari Nafi’: satu hari satu malam, dan dalam riwayat Ayyub dari Nafi’: tiga hari.” (HR. Al-Baihaqy no 1818)
Dan dalam Ad-Daruquthni menyebutkan dalam sunannya bahwa Ibnu Umar pingsan lebih dari 2 hari dan ia tidak mengqodonya. (Lihat: sunan ad-daruquthni no 1862, dan ia juga menyebutkan bahwa Ibnu Umar pingsan tiga hari tiga malam. No 1863)
Pendapat ketiga: orang yang pingsan wajib qadha, seberapapun lama pingsannya. Dan ini adalah pendapat yang kuat dalam madzhab hambali.
Abu Dawud As-Sijistani menceritakan kisahnya ketika bertanya kepada Imam Ahmad:
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِي؟ قَالَ: نَعَمْ، يَقْضِي مَا فَاتَهُ جَمِيعًا، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَمَّارٍ
“Aku bertanya kepada Imam Ahmad: apakah orang yang pingsan mengqodho (shalatnya)? Ia menjawab: iya, ia mengqodho semua yang luput darinya.” Lalu beliau berdalil dengan hadits Ammar. (Rosail al-imam ahmad riwayatu abi dawud as-sijistany 1/73)
Dan juga dijelaskan alasannya bahwa yang pingsan sama seperti orang yang tertidur
الْمغمى عَلَيْهِ ان يُعِيد كل مَا فَاتَهُ فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَام عَن صَلَاة فانتبه وَقد طلعت عَلَيْهِ الشَّمْس فَأَعَادَ وَأعَاد الْقَوْم مَعَه الْفجْر وَقد كَانَ الْقَلَم مَرْفُوعا عَنْهُم لَان النَّائِم الْقَلَم عَنهُ مَرْفُوع فَأَعَادُوا الصَّلَاة
“Orang yang pingsan hendaklah mengulang semua (shalat) yang telah luput darinya, karena Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tertidur dari shalat kemudian ia terbangun dan matahari telah terbit, maka beliau mengqodho shalat subuh dan para sahabat ikut mengqodho bersama beliau. Dan sungguh pena telah terangkat dari mereka, karena orang yang tertidur pena telah terangkat darinya, namun mereka tetap mengqodho shalat.” (Masail al-imam ahmad riwayatu ibnihi ‘Abdillah 1/56-57)
Dan berkata Ibnu Qudamah:
وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ حُكْمُهُ حُكْمُ النَّائِمِ، لَا يَسْقُطُ عَنْهُ قَضَاءُ شَيْءٍ مِنْ الْوَاجِبَاتِ الَّتِي يَجِبُ قَضَاؤُهَا عَلَى النَّائِمِ
“dan kesimpulan hal tersebut bahwa orang yang pingsan hukumnya hukum orang yang tidur, tidak gugur darinya qodho satupun dari kewajiban-kewajiban yang wajib untuk diqodho bagi orang yang tertidur.” (Al-Mughni 1/290)
Berkata al-Mardawi:
وأما المغمى عليه فالصحيح من المذهب: وجوبها عليه مطلقا نص عليه في رواية صالح وابن منصور وأبي طالب وبكر بن محمد كالنائم وعليه جماهير الأصحاب
“Orang yang pingsan, pendapat yang shohih dalam madzhab hambali, wajib (mengqadhanya) secara mutlak. Ditegaskan Imam Ahmad menurut riwayat Sholeh, Ibnu Manshur, Abu Thalib, dan Bakr bin Muhammad, sebagaimana orang tidur. Ini merupakan pendapat mayoritas madzhab hambali.” (Al-inshaf 1/390)
Yang menjadi dalil mereka adalah:
- Perbuatan sahabat Ammar bin Yasir
أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَأَفَاقَ نِصْفَ اللَّيْلِ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
“sesungguhnya Ammar bin Yasir pingsan di waktu zhuhur, ashar, maghrib, dan isya. Kemudian ia ter tersadar di pertengahan malam, maka ia melakukan shalat waktu zhuhur, ashar, maghrib, dan isya.” (HR. Al-Baihaqy No. 1822)
- Mengqiyaskan orang yang pingsan dengan orang yang tertidur, ketika orang yang tertidur terluput darinya beberapa shalat maka ia tetap wajib untuk mengqodho shalatnya, begitu juga orang yang pingsan.
Dari pemaparan pendapat-pendapat para ulama, terdapat dua pendapat yang kuat, yaitu pendapat kedua dan ketiga, dan dari kedua pendapat tersebut penulis lebih condong kepada pendapat kedua, hal ini berdasarkan penjelasan bagus yang dijelaskan oleh syaikh Utsaimin saat menjawab dalil pendapat ketiga, yaitu tidak bisa mengqiyaskan orang yang pingsan dengan orang yang tertidur, beliau berkata:
إذا أغمي على المريض وفقد الوعي فإنه لا صلاة عليه سواء توفى أو عافاه الله، فلو قدر أن المريض أغمي عليه لمدة يوم أو يومين أو شهر أو شهرين ثم أفاق فإنه لا قضاء عليه، ولا يمكن أن يقاس الإغماء على النوم؛ لأن النائم يمكن أن يستيقظ إذا أوقظ، والمغمى عليه لا يمكن، فهو في حال بين الجنون وبين النوم، والأصل براءة الذمة، وعلى هذا فيكون من أغمي عليه لمرض أو حادث فإنه لا يقضي الصلوات قلت أو كثرت، أما إذا أغمي عليه للبنج الذي استعمله باختياره ولكنه لم يصح بعد البنج إلا بعد يومين أو ثلاثة فعليه أن يعيد الصلاة؛ لأن هذا حصل باختياره.
“jika orang yang sakit pingsan dan hilang kesadarannya maka tidak ada shalat baginya, sama saja apakah ia wafat atau Allah sembuhkan, dan jikalau ditaqdirkan orang yang sakit pingsan selama satu atau dua hari, atau satu bulan atau dua bulan kemudian ia tersadar maka tidak ada qodho baginya, dan tidak mungkin untuk diqiyaskan pingsan dengan tidur, karena orang yang tertidur mungkin untuk bangun jika dibangunkan, adapun orang yang pingsan maka tidak mungkin (untuk dibangunkan), maka dia dalam keadaan antara gila dan tertidur, dan asalnya adalah berlepas diri (dari taklif), maka dengan ini orang yang pingsan karena sakit atau kecelakaan maka ia tidak mengqodho shalat-shalat tersebut sedikit ataupun banyak, adapun jika ia pingsan disebabkan karena obat bius yang ia gunakan atas keinginannya dan ia tidak sadara setelan menggunakannya kecuali setelah dua atau tiga hari maka baginya untuk mengulang (mengqodho) shalat tersebut, karena ini terjadi atas kemauannya.” (Al-liqo asy-syahri 48/17)
Dan beliau juga menjawab tentang dalil mereka dengan perbuatan Ammar bin Yasir:
أما المسألة التي أشار إليها السائل وهي قضاء عمار صلاته التي فاتته بالإغماء فهي أيضاً مبنية على الخلاف في حجية فعل الصحابي، ثم إن فعل عمار لا يدل على الوجوب؛ لأن الفعل المجرد من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حجة لا يدل على الوجوب، فكيف بفعل غيره؟ فهو رضي الله عنه لما أغمي عليه استحسن أن يقضي ما فاته.
“adapun permasalahan yang diisyaratkan oleh penanya yaitu qodho Ammar shalatnya yang telah luput darinya disebabkan pingsan maka permasalahan ini juga dibangun di atas perbedaan dalam hujjah perbuatan sahabat, kemudian jika Ammar melakukan hal tersebut maka ini tidak menunjukkan wajib, karena sekedar perbuatan dari Rasulullah yang bisa menjadi hujjah saja tidak menunjukkan kewajiban, lantas bagaimana dengan perbuatan selainnya? Dan dia radhiyallahu ‘anhu ketika pingsan, beristihsan untuk mengqodho apa yang telah luput.” (Liqo al-baab al-maftuuh 60/28)
Adaun Syaikh Ibnu Baz, beliau lebih memilih kehati-hatian dalam masalah ini, jika pingsan hanya 3 hari atau kurang maka untuk kehati-hatian hendaknya orang yang pingsan mengqodho shalatnya, adapun jika lebih dari tiga hari maka tidak perlu mengqodho. (Lihat: majmu’ fatawa Bin Baz 15/210)