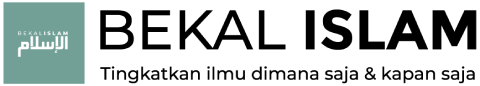Rukun-rukun Iktikaf
Iktikaf adalah sebuah ibadah, maka dari itu terdapat aturan-aturan agar seseorang dapat dikatakan beriktikaf. Adapun rukun-rukun iktikaf antara lain:
- Lokasi yang digunakan untuk iktikaf
Secara umum, jumhur ulama berpendapat bahwa iktikaf harus di masjid. ([1]) Sebagian kecil dari mereka juga berpendapat bahwa iktikaf boleh dilaksanakan di selain masjid seperti di musala rumah yang memang ruangan tersebut dikhususkan untuk tempat shalat. ([2]) Namun, yang lebih benar adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa iktikaf harus di masjid. Hal tersebut sebagaimana firman Allah ﷻ,
﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾
“(tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beriktikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 187)
Dari sini dipahami oleh para ulama bahwasanya masjid merupakan syarat untuk iktikaf, karena dari ayat ini seakan-akan menunjukkan bahwa iktikaf di masjid adalah perkara yang makruf (dikenal). Masjid yang dimaksud di sini adalah masjid mana pun yang terbuka untuk umum, dikumandangkan azan dan iqamah untuk melaksanakan shalat lima waktu di dalamnya, meskipun tidak dilaksanakan shalat Jumat di dalamnya, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat, wallahu a’lam.([3])
Bagian mana dari masjid yang bisa digunakan untuk beriktikaf?
Seluruh bagian yang lokasinya memang dibangun untuk tempat shalat, ulama bersepakat atas bolehnya beriktikaf di situ. Namun terdapat ikhtilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama tentang bagian dari masjid yang area tersebut tidak digunakan untuk shalat, seperti perpustakaan masjid atau kantor masjid. Pendapat yang dipilih oleh Lajnah Daimah dan juga dikuatkan oleh syekh ‘Utsaiminrahimahullah adalah semua area tersebut, selama masih berada dalam bangunan masjid maka boleh digunakan untuk iktikaf. ([4])
Bagaimana dengan musala?
Selama musala itu dibuka untuk umum, dikumandangkan di dalamnya azan dan iqamah untuk melaksanakan shalat lima waktu, maka boleh digunakan untuk iktikaf. Selama itu bangunan tersendiri dan dibuka untuk umum maka hukumnya mengikuti hukum masjid. Berbeda halnya dengan musala kantor yang tidak terbuka untuk umum maka tidak boleh dijadikan tempat beriktikaf.
- Niat
Seseorang yang ingin beriktikaf maka ia harus berniat.([5]) Niat ini cukup dalam hati dan tidak perlu diucapkan. Niat adalah syarat untuk iktikaf, sehingga jika seseorang tidak berniat untuk beriktikaf maka iktikafnya tidak dianggap meskipun seseorang telah lama berdiam di masjid. Nabi Muhammad ﷺ bersabda,
إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ
“Amalan-amalan itu tergantung niat.”([6])
Maka, jika seseorang telah lama berdiam di masjid, banyak shalat dan baca Al-Qur’an, maka yang ia dapatkan hanyalah pahala shalat dan baca Al-Qur’an saja, ia tidak mendapatkan pahala iktikaf karena tidak meniatkannya.
- Muslim mumayiz
Seorang yang beriktikaf haruslah muslim yang mumayiz, ([7]) karena Allah ﷻ hanya menerima amalan dari seorang muslim. Bukan hanya untuk lelaki, bahkan perempuan pun boleh melaksanakan iktikaf. Hal ini sebagaimana yang dilakukan istri-istri Nabi Muhammad ﷺ, di mana mereka beriktikaf bersama Nabi Muhammad ﷺ. Juga, sebagaimana yang dipahami oleh para ulama dari iktikafnya Maryam di Masjidilaqsa sebagai syariat terdahulu. Hanya saja, wanita yang beriktikaf harus atas izin suaminya, ([8]) karena ketaatan kepada suami hukumnya wajib, sedangkan iktikaf hukumnya sunah.
Apakah wanita yang haid atau nifas boleh Iktikaf?
Mayoritas ulama empat mazhab berpendapat bahwa wanita yang haid tidak boleh berdiam diri di masjid. Dari pendapat ini, bagaimana dengan wanita yang beriktikaf lalu di tengah-tengah iktikafnya ia haid, apakah iktikafnya batal? Sebagian mengatakan tidak, karena wanita haid tersebut hanya uzur untuk meninggalkan masjid, sehingga jika sudah bersih maka ia kembali beriktikaf. ([9]) Sebagian lain berpendapat iktikafnya batal, dan jika ia sudah suci maka ia wajib memperbarui niatnya untuk beriktikaf([10]).
Sedangkan ulama zahiriah seperti Ibnu Hazm dan yang lainnya berpendapat bahwa wanita haid tidak dilarang berdiam diri di masjid selama ia tidak mengotori area masjid. ([11]) Hal ini dikarenakan tidak ada dalil yang secara tegas melarang wanita haid untuk berdiam diri di masjid. Sedangkan jika diperhatikan, ada banyak wanita yang beriktikaf di zaman Nabi Muhammad ﷺ, akan tetapi tidak pernah disebutkan bahwa ada seorang wanita yang kembali ke rumahnya dikarenakan haid. Seandainya haid menghalangi seorang wanita untuk beriktikaf maka tentu akan ada dalil yang tegas tentang hal ini. Demikianlah ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama, namun penulis lebih condong kepada pendapat zahiriah ini, bahwasanya wanita yang haid masih boleh beriktikaf di masjid meskipun sedang haid, selama mereka tidak mengotori masjid. Adapun wanita yang istihadah maka tidak mengapa untuk beriktikaf karena ini adalah uzur syar’i.
- Menetap di masjid
Para ulama ikhtilaf tentang ukuran berapa lama seseorang telah dikatakan beriktikaf. Ada yang mengatakan harus sepuluh hari atau sembilan hari dan tidak boleh kurang dari itu([12]), karena yang demikianlah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad ﷺ. Bahkan, pendapat ini mengatakan bahwa iktikaf tersebut harus disertai dengan puasa di siang harinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ﷺ.
Pendapat yang lain mengatakan iktikaf boleh dilaksanakan walaupun sebentar saja, meskipun hanya lima atau sepuluh menit. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya at-Tibyan([13]). Oleh karenanya, hendaknya setiap orang yang hendak ke masjid untuk selalu berniat untuk iktikaf, agar ia bisa terus mendapatkan pahala iktikaf meskipun hanya sebentar saja. Perlu diketahui bahwasanya iktikaf bisa dilakukan di selain bulan Ramadan.
Ada juga ulama yang mengatakan bahwa iktikaf harus dilakukan minimal sehari semalam([14]). Ada pula yang mengatakan bahwa bisa lebih ringan daripada itu, yaitu boleh satu siang atau satu malam saja. ([15]) Mereka berdalil dengan hadits ‘Umar radhiallahu ‘anhu,
كنتُ نَذَرْتُ في الجاهليَّةِ أن أعتكِفَ ليلةً في المسجِدِ الحَرامِ
“Aku pernah bernazar pada zaman jahiliah untuk beriktikaf selama semalam di Masjidilharam.”([16])
Sebagian ulama juga berpendapat tidak harus semalam akan tetapi yang terpenting adalah berdiam diri dalam waktu yang panjang yang ukurannya kembali kepada tradisi atau bahasa daerah tempat tinggal. Sebab jika syariat tidak memberi batasan tertentu maka hukumnya dikembalikan kepada tradisi atau bahasa.
Dari sini kita ketahui bahwa iktikaf tidak harus dilaksanakan sepuluh hari, karena dalam permasalahan ini Nabi Muhammad ﷺ tidak pernah memberi batasan waktu tertentu untuk iktikaf. Maka seseorang telah dikatakan beriktikaf jika telah berdiam diri di masjid dalam waktu yang lama atau waktu yang dianggap sebagai tindakan mendiami suatu tempat.
Tentunya, hal ini menjadi solusi yang membahagiakan bagi saudara-saudara kita yang di siang hari bulan Ramadan masih sibuk dengan bekerja, maka malamnya masih bisa digunakan untuk beriktikaf, meskipun hanya dua atau tiga jam. Karena, selama niat iktikaf itu dipasang, maka pahala tetap akan terhitung di sisi Allah ﷻ.

Karya : Ustadz DR. Firanda Andirja, MA
Tema : Bekal Puasa
___________
Footnote:
([1]) Ibnu Abdul Barr mengayakan bahwa ini adalah ijmak. [Lihat: Al-Istidzkar (3/385)
([2]) Ini adalah pendapat al-Qadim dari Imam Syafi’i. [Lihat: Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab (6/480)].
([3]) Sebagian ulama memang berpendapat bahwa yang disebut dengan masjid adalah tempat yang dilaksanakan shalat lima waktu, termasuk shalat Jumat. [Lihat: Al-Mughni (3/190)].
Hal ini dikarenakan agar orang yang beriktikaf tidak perlu lagi keluar dari masjid tersebut untuk shalat Jumat. Namun yang benar, masjid yang ditegakkan shalat lima waktu di dalamnya boleh dipakai untuk beriktikaf, meskipun tidak dilaksanakan shalat Jumat di dalamnya. Adapun keluar untuk shalat Jumat di masjid jami’ misalnya, maka hal tersebut adalah keluar yang diberi uzur (dibolehkan) dan tidak membatalkan iktikaf seseorang.
([4]) Lihat: Liqa’ al-Bab al-Maftuh (18/114).
([5]) Lihat: Bidayah al-Mujtahid (1/315)..
([6]) HR. Bukhari No. 6689 dan HR. Muslim No. 1907.
([7]) Lihat: Al-Bahr ar-Raiq (2/322), Mawahib al-Jalil (3/395), al-Majmu’ (6/476), dan al-Inshaf (3/358).
([8]) Lihat: Syarh an-Nawawi ‘Ala Muslim (8/70).
([9]) Ini adalah pendapat mayoritas ulama, mazhab Malikiyah [Lihat: Asy-Syarh al-Kabir (1/552)], Syafi’iyah [Lihat: Al-Majmu’ (6/519)], dan Hanabilah [Lihat: Kasysyaf al-Qina’ (2/537)].
([10]) Lihat: Mughni al-Muhtaj (1/201).
([11]) Lihat: Al-Muhalla (1/401-402).
([12]) Ini adalah pendapat sebagian dari mazhab Malikiyah [Lihat: Hasyiyah al-Adawi (1/466).
([13]) Lihat: At-Tibyan (1/77-78).
([14]) Ini adalah pendapat imam Malik [Lihat: Al-Mudawwanah (1/297).
([15]) Lihat: Hasyiyah ad-Dusuqi (2/541).
([16]) HR. Bukhari No. 2032.