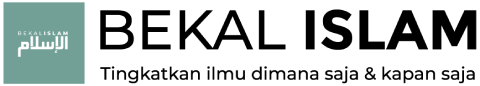Qadha Puasa
Ada beberapa aturan atau fikih terkait qadha, di antaranya:
- Tidak harus berurutan dan boleh terpisah-pisah.
- Batas akhir membayar qadha hingga sebelum Ramadan berikutnya. Hal ini sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiallahu ‘anha,
كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ
“Aku berhutang puasa Ramadan dan aku tidak bisa mengqadhanya kecuali pada bulan Sya’ban.”([1])
Bagaimana jika seseorang ternyata telat mengqadha puasanya hingga tiba Ramadan berikutnya? Maka dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan para ulama:
Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini:
Pertama: Dia harus membayar qadha dengan fidyah. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama([2]). Mereka berdalil dengan sebuah riwayat dari Abu Hurairah h tentang seorang lelaki yang memiliki utang puasa, namun ia mengakhirkannya hingga tiba Ramadan berikutnya. Abu Hurairah berkata terkait orang ini,
يَصُومُ الَّذِي أَدْرَكَهُ وَيُطْعِمُ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مَدًّا مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ , فَإِذَا فَرَغَ فِي هَذَا صَامَ الَّذِي فَرَّطَ فِيهِ
“Ia tetap berpuasa Ramadan, lalu mengqadha puasa Ramadan yang lalu yang ia dulu berbuka, ditambah memberi makan tiap hari (dari puasa qadhanya) seorang miskin satu mud gandum.” ([3])
Ibnu Qudamah berkata,
وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُمْ قَالُوا: أَطْعِمْ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. وَلَمْ يُرْوَ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنْ الصَّحَابَةِ خِلَافُهُمْ
“Dalil kami (atas wajibnya fidyah) adalah riwayat Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah yang mewajibkan membayar fidyah untuk setiap harinya satu orang miskin. Tidak ada sahabat lain yang menyelisihi riwayat ini.” ([4])
Kedua: Cukup baginya qadha saja tanpa fidyah. Ini merupakan pendapat mazhab Hanafiyah,([5]) Ibnu Hazm,([6]) dan beberapa ulama lainnya.([7])
Di antara dalil atas pendapat ini adalah firman Allah ﷻ,
﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾
“Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” (QS. Al-Baqarah: 185)
Imam Bukhari dalam Shahihnya membawakan perkataan Ibrahim an-Nakha’i rahimahullah,
إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَابْنِ عَبَّاسٍ: ” أَنَّهُ يُطْعِمُ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الإِطْعَامَ، إِنَّمَا قَالَ: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}
“Jika seseorang melalaikan untuk mengqadha puasanya hingga datang Ramadan berikutnya maka dia harus mengqadha keduanya, dia tidak perlu membayar fidyah. Disebutkan dari Abu Hurairah secara mursal dan Ibnu Abbas pernyataan wajibnya membayar fidyah. Padahal, Allah ﷻ tidak menyebutkan fidyah, Allah ﷻ hanya menyebutkan, ‘maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain’.” ([8])
Keumuman firman Allah ﷻ ini mencakup qadha setelah Ramadan berikutnya, dan Allah ﷻ dalam ayat ini tidak menyebutkan fidyah. Oleh karenanya, yang wajib bagi orang tersebut hanyalah qadha.([9])
Pendapat yang lebih tepat dan juga pendapat yang penulis pilih adalah pendapat pertama, bahwasanya orang yang sampai Ramadan berikutnya belum mengqadha puasanya maka yang wajib baginya adalah tetap qadha di hari-hari yang lain. Namun ada dua kemungkinan yang perlu diperhatikan, yaitu apabila seseorang sampai terlambat mengqadha karena uzur syar’i maka sepakat tidak ada dosa baginya, adapun jika terlambat tanpa ada uzur maka ia berdoa dan ia harus beristigfar dan bertobat kepada Allah ﷻ.
- Bagi orang yang meninggal dan mempunyai utang puasa, maka ada dua kondisi:
Kondisi pertama: Jika masih berutang karena tidak memiliki kesempatan mengqadha maka secara syariat ia tidak memiliki hutang puasa. Contoh dalam hal ini adalah orang sakit dan tidak mendapati kesembuhan, dan kemudian meninggal dunia. Contoh lain seperti musafir yang ketika hendak kembali ke kampung halamannya, ia kecelakaan dan meninggal dunia. Orang-orang yang seperti ini yang tidak memiliki kesempatan untuk mengqadha puasanya, maka tidak dianggap mereka memiliki utang puasa. Imam Nawawi berkata,
فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ فَاتَهُ بِمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ الْأَعْذَارِ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ قَضَائِهِ حَتَّى مَاتَ. ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ لا شئ عَلَيْهِ وَلَا يُصَامُ عَنْهُ وَلَا يُطْعَمُ عَنْهُ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالْجُمْهُورُ قَالَ الْعَبْدَرِيُّ وَهُوَ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إلَّا طَاوُسًا وَقَتَادَةَ فَقَالَا يَجِبُ أَنْ يُطْعَمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ فَأَشْبَهَ الشَّيْخَ الْهَرِمَ
“Mazhab para ulama tentang orang yang meninggal sedangkan dia memiliki utang puasa karena sakit, safar, atau karena uzur lainnya, dan tidak memungkinkan baginya untuk mengqadhanya hingga mati.
Kami sebutkan dalam mazhab kami (Syafi’iyah), bahwasanya tidak ada kewajiban apa pun atasnya, tidak perlu dipuasakan atasnya juga tidak perlu dibayarkan fidyah. Pendapat ini tidak ada perselisihannya dalam mazhab kami. Ini juga pendapat Abu Hanifah, Malik, dan mayoritas ulama. Al-Abdari berkata, ‘Ini merupakan pendapat seluruh ulama kecuali Thawus dan Qatadah yang mengatakan ‘Wajib membayarkan fidyah atasnya untuk setiap harinya kepada seorang miskin.’’ Hal ini dikarenakan dia tidak mampu mengqadhanya seperti orang tua renta.” ([10])
Kondisi kedua: Memiliki kesempatan untuk mengqadha namun tidak dikerjakan. Dalam hal ini para ulama ikhtilaf, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah:
Pertama: Hanya wajib fidyah. Ini adalah pendapat istri Rasulullah ﷺ, yaitu Aisyah radhiallahu ‘anha dan Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu. Ini juga pendapat mayoritas ulama, yaitu Malik, al-Awza’i, ats-Tsauri, Syafi’i, dan lainnya.
Kedua: Walinya (ahli warisnya) yang mengqadhakan (berpuasa untuknya) atau membayarkan fidyah([11]). Hal ini berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiallahu ‘anha, Nabi Muhammad ﷺ bersabda,
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
“Barang siapa yang meninggal dan memiliki utang puasa maka walinya berpuasa untuknya.”([12])
Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu Tsaur, Syafi’i([13]) dalam qaul qadim, dan dipilih oleh Nawawi([14]). Adapun ulama kontemporer yang memilih pendapat ini adalah Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Bin Baz.([15])
Pendapat yang kuat adalah bahwa orang tersebut masih memiliki utang puasa, sehingga walinya (ahli warisnya) yang mengqadhakan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad ﷺ,
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
“Barang siapa yang meninggal dan memiliki utang puasa maka walinya berpuasa untuknya.”([16])
Sebagian mengatakan bahwa hadits di atas khusus untuk puasa nazar. ([17]) Namun, yang benar adalah hadits ini bersifat umum. Hadits ini didukung oleh hadits lain, di mana ada seorang anak bertanya kepada Nabi Muhammad ﷺ tentang ibunya yang meninggal namun memiliki utang puasa, maka dia bertanya apakah ia membayarkan puasa ibunya tersebut? Maka Nabi Muhammad ﷺ bersabda,
لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟…فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى
“Bagaimana menurutmu jika ibumu memiliki hutang uang, apakah kamu akan melunasinya?…Utang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi.”([18])
Adapun jika orang lain (selain wali) ingin berpuasa untuknya, maka dibolehkan. Dikarenakan Rasulullah ﷺ mengiaskan hal ini dengan utang, dan utang seorang muslim bisa dibayarkan oleh siapa saja, tidak khusus kerabat. ([19])

Antara puasa sunnah dengan puasa qadha
Mayoritas ulama menjelaskan bahwasanya seseorang boleh untuk melakukan puasa sunnah meskipun dia belum mengqadha puasanya.([20]) Hal ini dikarenakan waktu qadha puasa Ramadan bersifat muwassa’ (luas) bukan mudhayyaq (sempit).([21])
Karya : Ustadz DR. Firanda Andirja, MA
Tema : Bekal Puasa
___________
Footnote:
([1]) HR. Bukhari No. 1950 dan HR. Muslim No. 1146.
([2]) Ini adalah pendapat mazhab Malikiyah [Lihat: At-Tamhid (7/162)], Syafi’iyah [Lihat: Al-Majmu’ (6/364)], dan Hanabilah [Lihat: Al-Inshaf (3/236)].
([3]) HR. Daruquthni dalam sunannya No. 2343. Beliau menyatakan sanadnya sahih mauquf. Juga dinyatakan sahih dan hasan oleh Ibnul Mulaqqin. [Lihat: Tuhfath al-Muhtaj (2/102)].
([4]) Al-Mughni (3/154).
([5]) Lihat: al-Bahr ar-Raiq (2/307).
([6]) Lihat: al-Muhalla (6/260).
([7]) Di antara ulama kontemporer yang mengambil pendapat ini adalah Syekh Utsaimin rahimahullah. [Lihat: Majmu’ Fatawa wa Rasail al-Utsaimin (19/385).
([8]) Shahih al-Bukhari (3/35).
([9]) Lihat: Fatawa Nur ‘Ala ad-Darb (25/212).
([10]) Al-Majmu’ (6/372).
([11]) Lihat: Al-Majmu’ (6/370).
([12]) HR. Bukhari No. 1952.
([13]) Lihat: Al-Mughni (3/152-153).
([14]) Lihat: Al-Majmu’ (6/370).
([15]) Lihat: Syarh al-Mumti’ (6/450) dan Majmu Fatawa Bin Baz (15/372).
([16]) HR. Bukhari No. 1952.
([17]) Lihat: Al-Mughni (3/152-153).
([18]) HR. Muslim No. 1148.
([19]) Ini adalah zahir dari pendapat Imam Bukhari dan Abu ath-Thayyib ath-Thabari. [Lihat: Fath al-Bari (4/194)].
([20]) Ini adalah pendapat mazhab Hanafiyah [Lihat: Hasyiyah Ibnu Abidin (2/423)], Malikiyyah (Hasyiyah ad-Dusuqi (1/518)], Syafi’iyah [Lihat: Mughni al-Muhtaj (1/445)], dan salah satu riwayat Imam Ahmad [Lihat: Al-Mughni (3/154-155)].
([21]) Lihat: Al-Mughni (3/154-155).