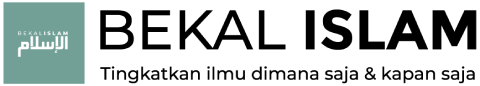Puasa Arafah
Yaitu puasa pada tanggal sembilan Zulhijah. Rasulullah ﷺ bersabda,
صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ
“Puasa Arafah, aku berharap kepada Allah ﷻ dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.” ([1])
Kapan Puasa Arafah?
Tidak diragukan lagi akan keutamaan puasa hari Arafah, Nabi ﷺ bersabda,
صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ
“Puasa hari Arafah aku berharap kepada Allah agar penebus (dosa) setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya”([2])
Tidak diragukan pula bahwa para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini menjadi dua pendapat:
Pertama: Waktu puasa Arafah disesuaikan dengan wukufnya para jemaah haji di padang Arafah. Ini adalah pendapat jumhur mayoritas ulama sekarang, seperti Syaikh Bin Baz rahimahullah dan Al-Lajnah Ad-Daimah([3]).
Kedua: Waktu puasa Arafah di sesuaikan dengan rukyat hilal bulan Dzulhijjah pada masing-masing wilayah. Dan inilah pendapat yang mashyur dari Syekh Muhammad bin Shaleh Al-‘Utsaimin rahimahullah,([4]) yang kemudian diikuti oleh murid-murid senior beliau seperti Syekh Khalid Al-Musyaiqih([5]). Demikian juga merupakan fatwa Syekh Abdullah bin Al-Jibrin rahimahullah.([6])
Karena ini adalah masalah khilafiyah, maka tentunya harus ada kelapangan dada untuk legowo dalam menghadapi permasalahan ini, tidak perlu ngotot apalagi menuduh orang yang berbeda pendapat dengan tuduhan yang tidak-tidak, seperti meniru pemikiran khawarij atau ahli bidah. Permasalahan ini sebagaimana permasalahan khilafiyah fiqhiyah yang lainnya yang hendaknya kita berlapang dada. Jika setiap permasalahan khilaf kita ngotot maka kita akan selalu ribut.
Di antara sebab bentuk kekakuan dan “sikap keras” dalam permasalahan ini adalah anggapan bahwa permasalahan ini telah ada nas (yaitu dalil yang tidak mengandung kecuali satu kemungkinan saja, dan tegas dalam penunjukannya). Sehingga barang siapa yang menyelisihi nas pantas untuk disalahkan.
Jika seandainya Nabi ﷺ bersabda ((Puasa hari Arafah adalah puasa di mana para jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah)), tentunya ini adalah nas dalam permasalahan ini, dan tentu para ulama tidak akan khilaf dalam memahami redaksi tersebut. Akan tetapi kenyataannya Nabi ﷺ bersabda صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ “Puasa hari Arafah…”. Di sinilah muncul perbedaan dalam memahami sabda Nabi tersebut, apakah maksudnya adalah “hari di mana para jamaah haji sedang wukuf di Arafah”? ataukah yang dimaksud adalah “hari tanggal 9 Dzulhijjah, yang dinamakan dengan hari Arafah?”
Ternyata khilaf ini sudah ada sejak zaman ulama terdahulu.
Ulama yang memilih pendapat pertama, di antaranya:
Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau berkata,
ويوم عرفة هو يوم العتق من النار فيعتق الله من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم من شهد الموسم منهم ومن لم يشهده لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة
Dan hari ‘Arafah adalah hari pembebasan dari neraka, maka Allah membebaskan dari neraka orang yang wukuf di Arafah dan juga orang yang tidak wukuf dari para penduduk kota-kota dari kaum muslimin. Karenanya jadilah hari setelah hari Arafah adalah hari raya bagi seluruh kaum muslimin di seluruh kota-kota mereka, baik yang menghadiri musim haji maupun yang tidak menghadiri, karena kesamaan mereka dalam pembebasan dari neraka dan ampunan Allah pada hari Arafah”([7])
Ulama yang memilih pendapat kedua, di antaranya adalah:
Ibnu Abidin rahimahullah, beliau berkata:
لأن اختلاف المطالع إنما لم يعتبر في الصوم لتعلقه بمطلق الرؤية. وهذا بخلاف الاضحية فالظاهر أنها كأوقات الصلوات يلزم كل قوم العمل بما عندهم، فتجزئ الاضحية في اليوم الثالث عشر وإن كان على رؤيا غيرهم هو الرابع عشر والله أعلم.
“Karena perbedaan matlak hanyalah tidak mu’tabar (tidak dianggap) pada permasalahan puasa karena puasa berkaitan dengan terlihatnya hilal secara mutlak. Hal ini berbeda dengan udhiyah (penyembelihan kurban), maka zahirnya ia seperti waktu-waktu shalat, maka wajib bagi setiap kaum beramal dengan apa yang ada pada mereka. Maka sah udhiyah pada hari ke 13 (Dzulhijjah) meskipun berdasarkan rukyat selain mereka adalah hari ke 14 Dzulhijjah, wallahu a’lam”.([8])
Ibnu Abidin justru memandang tidak ada perbedaan matlak dalam menentukan awal puasa Ramadan, akan tetapi untuk masalah penyembelihan kurban justru beliau memandang adanya perbedaan matlak, maka masing-masing beramal dengan rukyatnya masing-masing.
Demikianlah para ulama mutaqaddimin (terdahulu) telah berselisih akan hal ini. Akan tetapi, penulis lebih condong kepada pendapat kedua yang menyatakan bahwa penentuan hari Arafah dikembalikan kepada rukyat di negeri masing-masing.
Adapun dari sisi dalil adalah sebagai berikut:
Pertama: Rasulullah ﷺ telah menamakan puasa Arafah meskipun kaum muslimin belum melaksanakan haji, bahkan para sahabat telah mengenal puasa Arafah yang jatuh pada 9 Dzulhijjah meskipun kaum muslimin belum melaksanakan haji.
Dalam sunan Abu Dawud,
عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَصُومُ تِسْعَ ذِى الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ.
Dari Hunaidah bin Khalid dari istrinya dari sebagian istri Nabi ﷺ berkata, “Adalah Rasulullah ﷺ berpuasa pada 9 Dzulhijjah, hari ‘Asyura’ (10 Muharam) dan tiga hari setiap bulan”([9])
Ini menunjukkan bahwasanya Nabi ﷺ terbiasa puasa Arafah.
Tatkala mengomentari lafal hadits ((أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا فِي صَوْم النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) “Orang-orang (yaitu para sahabat) berselisih tentang puasa Nabi ﷺ (tatkala di padang Arafah)”, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata,
هَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ صَوْم يَوْمِ عَرَفَةَ كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَهُمْ مُعْتَادًا لَهُمْ فِي الْحَضَر ، وَكَأَنَّ مَنْ جَزَمَ بِأَنَّهُ صَائِم اِسْتَنَدَ إِلَى مَا أَلِفَهُ مِنْ الْعِبَادَةِ ، وَمَنْ جَزَمَ بِأَنَّهُ غَيْرُ صَائِمٍ قَامَتْ عِنْدَهُ قَرِينَةُ كَوْنِهِ مُسَافِرًا
“Ini mengisyaratkan bahwasanya puasa hari Arafah adalah perkara yang dikenal di sisi para sahabat, terbiasa mereka lakukan tatkala tidak bersafar. Seakan-akan sahabat yang memastikan bahwasanya Nabi berpuasa bersandar kepada kebiasaan Nabi yang suka beribadah. Dan sahabat yang memastikan bahwa Nabi tidak berpuasa berdalil adanya indikasi Nabi sedang safar”([10])
Padahal kita tahu bahwa Nabi ﷺ hanya berhaji sekali -yaitu haji wada’- dan ternyata Nabi dan para sahabat sudah terbiasa puasa di hari Arafah meskipun tidak ada muslim yang wukuf di padang Arafah.
Tentu sebelum Islam sudah ada orang-orang Arab yang wukuf di Arafah dari kalangan kaum musyrikin (kecuali kaum Quraisy yang wukufnya di Al-Muzdalifah). Akan tetapi, pembicaraan kita adalah tentang ikut serta meraih ampunan yang Allah berikan kepada kaum muslimin yang sedang wukuf di padang Arafah. Dan tatkala Nabi dan para sahabatnya terbiasa puasa hari Arafah ternyata tidak ada seorang muslim pun yang wukuf di Arafah. Ini menujukan bahwa konsentrasi penamaan puasa Arafah berkaitan dengan waktu 9 Dzulhijjah dan bukan pada tempat padang Arafah yang para jemaah haji sedang wukuf di situ.
Al-Khirasyi berkata,
(قَوْلُهُ: وَعَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ) هَذِهِ الْمَوَاسِمُ الْمُشَارُ بِقَوْلِهِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَوَاسِمِ ، وَعَاشُورَاءُ وَنِصْفُ شَعْبَانَ مَوْسِمٌ مِنْ حَيْثُ الصَّوْمُ وَغَيْرُهُ مِمَّا يُطْلَبُ فِيهِ، وَالْمَوَاسِمُ جَمْعُ مَوْسِمٍ الزَّمَنُ الْمُتَعَلِّقُ بِهِ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ وَلَمْ يُرِدْ بِعَرَفَةَ مَوْضِعَ الْوُقُوفِ بَلْ أَرَادَ بِهِ زَمَنَهُ وَهُوَ الْيَوْمُ التَّاسِعُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
“Hari Arafah dan Asyura -sebagaimana yang disebutkan- adalah salah satu dari musim-musim ibadah. Jika ditinjau dari sisi puasa maka Hari Asyura’, Nisfu Sya’ban, dan yang lainnya adalah musim ibadah yang dituntut untuk berpuasa pada musim tersebut. Musim adalah waktu yang terkait dengan suatu hukum syariat. Bukanlah yang dimaksud dengan lafal “Arafah” adalah tempat wukuf, akan tetapi yang dimaksud adalah waktunya, yaitu waktu wukufnya yaitu 9 Dzulhijjah”([11])
Kedua: Kita bayangkan bagaimana kondisi kaum muslimin -taruhlah- sekitar 200 tahun yang lalu, sebelum ditemukannya telegraph, apalagi telepon. Jika puasa Arafah penduduk suatu negeri kaum muslimin harus sesuai dengan wukufnya jamaah haji di padang Arafah, maka bagaimanakah puasa Arafahnya penduduk negeri-negeri yang jauh dari Makkah seperti Indonesia, India, Cina dll 200 tahun yang lalu? Apalagi 800 atau 1000 tahun yang lalu.
Demikian juga bagi yang hendak berkurban, maka sejak kapankah ia harus menahan untuk tidak memotong kuku dan mencukur rambut? Dan kapan ia boleh memotong kambing kurbannya? Apakah harus menunggu kabar dari Makkah, yang bisa jadi datang kabar tersebut berbulan-bulan kemudian?
Kalaupun akhirnya telah datang kabar setelah setengah bulan atau sebulan misalnya -padahal terjadi perbedaan antara rukyat mereka dengan Makkah-, maka sama sekali tidak dinukil mereka mengqada kesalahan mereka.
Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata,
أَنَّا نَعْلَمُ بِيَقِينٍ أَنَّهُ مَا زَالَ فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ يُرَى الْهِلَالُ فِي بَعْضِ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ بَعْضٍ فَإِنَّ هَذَا مِنْ الْأُمُورِ الْمُعْتَادَةِ الَّتِي لَا تَبْدِيلَ لَهَا وَلَا بُدَّ أَنْ يَبْلُغَهُمْ الْخَبَرُ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ فَلَوْ كَانُوا يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْقَضَاءُ لَكَانَتْ هِمَمُهُمْ تَتَوَفَّرُ عَلَى الْبَحْثِ عَنْ رُؤْيَتِهِ فِي سَائِرِ بُلْدَانِ الْإِسْلَامِ كَتَوَفُّرِهَا عَلَى الْبَحْثِ عَنْ رُؤْيَتِهِ فِي بَلَدِهِ وَلَكَانَ الْقَضَاءُ يَكْثُرُ فِي أَكْثَرِ الرمضانات وَمِثْلُ هَذَا لَوْ كَانَ لَنُقِلَ وَلَمَّا لَمْ يُنْقَلْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَدُلُّ عَلَى هَذَا
“Kita tahu dengan yakin bahwasanya semenjak zaman sahabat dan tabiin telah terlihat hilal di sebagian negeri kaum muslimin setelah terlihat di negeri yang lainnya (yaitu terjadi perbedaan hari dari terlihatnya hilal-pen). Karena ini merupakan perkara yang biasa yang tidak tergantikan. Dan pasti akan sampai kabar di tengah bulan (akan perbedaan hilal mereka dengan hilal yang terlihat di hijaz-pen). Kalau memang wajib bagi mereka untuk mengqada’ maka tentu semangat mereka untuk mencari tahu tentang terlihatnya hilal di seluruh negeri kaum muslimin sebagaimana semangat mereka untuk melihat hilal di negeri mereka. Dan tentu pula akan banyak terjadi qada di sebagian besar bulan Ramadan. Hal seperti ini, kalau seandainya terjadi maka tentu akan dinukilkan. Maka tatkala tidak dinukilkan (kalau mereka mengqada) maka ini menunjukkan perkara ini tidak ada asalnya. Dan hadits Ibnu Abbas menunjukkan akan hal ini.”([12])
Karenanya di zaman Ibnu Hajar terjadi perbedaan antara penduduk Makkah dan penduduk Mesir dalam menentukan hari Arafah dan hari raya Iduladha. Ibnu Hajar rahimahullah berkata,
وكانت الوقفة يوم الجمعة بعد تنازع بمكة مع أن العيد كان بالقاهرة يوم الجمعة
“Tatkala itu wuquf (padang Arafah) di Makkah hari Jumat -setelah terjadi perselisihan-, sementara hari raya Iduladha di Kairo (Mesir) adalah hari Jumat”([13])
Beliau juga berkata,
وفي الثالث والعشرين من ذي الحجة وصل بالمبشر من الحاج … وأخبر بأن الوقفة كانت يوم الاثنين وكانت بالقاهرة يوم الأحد ، فتغيظ السلطان ظنا منه أن ذلك من تقصير في ترائي الهلال ، فعرفه بعض الناس أن ذلك يقع كثيرا بسبب اختلاف المطالع ؛ وبلغني أن العيني شنع على القضاة بذلك السبب فلما اجتمعنا عرفت السلطان أن الذي وقع يقدح في عمل المكيين عند من لا يرى باختلاف المطالع ، حتى لو كان ذلك في رمضان للزم المكيين قضاء يوم
“Pada tanggal 23 Dzulhijjah sampailah pembawa kabar berita dari haji…., ia mengabarkan bahwa wukuf (di padang Arafah) pada hari senin, dan di Qohiroh (Mesir) jatuh pada hari Ahad. Maka Sultan (Mesir) pun marah karena menyangka bahwa perbedaan ini timbul karena kurang (serius) dalam melihat hilal. Maka ada sebagian orang yang menjelaskan kepada Sultan bahwasanya hal ini sering terjadi karena perbedaan matlak. Dan telah sampai kabar kepadaku bahwasanya Al-‘Aini mencela para Qadhi disebabkan hal ini. Maka tatkala kami bertemu, maka aku pun menjelaskan kepada Sultan bahwasanya apa yang terjadi hanyalah merusak amalan penduduk Makkah menurut yang berpendapat bahwasanya tidak ada perbedaan matlak, bahkan jika terjadi di bulan Ramadan maka wajib bagi penduduk Makkah untuk mengqada sehari”([14])
Kejadian di atas menunjukkan bahwa Mesir lebih dahulu melihat hilal daripada Makkah, sehingga Makkah 9 Zulhijahnya (wukufnya) jatuh pada hari Senin, sementara Mesir 9 Zulhijahnya jatuh pada hari ahad yaitu sehari sebelumnya. Jika para ulama memandang harus satu matlak maka seharusnya penduduk Makkah harus mengikuti penduduk Mesir, sehingga mereka telah salah dalam menentukan waktu wukuf di padang Arafah. Demikian juga jika hal ini terjadi di bulan Ramadan, tatkala Mesir lebih dahulu puasa maka penduduk Makkah baru berpuasa sehari setelahnya. Seharusnya, penduduk Makkah harus mengqada puasa sehari.
Akan tetapi Ibnu Hajar menjelaskan kepada Sultan bahwasanya hukum ini hanya berlaku bagi yang memandang tidak ada perbedaan matlak, dan tidak berlaku bagi yang memandang adanya perbedaan matlak. Zahir kisah ini menunjukkan Ibnu Hajar rahimahullah condong kepada pendapat perbedaan pelaksanaan puasa Arafah jika memang waktu melihat hilalnya berbeda.
Ketiga: Jika memang yang ditujukan adalah menyesuaikan dengan waktu wukufnya para jemaah haji di padang Arafah (dan bukan tanggal 9 Dzulhijjah berdasarkan masing-masing negeri), maka bagaimanakah cara berpuasanya orang-orang di Sorong Irian Jaya, yang perbedaan waktu antara Makkah dan Sorong adalah 6 jam?
Jika penduduk Sorong harus berpuasa pada hari yang sama -misalnya- maka jika ia berpuasa sejak pagi hari (misalnya jam 6 pagi WIT) maka di Makkah belum wukuf tatkala itu, bahkan masih jam 12 malam. Dan tatkala penduduk Makkah baru mulai wukuf -misalnya jam 12 siang waktu Makkah-, maka di Sorong sudah jam 6 magrib? Lantas bagaimana bisa ikut serta menyesuaikan puasanya dengan waktu wukuf?
Keempat: Jika seandainya terjadi malapetaka atau problem besar atau bencana atau peperangan, sehingga pada suatu tahun ternyata jemaah haji tidak bisa wukuf di padang Arafah, atau tidak bisa dilaksanakan ibadah haji pada tahun tersebut, maka apakah puasa Arafah juga tidak bisa dikerjakan karena tidak ada jemaah yang wukuf di padang Arafah?
Jawabannya tentu tetap boleh dilaksanakan puasa Arafah meskipun tidak ada yang wukuf di padang Arafah. Ini menunjukkan bahwa puasa Arafah yang dimaksudkan adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah.
Barang siapa yang satu matlak dengan Makkah dan tidak berhaji maka hendaknya ia berpuasa di hari para jemaah haji sedang wukuf di padang Arafah. Akan tetapi, jika ternyata matlaknya berbeda -seperti penduduk kota Sorong- maka ia menyesuaikan 9 Dzulhijjah dengan rukyat hilal setempat.
Intinya permasalahan ini adalah permasalahan khilafiyah. Meskipun penulis lebih condong kepada pendapat kedua -yaitu setiap negeri menyesuaikan 9 Dzulhijjah berdasarkan rukyat hilalnya-, akan tetapi sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya pendapat pertama pun sangat kuat dan dipilih oleh mayoritas ulama kontemporer.
Permasalahan seperti ini sangatlah tidak pantas untuk dijadikan ajang untuk saling memaksakan pendapat, apalagi menuding dengan tuduhan kesalahan manhaj atau kesalahan akidah dan sebagainya. Semoga Allah mempersatukan kita di atas ukhuwwah Islamiyah yang selalu berusaha untuk dikoyak oleh setan dan para pengikutnya. Hendaknya kita beradab dengan adab para ulama dalam permasalahan khilafiyah, dan hendaknya kita mengenal manhaj salaf dalam menyikapi permasalahan khilafiyah. Jangan sampai kita mengaku-ngaku bermanhaj ahlus sunnah tapi justru tidak tahu manhaj ahlus sunnah dalam permasalahan khilafiyah.
Karya : Ustadz DR. Firanda Andirja, MA
Tema : Bekal Puasa
_____________
Footnote:
([3]) Lihat: Fatwa Lajnah Daimah (10/393).
([4]) Lihat: Majmu Fatawa Ibnu Utsaimin (20/47).
([5]) Lihat: http://almoslim.net/55164
([6]) Lihat: http://ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-11952-.html
([7]) Lathoif al-Ma’aarif hlm. 276
([8]) Hasyiah Rodd Al-Muhtaar (2/432)
([9]) HR. Abu Dawud no. 2439 dan dinyatakan sahih oleh al-Albani, namun hadits ini diperselihkan akan kesahihannya
([11]) Syarh Mukhtashar Al-Khalil (2/234)
([12]) Majmuu’ al-Fatawa (1/12)
([13]) Inbaa’ Al-Ghomr bi Abnaa’ al-Umr fi At-Taariikh (2/425)
([14]) Inbaa’ Al-Ghomr bi Abnaa’ al-Umr fi At-Taariikh (8/78)