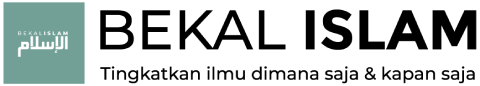Senang Berkorban dan Tidak Menyepelekan Hal Kecil
Safar merupakan penguak tabir hakikat yang sesungguhnya dari akhlak seseorang, karena safar penuh dengan kesulitan. Oleh karena itu, Nabi pernah bersabda: “Safar adalah sepotong adzab”. Artinya, bagaimanapun sarana dan prasarana yang terbaik dan tercanggih pun yang disiapkan untuk safar tetap saja orang yang bersafar akan mengalami kesulitan. Jadi, tidak heran jika orang yang bersafar akan menemukan kesulitan dan keletihan dan terkadang mara bahaya. Oleh karena itu, harus ada sikap saling bantu-membantu di antara para musafir. Jika seorang musafir memiliki akhlak yang mulia maka akan tampak kemuliaan akhlaknya saat ia dibutuhkan bantuan dan pengorbanannya. Sebaliknya, jika seseorang berakhlak buruk maka meskipun ia berusaha menyembunyikannya di hadapan orang lain dan berusaha bergaya seakan-akan ia berakhlak mulia, tetapi di saat safar akan terbongkar akhlak buruknya tersebut. Terlebih, jika safar menempuh jarak yang jauh dan waktu yang lama.
Pernah ada seseorang ingin memberikan persaksian di hadapan Umar bin Al-Khaththab, maka Umar pun berkata kepadanya, “Aku tidak mengenalmu, dan tidak memudaratkanmu meskipun aku tidak mengenalmu. Datangkanlah orang yang mengenalmu.” Maka ada seseorang -dari para hadirin- yang berkata, “Aku mengenalnya wahai amirul mukminin”. Umar berkata, “Dengan apa engkau mengenalnya?” Orang itu berkata, “Dengan keshalehan dan keutamaannya.” Umar berkata, “Apakah ia adalah tetangga dekatmu? yang engkau mengetahui kondisinya di malam hari dan di siang hari serta datang perginya?”, Orang itu berkata, “Tidak”. Umar kembali berkata, “Apakah ia pernah bermu’amalah denganmu berkaitan dengan dirham dan dinar, yang keduanya merupakan indikasi sikap wara’ seseorang?” Orang itu berkata, “Tidak”. Umar berkata lagi,
فَرَفِيْقُكَ فِي السَّفَرِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مَكَارِمِ الأَخْلاَقِ؟
Apakah ia pernah menemanimu dalam safar, yang safar merupakan indikasi mulianya akhlak seseorang?
Orang itu berkata, “Tidak.” Umar menimpali, “Jika demikian engkau tidak mengenalnya.” (Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Irwaa’ Al-Ghalil, 8/260 No. 2637)
Sungguh benar perkataan Umar, safar memang merupakan pengungkap dan pembongkar akhlak seseorang yang sebenarnya. Betapa banyak orang yang tampaknya mulia dan berakhlak baik namun saat kita bersafar bersamanya dalam waktu yang lama dan jarak perjalanan yang jauh, dan berhadapan dengan kesulitan yang membutuhkan pengorbanan maka akan tampak akhlaknya yang asli, yaitu akhlak yang buruk.
Sungguh merupakan kesempatan emas dapat bersafar bersama syaikh Abdurrazzaq, untuk menimba ilmu dari beliau, yaitu melalui akhlak beliau di saat bersafar. Akhirnya, tiba waktu safar yaitu hari senin tanggal 25 Muharram 1431 H yang bertepatan dengan tanggal 11 Januari 2010. Seperti biasa, hari ahad sore beliau masih menyampaikan kajian di Radio Rodja. Setelah menutup kajian, aku pun menyampaikan kepada kru Radio Rojda bahwa esok hari (hari Senin) tidak ada kajian karena kita akan bersiap safar, mengingat jadwal keberangkatan pesawat pada pukul 19.15, lansung setelah shalat maghrib. Sementara pengajian biasanya berakhir sekitar pukul 18.00. Tentunya aku menyampaikan hal ini kepada kru Radio Rodja tanpa seizin syaikh. Setelah itu aku menyampaikan kepada beliau hal tersebut. Beliau pun berkata, “Ndak, besok tetap ada pengajian, insya Allah waktunya cukup, dan ada orang lain yang akan mengurus masalah penerbangan, jadi kita hanya tinggal berangkat.” Keesokan harinya aku pun ke rumah beliau dengan membawa barang-barangku yang akan kubawa untuk bersafar. Selepas shalat ashar, beliau meminta tolong salah seorang saudara kandungnya untuk membawa seluruh barang-barang bawaan safar sekaligus mengurus penerbangan kami, sementara kami tetap mengadakan pengajian. Usai pengajian, kami langsung beranjak menuju bandara. Aku masih ingat saat kami sampai di bandara adzan maghrib berkumandang, setelah itu Syaikh bertanya kepadaku, “Bukankah untuk penerbangan internasional lokasinya di sana?” Aku menjawab, ”Iya syaikh, tetapi sudah pindah ke lokasi yang lain.” Akhirnya, kami pun turun di lokasi yang lain untuk masuk ke ruang tunggu. Ternyata di saat kami akan masuk, kami diberitahu oleh petugas bandara bahwa itu adalah ruang tunggu untuk penerbangan domestik. Adapun ruang tunggu penerbangan internasional lokasinya sebagaimana yang ditunjukkan oleh Syaikh sebelumnya. Aku pun merasa tidak enak, tetapi ternyata beliau sama sekali tidak marah dan tidak tampak kekesalan beliau terhadap kesalahanku. Akhirnya, kami pun berjalan kaki agak jauh menuju lokasi tersebut, padahal tas koper yang dibawa oleh Syaikh cukup berat, namun beliau tetap membawanya tanpa ada keluhan sama sekali. Setiba di ruang tunggu beliau langsung melaksanakan shalat magrib secara berjama’ah. Setelah selesai shalat, aku pun mendekati beliau dan berkata, “Syaikhanaa, apa kita tidak menjamak shalat maghrib dan isya saja? karena shalat di pesawat repot?” Beliau menjawab, “Tidak, shalat isya kita kerjakan di pesawat saja.” Setelah itu beliau pun shalat sunnah ba’da maghrib dua rakaat kemudian kita pun masuk ke dalam ruangan tunggu untuk bersiap naik pesawat.
Saat berada di ruang tunggu, aku pun berkata kepada beliau, “Yaa Syaikh, apa perlu aku ceritakan kepada antum tentang kondisi peta dakwah di Indonesia, agar antum punya gambaran tentang kondisi dakwah dan perpecahan yang ada di Indonesia, ataukah tidak perlu?” Beliau pun menjawab, “Aku rasa tidak perlu, karena aku ke Indonesia bukan untuk memihak salah satu dari golongan yang ada. Aku ke Indonesia untuk silaturrahmi dan mengunjungi Radio Rodja. Apakah engkau suka ya Firanda kalau ada seorang syaikh yang datang ke saudara-saudaramu yang berselisih denganmu, kemudian mereka menceritakan keburukan-keburukanmu kepada syaikh tersebut? tentu engkau tidak suka[1]. Demikian juga dengan yang lainnya, sebaiknya engkau tidak perlu menceritakan kondisi saudara-saudaramu yang berselisih denganmu. Toh, mereka tidak berselisih denganmu pada permasalahan aqidah. Engkau dan mereka saling bersaudara di atas aqidah yang satu.”
Aku pun terdiam. Jawaban ini sebenarnya telah aku duga sebelumnya, hanya saja aku memberanikan diri untuk menanyakannya. Selain itu, hal tersebut karena ada dorongan dari sebagian teman-teman senior agar syaikh juga mengerti hal ini, sehingga dapat mengusahakan agar adanya persatuan. Beberapa menit berikutnya aku berkata lagi, “Yaa Syaikh, sebagian orang ada yang menyatakan bahwa aku adalah Kadzdzaab (pendusta), Dajjaal, dan Khabiits. Apakah aku berhak untuk membela diri dan membantah tuduhan tersebut?” Beliau menjawab, “Wahai Firanda, jangan kau bantah ia, bagaimanapun ia adalah saudaramu seaqidah. Bahkan, jika ada orang yang bertanya kepadamu tentangnya, maka tunjukkan bahwa engkau tidak suka untuk membantah dan tidak suka membicarakannya.” Beliau terdiam sejenak, lalu melanjutkan nasihatnya, “Engkau bersabar, dan jika engkau bersabar percyalah suatu saat ia akan melunak dan akan menjadi sahabatmu.” Aku jadi teringat saat musim fitnah tahdzir mentahdzir di kota Madinah sekitar tahun 2002 dan sempat tersebar tuduhan bahwa Syaikh adalah mubtadi’. Tuduhan tersebut dilontarkan oleh sebagian Syaikh yang lain, yang juga beraqidah yang lurus. Bahkan di antara tuduhan yang sangat buruk terhadap Syaikh –sebagaimana pernah aku baca langsung tuduhan tersebut- syaikh dikatakan terpengaruh dengan faham sufiah. Kemudian dikatakan bahwa Syaikh telah mempengaruhi ayah beliau, Syaikh Abdul Muhsin. Subhaanallah, tuduhan yang sangat buruk, apakah syaikh Abdurrazzaq seorang profesor di bidang Aqidah terpengaruh paham sufi? Bahkan berhasil memasukkan paham tersebut kepada ulama besar sekaliber Syaikh Abdul Muhsin Al-‘Abbad? Apakah karena perhatian beliau terhadap akhlak dan sikap beliau yang tidak suka membicarakan kejelekan dan kesalahan orang lain, kemudian beliau dikatakan sufi? Namun, Syaikh sama sekali tidak pernah menggubris tuduhan-tuduhan tersebut seakan-akan beliau tidak tahu, bahkan tidak ada sama sekali.[2]
Di antara nasihat beliau yang pernah aku dengar, yang berkaitan dengan permasalahan bantah-membantah, yaitu nasihat beliau tentang kenyataan yang terjadi di medan dakwah saat seseorang membantah yang lain, tetapi tidak dengan adab yang benar. Beliau membacakan kepadaku sebuah perkataan emas yang pernah dituliskan oleh seorang ulama yang dikenal dengan Al-Imam Ibnu Syaikh Al-Hizamiyin (yang wafat pada tahun 711 H) dalam sebuah kitabnya yang menceritakan tentang perjalanannya dari pemahaman sufi yang menyimpang hingga akhirnya ia mendapatkan hidayah dan mengenal pemahaman ahlus sunnah.[3] Ibnu Syaikh Al-Hizamiyin berkata, “Ilmu ini (menjelaskan dan membantah kesesatan pihak yang lain-pen) hukumnya haram bagi orang yang berkeinginan untuk menjatuhkan harga diri manusia untuk memuaskan kehendaknya yang rusak atau untuk mendukung hawa nafsu yang diikuti. Ilmu ini hukumnya mubah (boleh) bahkan mustahab bagi orang yang hendak menjaga dirinya agar tidak terpengaruh pada kesalahan-kesalahan dan terjerumus dalam dosa. Ilmu ini tidak boleh dan tidak mustahab bagi seseorang yang hanya ingin mencela atau mengejek sehingga menjadikan pembicaraan kesalahan orang lain sebagai bahan tertawaan dan candaan, bukan sebagai sarana untuk mengenal kesalahan agar tidak terjerumus dan sebagai bahan pelajaran. Akhirnya, ia pun mengungkap tirai yang menutup kesalahan-kesalahan orang lain tanpa niat yang benar. Padahal setiap amalan tergantung niatnya, dan setiap orang memperoleh balasan sesuai dengan niatnya” (Rihlatu Al-Imam. hlm. 16). Syaikh mengomentari perkataan emas ini dengan berkata, “Betapa banyak di antara kita yang butuh akan nasihat yang sangat berharga ini.”[4]
Tidak berapa lama kemudian, mulailah para penumpang menaiki pesawat dari maskapai penerbangan Saudi Airlines. Aku ingatkan beliau bahwasanya beliau akan duduk di bagian depan pesawat karena beliau di kelas eksekutif. Adapun aku duduk di belakang karena berada di kelas ekonomi. Setelah kami berada di atas pesawat, kebetulan aku duduk di samping kiri dua orang tenaga kerja wanita yang pulang dari Arab Saudi ke Indonesia. Jadi, posisiku No. 3 dari jendela pesawat. Namun, Al-Hamdulillah, setelah pesawat berangkat ada empat kursi kosong di sebelah kiriku, dan akhirnya aku pun pindah kursi duduk. Pesawat lepas landas sekitar pukul 7.30 malam. Kondisiku saat pukul 11 malam antara tidur dan tidak karena kebiasaanku sulit untuk tidur di atas pesawat. Namun akhirnya aku pun tertidur. Tiba-tiba sekitar pukul 12 malam, Syaikh membangunkan aku. Beliau berkata, “Firanda, kapan adzan shubuh?” Pertanyaan ini wajar, mengingat waktu Jakarta lebih maju 4 jam dari waktu Arab Saudi. Aku katakan, “Kira-kira 3 jam lagi ya Syaikh.” Beliau berkata, “Hati-hati, jangan sampai kita terlambat shalat, apabila telah tiba waktu shalat kamu ke bagian depan pesawat beritahu aku.”
Setelah itu aku semakin gelisah, padahal rasa kantuk yang sangat berat sedang menyerang mataku. Saat tiba jam tiga, pandanganku mulai terkonsentrasi ke luar jendela pesawat, siapa tahu terlihat cahaya putih sebagai tanda telah terbit fajar shadiq. Akan tetapi, karena kondisiku yang sedikit jauh dari jendela membuatku selalu ragu. Aku tidak dapat melihat dekat ke jendela, karena dihalangi oleh dua kursi yang ditempati dua orang TKW. Namun, dari jauh langit masih kelihatan gelap. Akhirnya saat pukul 3.45 shubuh, kulihat tampak cahaya di langit, aku pun segera menuju ke bagian depan pesawat untuk memberitahu syaikh, ternyata aku mendapatinya sudah selesai shalat shubuh. Rupanya sudah masuk waktu shalat shubuh sejak jam 3, hanya saja aku yang tidak dapat melihat langit dengan jelas. Akhirnya, Syaikh menyuruhku untuk segera berwudhu, kemudian menyuruhku untuk shalat sunnah fajar. Setelah itu aku pun shalat shubuh berjama’ah bersama salah seorang penumpang yang lain. Lihatlah bagaimana perhatian syaikh untuk bisa shalat shubuh tepat pada waktunya dan diawal waktu, meskipun beliau sedang berada di atas pesawat.
Setelah shalat aku pun kembali ke kursiku di bagian belakang pesawat. Beberapa jam kemudian, akhirnya pesawat pun mendarat di bumi tercinta Indonesia di Bandara Sukarno Hatta, Cengkareng, Jakarta, yaitu pada hari Selasa, tepat sekitar pukul 12 siang WIB. Saat turun dari pesawat aku melihat Syaikh disapa oleh salah seorang penumpang pesawat yang juga bersafar dari Arab Saudi. Orangnya sedikit tua dan naik kursi roda. Hatiku bertanya-tanya siapa gerangan orang ini, sepertinya kenal baik dengan syaikh. Syaikh menjelaskan kepadaku, orang tersebut rupanya adalah orang kaya dan memiliki banyak kantor untuk mendatangkan tenaga kerja dari Indonesia ke Arab Saudi. Syaikh tampak banyak mengobrol bersamanya, dan menghadiahkan beberapa tulisan Syaikh kepada orang tersebut, di antaranya kitab beliau yang berjudul Kunci-Kunci Kebaikan, dan juga transkrip ceramah beliau yang berjudul Sebab-Sebab Kebahagiaan. Kata Syaikh, “Yaa semoga bermanfaat bagi orang ini”. Hatiku bergumam, “Subhaanallah, syaikh..syaikh.. sempat-sempatnya berdakwah di pesawat.”
Rencananya, kami akan langsung melanjutkan safar menuju ke pulau Lombok pada pukul 5 sore, tetapi tampak keletihan pada wajah beliau. Akhirnya, kru Radio Rodja menawarkan kepada beliau untuk beristirahat semalam di Jakarta untuk perawatan medis tradisional. Tadinya beliau masih nekat untuk tetap hari itu juga berangkat ke Lombok. Namun, kondisi beliau yang agak payah, karena memang beliau baru saja bersafar ke Kuwait untuk mengisi pengajian dan beliau tiba di kota Madinah dua hari sebelum keberangkatan ke Jakarta, terlebih lagi batuk yang beliau derita sudah hampir sebulan belum juga hilang. Akhirnya beliau pun memilih untuk beristirahat di Jakarta.
Kami pun beranjak dari bandara menuju hotel milik salah seorang ikhwah. Beliau pun beristirahat di hotel. Saat tiba di hotel, kami pun makan siang ditemani pemilik hotel tersebut yang juga sering mendengarkan ceramah Syaikh di Radio Rodja. Syaikh meminta agar pemilik hotel tersebut duduk di hadapan beliau, sedang aku duduk di samping pemilik hotel untuk menerjemahkan pembicaraan antara Syaikh dengan pemilik hotel itu. Saat Syaikh melihat beberapa jenis makanan yang aneh –yang tentunya tidak ada di Arab Saudi- beliau bertanya kepadaku mengenai makanan tersebut. Akhirnya beliau menunjuk pada sebuah makanan kecil-kecil yang berwarna coklat yang terletak di atas piring kecil, maka aku katakan itu adalah kue. Beliau pun mencobanya, namun ternyata makanan itu bukan kue, tetapi ayam goreng yang dipotong kecil-kecil. Beliau pun berkata kepada para hadirin sambil bercanda, “Firanda ini kalau menerjemahkan pengajian benar, tetapi diminta menerjemahkan makanan salah terjemah.” Para hadirin yang ikut makan bersama kami pun tertawa. Saat kami sedang makan, Syaikh juga mengambil makanan lalu beliau sodorkan ke salah seorang penyiar di radiorojda seraya berkata, “Si fulan ini harus makan lebih banyak karena badannya lemah.” Para hadirin kembali tertawa karena memang si penyiar Radio Rodja tersebut bertubuh kurus. Demikianlah Syaikh terkadang bercanda untuk menyenangkan hati orang-orang yang di sekitar beliau.
Usai makan siang, Syaikh pun diantar oleh pemilik hotel ke kamar yang telah disediakan untuk beliau. Setelah itu beliau pun memberi hadiah kepada pemilik hotel tersebut sebuah buku karya beliau yang berjudul Kunci-Kunci Kebaikan, dan tidak lupa beliau menulis di depan buku tersebut, “Hadiah untuk ustadz fulan dari Abdurrazzaq Al-Badr”. Subhaanallah, Syaikh Abdurrazzaq menulis demikian untuk menyenangkan hati pemilik hotel tersebut. Beliau menuliskan namanya kemudian menyebut orang tersebut dengan didahului panggilan ustadz, semuanya hanya untuk menyenangkan hati orang tersebut. Padahal aku tidak pernah melihat beliau melakukannya kepada para penuntut ilmu. Jika beliau memberi hadiah kepada mereka maka tanpa menulis sesuatupun di buku tersebut. Penulisan tersebut kelihatannya sepele dan tidak membutuhkan tenaga dan waktu, tidak sampai satu menit, namun betapa gembiranya hati pemilik hotel tersebut.
Akhirnya Syaikh pun beristirahat sebentar, dan selepas shalat isya datanglah seorang pakar herbal yang siap untuk mengobati dan memijit Syaikh. Malam itu Syaikh dipijit refleksi oleh orang tersebut, kurang lebih selama 1 jam setengah. Terkadang memijit bagian tubuh Syaikh yang menimbulkan rasa kesakitan. Aku mengetahuinya dari mimik wajah Syaikh yang menunjukkan rasa kesakitan yang sangat, namun beliau bersabar. Aku bertanya kepada beliau, “Sakit Syaikh?” Beliau menjawab, “Iya, tetapi aku sabar insyaa Allah”. Tidak sekalipun ada suara yang timbul dari beliau yang menandakan rasa sakit. Beliau pun diharuskan untuk meminum jamu yang telah dibawa oleh orang tersebut. Rupanya syaikh cocok dengan tukang pijit tersebut, maka syaikh berkata kepadaku, “Apakah bisa akh fulan (si ahli herbal) ini ikut safar bersama kita ke Lombok? kalau tidak memberatkan panitia?.” Al-Hamdulillah, panitia menyanggupi hal tersebut.
Keesokan harinya, kami pun berangkat menuju pulau Lombok. Kami tiba di Bandara lebih awal. Saat tiba di bandara, beliau minta untuk diantar ke mushala, aku bersama ahli herbal tersebut menemani Syaikh ke mushalla. Sesampainya kami di mushalla, Syaikh menuju kamar kecil. Saat menunggu Syaikh, si ahli herbal bertanya kepadaku, “Apakah ustadz Firanda mengenal banyak Syaikh, kalau iya siapa saja?” Aku pun secara spontan menjawab, “Aku kenal banyak Syaikh, tetapi tidak seorangpun dari mereka yang mengenalku. Bahkan Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili yang pernah mengajarku selama setahun, jika bertemu ia pasti ingat bahwa aku pernah menjadi murid beliau, tetapi tidak tahu namaku, karena memang beliau tidak mengenalku. Apalagi Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili lebih-lebih lagi tidak mengenalku sama sekali. Yang dekat dengan Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili adalah Ustadz Abdullah Zain dan Ustad Anas Burhanuddin, dan yang dekat dengan Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili adalah Ustadz Muhammad Arifin. Adapun yang aku kenal hanyalah Syaikh Abdurrazzaq, itupun karena beliau pernah mengajarku selama dua tahun, dan sekarang menjadi dosen pembimbingku dalam menulis tesis selama tiga tahun. Kalau tidak, tentu beliau tidak akan mengenalku.” Ahli herbal ini sedikit terperanjat saat mendengar tuturanku ini. Ia berkomentar, “Ustadz Firanda kok jawabannya lain, ada sebagian ustadz apabila ditanya ngaku-ngaku dekat dengan para masyaayikh.” Aku pun terdiam.[5]
Tidak lama kemudian syaikh keluar dari kamar kecil hendak berwudhu, saat itu beliau memakai sepatu, dan hendak ke tempat wudhu. Namun, beliau berhenti sebentar, kemudian bertanya kepada kami berdua yang sedang duduk ngobrol, “Firanda, apa tidak masalah aku ke tempat wudhu dengan mengenakan sepatu?” Dengan spontan aku menjawab, “Tidak jadi masalah Syaikh, silakan.” Rupanya bagi syaikh itu sebuah masalah, lalu beliau berkata, “Tolong tanyakan ke petugas kebersihan.” Aku pun bertanya atau meminta idzin kepada petugas kebersihan tersebut, maka dengan serta merta ia mempersilakan syaikh untuk tetap menggunakan sepatu beliau. Lalu Syaikh pun memasuki mushala dan shalat sunnah, sementara aku dan ahli herbal tetap ngobrol menunggu tibanya jadwal keberangkatan pesawat. Ahli herbal tersebut agak terkagum dengan sikap Syaikh, seraya berkata, “Subhaanallah, begitu saja kok Syaikh minta izin segala, kalau kita mungkin langsung “nyelonong” memakai sepatu ke tempat wudhu.”
Akhirnya kami pun naik ke pesawat, dan Al-Hamdulillah, panitia menyediakan tiket kelas eksekutif. Akhirnya aku dan syaikh duduk di bagian paling depan pesawat Garuda. Setelah pesawat lepas landas, Syaikh sempat bercerita sebentar kepadaku, beliau berkata, “Waktu lalu saat aku balik dari Kuwait menuju Riyadh, ternyata pilot pesawatnya adalah salah seorang saudara dari seorang ikhwah di Kuwait yang ikut menghadiri pengajianku. Lantas sang pilot memberi salam kepadaku lalu mempersilakan aku untuk duduk bersama beliau di kop pilot dan ia menceritakan kepadaku cara mengemudi pesawat. Sungguh menajkubkan saat duduk di depan, kita dapat melihat dunia yang begitu luas dan indah. kemudian saat akan mendarat, pilot tersebut mengatakan kepadaku, “Wahai Syaikh sekarang kita akan mendarat, dan ada dua cara pendaratan, dengan cara otomatis atau cara manual kita yang menggerakkan, antum pilih yang mana?” Aku berkata, “Aku pilih yang manual”, Akhirnya kami pun mendarat.”
Demikianlah, terkadang Syaikh bercerita kepadaku tentang kejadian-kejadian yang menakjubkan dan berkesan yang pernah dilewatinya. Kemudian setelah bercerita beliau berkata, “Firanda aku ingin tidur.” Beliau pun menjulurkan kaki beliau dan tidur. Beberapa kali pramugari mencoba membangunkan beliau dan menawarkan makanan atau minuman dan bahan bacaan seperti koran dan majalah, aku katakan, “Beliau hanya ingin tidur.”
Penulis: Ustadz DR. Firanda Andirja, MA
Tema: SEPENGGAL CATATAN PERJALANAN
DARI MADINAH HINGGA KE RADIORODJA
(Mendulang Pelajaran Akhlaq dari Syaikh Abdurrozzaq Al-Badr hafizohulloh)
__________
Footnote:
[1] Perkataan Syaikh ini merupakan pencerminan dari definisi Akhlaq yang mulia. Adapun penjelasan beliau tentang definisi akhlaq yang mulia yaitu mengacu pada hadits Nabi berikut. Beliau berkata, “Banyak pendapat yang menjelaskan definisi akhlak mulia. Namun, definisi terbaik dari akhlak mulia adalah sabda Nabi :
وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْه
“Hendaknya ia memberi kepada orang lain apa yang ia suka untuk diberikan padanya.” (HR. Muslim No. 1844)
Praktik dari hadits ini, jika engkau ingin bermu’amalah dengan kedua orangtuamu maka bayangkanlah bahwa engkau adalah orangtua. Anggaplah engkau adalah seorang ibu, apa yang kau kehendaki dari anakmu untuk bermu’amalah kepadamu (maka seperti itulah yang kau lakukan terhadap ibumu). Analogikanlah hal ini di saat engkau ingin bermu’amalah dengan tetangga dan sahabatmu. Jika ada sahabatmu yang bersalah kepadamu maka apa sikapmu kepadanya? Bayangkan seandainya engkau adalah sahabatmu yang bersalah itu, apakah yang kau harapkan saat itu? Tentu engkau berharap untuk dimaafkan. Jika demikian maka maafkanlah sahabatmu itu.”
[2] Demikian juga pada kondisi di mana kita dalam keadaan terzalimi. Jika kita tertuduh dengan tuduhan-tuduhan kosong tanpa bukti, hendaknya kita tetap mempraktikkan hal ini. Lihatlah bagaimana sikap Syaikh, meskipun beliau dahulu sering ditahdzir, bahkan dituduh mubtadi’, beliau tidak pernah membalas bahkan menyebutkan kejelekan pihak yang mentahdzir beliau. Beliau pun tidak suka jika ada seseorang yang memancing beliau untuk membantah tuduhan tersebut.
Ibnu Rajab berkata: “Hadits yang sedang kita bicarakan ini menunjukkan bahwa wajib bagi seorang mukmin untuk bergembira jika ada saudaranya yang seiman gembira. Hendaknya ia menginginkan agar saudaranya mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia juga menginginkan kebaikan. Semua ini tidak dapat terwujud kecuali dari hati yang bersih dari sifat dendam, hasad (dengki), dan curang. Sesungguhnya sifat hasad menjadikan pemiliknya benci jika ada orang lain yang mengungguli atau menyamakannya dalam kebaikan. Hal itu karena didorong dengan keinginannya untuk menjadi seseorang yang spesial dan istimewa di tengah-tengah manusia dengan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Akan tetapi, konsekuensi dari iman adalah sebaliknya, yaitu menginginkan agar seluruh kaum mukminin menyamakannya dalam kebaikan yang Allah berikan kepadanya, tanpa mengurangi kebaikan dirinya sedikit pun.” (Jaami’ Al-‘Ulum wa Al– Hikam, I/306)
[3] Kitab tersebut berjudul, “رِحْلَةُ الإِمَامِ ابْنِ شَيْخِ الحَزَّامِيِيْنَ مِنَ تَصَوُّفِ الْمُنْحَرِفِ إِلَى تَصَوُّفِ أَهْلِ الْحَدِيْثِ والأَثَرِ”
[4] Kenyataan pahit yang ada di lapangan, yaitu saat sebagian kita mengkritik sebagian yang lain, bahkan sesama ahlus sunnah- dengan kritikan yang benar, namun dengan cara kritik yang tidak benar. Banyak di antara kita menjadikan majelis kritik sebagai majelis tawa dan humor, bahkan ejekan dan cercaan. Saudara sendiri pun dijadikan bahan lelucon. Bagaimana dengan sabda Nabi:
وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْه
“Hendaknya ia memberi kepada orang lain apa yang ia suka untuk diberikan padanya.”
Apakah ada di antara kita yang suka menjadi bahan lelucon dan ejekan? Bagaimana pula sikap kita dengan sabda Nabi:
لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ
“Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga ia menyukai (menginginkan) bagi saudaranya segala (kebaikan) yang ia sukai bagi dirinya sendiri.”
Bukankah lafazh (ما) dalam kalimat hadits ini: (مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) adalah isim maushul. Dalam kaidah ilmu ushul fiqh disebutkan bahwa isim maushul memberikan makna yang umum (universal)? Renungkanlah penjelasan Syaikh Shalih Alu Syaikh berikut ini, “Hadits di atas mencakup aqidah, perkataan dan perbuatan, yaitu mencakup seluruh bentuk amal shalih, baik keyakinan, perkataan, maupun perbuatan.” Hendaknya seorang mukmin menginginkan agar saudaranya memiliki aqidah yang benar seperti aqidah yang ia yakini. Sikap seperti ini hukumnya wajib. Hendaknya ia juga menginginkan agar saudaranya shalat sebagaimana ia shalat. Sekiranya ia senang jika saudaranya tidak berada di atas petunjuk yang benar, maka ia telah berdosa, dan telah hilang darinya keimanan sempurna yang wajib. Jika ia senang apabila ada saudaranya yang berada di atas aqidah yang batil dan tidak sesuai dengan sunnah, yaitu aqidah bid’ah maka telah ternafikan darinya kesempurnaan iman yang wajib. Demikian pula halnya dengan seluruh peribadatan dan sikap menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Jika ia senang apabila dirinya terbebas dari praktik suap, tetapi ia senang jika ada saudaranya yang terjatuh dalam praktik suap, hingga ia merasa unggul –lebih shalih dari saudaranya tersebut-, maka telah ternafikan kesempurnaan iman yang wajib dari dirinya (ia telah berdosa). (Dari ceramah beliau yang berjudul Huquq Al-Ukhuwwah)
[5] Bukanlah aku menceritakan hal ini untuk menunjukan bahwa aku seorang yang tawadhu –tidak demi Allah- tetapi kenyataannya demikian, tidak seorang syaikh pun yang mengenalku. Bahkan betapa sering aku malu apabila ditanya oleh mahasiswa yang lain, “Siapakah dosen pembimbingmu dalam menulis tesis,” Maka aku katakan, “Syaikh Abdurrazzaq Al-Badr.” Kebanyakan mahasiswa yang mendengar jawaban ini spontan berkomentar, “Ni’mal musyrif”, yang artinya “Sebaik-baik dosen pembimbing.” Jika mendengar komentar ini, aku langsung menimpali dengan perkataanku, “Wa bi’sat thalib,” yang artinya, “Dan seburuk-buruknya murid yang ia bimbing adalah aku.” Komentar ini selalu aku lontarkan karena memang aku tidak merasa pantas dikatakan sebagai murid beliau. Sampai akhirnya ada seorang ustadz di Jedah yang menegurku, dengan perkataannya, “Ya Firanda, janganlah engkau berkata demikian, ana kawatir perkataanmu itu didoakan malaikat,” Setelah itu aku tidak pernah berkomentar demikian. Bahkan tatkala ada seorang teman mahasiswa yang berkata, “Kalau mau menghubungi syaikh Abdurrazzaq hubungi saja Firanda karena ia dekat dengan Syaikh,” Aku pun sedikit “mangkel” mendengar hal itu. Sesungguhnya rasa malu itu timbul saat orang-orang tahu bahwa aku adalah murid beliau, karena yang ada dibenakku seharusnya seorang murid dapat mencerminkan akhlak dan juga ilmu sang guru. Inilah yang menurutku sangat berat. Oleh karena itu, aku tahu benar bahwa teman-teman mahasiswa di Madinah yang berada di jenjang S2 dan S3 yang bertahun-tahun belajar di majelis Syaikh Abdul Muhsin Al-‘Abbad, -ada yang lima tahun, bahkan ada yang lenih 10 tahun- tidak seorang pun dari mereka saat pulang ke Indonesia kemudian membuat iklan pengajian “Hadirilah kajian yang akan disampaikan oleh ustadz Fulan, murid Syaikh Abdul Muhsin Al-‘Abbad”. Oleh karena itu, aku tidak pernah mendapatkan di Arab Saudi satu pengunguman pengajian pun yang menyebutkan “Hadirilah pengajian syaikh fulan, murid syaikh Utsaimin.” atau “….fulan murid Syaikh bin Baaz.”
Akan tetapi, aku memaklumi bahwa sebagian kita ada yang mencantumkan dalam pengunguman bahwasanya ia adalah murid syaikh fulan dan tujuannya tidak lain adalah demi kemaslahatan masyarakat. Terkadang masyarakat mungkin tidak tahu bahwasanya ia adalah orang yang telah banyak menuntut ilmu. Atau agar orang-orang awam yang melihat pengunguman tersebut tertarik untuk menghadiri pengajiannya.