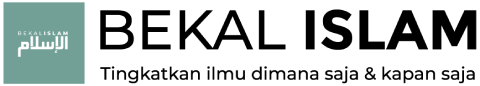لاَ يَقُوْلُ: عَبْدِي وَأَمَتِي
Larangan Mengucapkan “Abdi dan Amati” (Hambaku)
Oleh DR. Firanda Andirja, Lc. MA.
Matan
Diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ وَضِّئْ رَبَّكَ، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلاَيَ، وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلاَمِي
“Janganlah seorang dari kalian berkata (ketika memerintahkan budaknya dengan kalimat): ‘Hidangkanlah makanan untuk rabb kamu, berilah minuman untuk rabbmu’, akan tapi hendaklah dia berkata (dengan kalimat): ‘sayyidku dan maulaku (pemeliharaku)’. Dan janganlah seorang dari kalian mengatakan: ‘Abdi (hamba sahaya laki-lakiku), dan Amati (hamba sahaya perempuanku)’, akan tapi Katakanlah: ‘fataya (pemudaku), Fatatiy (pemudiku) dan ghulami (budakku)’.”
Syarah
Pembahasan ini tentunya berkaitan zaman dahulu ketika masih ada perbudakan, yaitu seorang majikan tidak boleh memanggil budak laki-lakinya dengan عَبْدِي “Abdi” dan bagi budak perempuannya dengan mengatakan أَمَتِي “Amati”. Hadits di atas mengajarkan kepada kita untuk tidak sembarang mengucapkan lafal, karena lafal juga berkaitan dengan masalah tauhid.
Kita tentu mengetahui bahwasanya semua makhluk yang ada di alam semesta ini adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa ta’ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta’ala,
إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا
“Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada (Allah) Yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba.” (QS. Maryam: 93)
Kita semua ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta’ala, dan Allah Subhanahu wa ta’ala adalah Rabb kita. Oleh karena itu bab ini mengajarkan kepada kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta’ala, yaitu dengan cara kita tidak mengucapkan lafal yang semakna dengan Allah Subhanahu wa ta’ala meskipun niat kita tidak demikian. Contohnya seperti seorang budak yang berkata kepada tuannya “Ya Rabbku” (Wahai Tuanku). Akan tetapi karena makna “Rabb” mirip dengan Allah, maka bentuk lafal seperti itu harus dijauhi untuk disebutkan kepada manusia, dan hendaknya dia ganti dengan “Ya Sayyidi” atau “Ya Maulaya” (Wahai Tuanku), karena lafal makna tersebut tidak mirip dengan nama Allah Subhanahu wa ta’ala.
Penggunaan kata الرَّبُّ (pemilik)
Penggunaan kata الرَّبُّ bisa dalam dua bentuk penggunaan,
Pertama: kata الرَّبُّ secara mutlak, maka hal ini tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta’ala semata, karena kata الرَّبُّ dengan alif lam yang menunjukkan “Sang Pemilik”, sehingga maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta’ala.
Kedua: kata رَبُّ secara penyandaran (عَلَى سَبِيْلِ الْإِضَافَة), contohnya seperti perkataan “رَبُّ كَذَا وَكَذَا” (pemiliki ini dan itu), maka yang hal in bisa memiliki dua kemungkinan:
1, Jika diidhafahkan (disandarkan) kepada selain manusia, maka hal ini tidak mengapa. contoh seperti perkataan: رَبُّ الدَّارِ (sang pemilik rumah), رَبُّ الْإِبِل (sang pemilik unta). Contoh semacam ini tidak mengapa digunakan karena unta dan rumah tidak dibebani untuk beribadah. Maksudnya adalah ketika ada orang yang mengatakan “Saya rabbnya unta”, maka itu tidak mengapa karena unta tidak pernah dibebani untuk menyembahnya dan juga unta tidak pernah menyembahnya. Dan hal ini pernah dikatakan oleh kakek Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam Abdul Muthalib ketika dirampas untanya oleh Abrahah sebanyak dua ratus ekor, maka Abdul Muthalib datang kepada Abrahah dan meminta kembali untanya yang telah dirampas, maka Abarahah berkata,
لَقَدْ كُنْتَ أَعْجَبْتَنِي حِينَ رَأَيْتُكَ، ثُمَّ قَدْ زَهِدت فِيكَ حِينَ كَلَّمْتَنِي، أَتُكَلِّمُنِي فِي مِائَتَيْ بَعِيرٍ أَصَبْتُهَا لَكَ، وَتَتْرُكُ بَيْتًا هُوَ دِينُكَ وَدِينُ آبَائِكِ قَدْ جئتُ لِهَدْمِهِ، لَا تُكَلِّمُنِي فِيهِ؟!
“Sesungguhnya pada mulanya ketika aku melihatmu, aku merasa kagum dengan penampilan dan wibawamu. Tetapi setelah engkau berbicara kepadaku, kesanku menjadi sebaliknya; apakah engkau berbicara kepadaku hanya mengenai dua ratus ekor unta yang telah kurampas darimu? Sedangkan engkau meninggalkan Ka’bahmu yang merupakan agamamu dan agama nenek moyangmu, padahal aku datang untuk merobohkannya, lalu mengapa engkau tidak berbicara kepadaku mengenainya?”
Maka Abdul Muthalib berkata,
إِنِّي أَنَا رَبُّ الْإِبِلِ، وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رِبًّا سَيَمْنَعُهُ
“Sesungguhnya aku adalah pemilik unta itu dan sesungguhnya bait itu mempunyai Pemiliknya sendiri yang akan menjaganya.”([1])
Dalam hadits juga disebutkan bahwa ada seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam,
قَالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قَالَ: هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ، قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ المَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا
“Orang tersebut berkata ‘Bagaimana hukum menemukan kambing?’ Nabi berkata, ‘Kambing itu untukmu, atau untuk saudaramu, atau akan dimakan oleh serigala’. Orang tersebut betaka, ‘Bagaimana dengan unta?’ Nabi berkata, ‘Apa urusanmu dengan unta tersebut, unta tersebut memiliki kantung minum untuk dia minum, dia memiliki kaki, dia bisa datang ke tempat sumber air, dan dia bisa ke pohon untuk makan, hingga dia bertemu dengan pemiliknya’.”([2])
Ini menunjukkan bahwa penyandaran kata رَبُّ kepada selain manusia dan Allah maka tidak mengapa.
2. Jika kata رَبُّ diidhafahkan (disandarkan) kepada manusia. Untuk hal ini ada dua kondisi,
- Kondisi pertama: Jika bukan dalam bentuk mukhatabah (kata ganti orang kedua), tetapi sebagai pengkhabaran atau sebagai orang ketiga. Contohnya jika seseorang mengatakan الْحَسَنُ رَبُّ خَالِدٍ “Hasan rabbnya Kholid” (Hasan adalah tuannya/majikannya Kholid), maka pada kondisi ini terdapat khilaf yang panjang di kalangan para ulama, akan tetapi penulis sendiri lebih condong kepada pendapat bahwa hal ini tidak mengapa, karena banyaknya dalil yang menunjukkan kebolehannya. Contohnya seperti sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam tentang tanda-tanda hari kiamat,
أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا
“Apabila seorang budak wanita melahirkan (anak) tuannya.”([3])
di sini Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam menggunakan kata رَبُّ sebagai kata ganti orang ketiga. Contoh lain seperti perkataan Nabi Yusuf ‘alaihissalam kepada yang menemaninya di penjara,
اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ
“Terangkanlah (sebut-sebut) keadaanku (tentangku) di sisi tuanmu.” (QS. Yusuf: 42)
Demikian pula Nabi Yusuf ‘alaihissalam berkata kepada orang yang datang kepadanya,
ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ
“Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha Mengetahui tipu daya mereka.” (QS. Yusuf: 50)
Kemudian perkataan Nabi Yusuf ‘alaihissalam pula ketika dirayu oleh istri penguasa, dia berkata,
إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ
“Sungguh, tuanku telah memperlakukan aku dengan baik.” (QS. Yusuf: 23)
Ini semua bentuk penggunaan kata رَبُّ bukan dalam bentuk mukhatabah, akan tetapi sebagai bentuk kata ganti orang ketiga, dan yang demikian tidak mengapa, meskipun telah kita sebutkan bahwa hal ini ada khilaf di kalangan para ulama, namun yang benar adalah tidak mengapa.
- Kondisi kedua: Jika dalam bentuk mukhatabah (pembicaraan kepada orang dengan kata ganti orang kedua). Contoh seorang majikan yang berkata kepada budaknya “Wahai Abdi (budak laki-lakiku), wahai Amati (budak wanitaku), beri makan kepada rabbmu (tuanmu)”, atau seorang budak yang berkata kepada tuannya “Wahai rabb(tuan)ku”. Penggunaan kata “Rabb” dan “Abdi” dalam contoh ini, jika digunakan pada pembicaraan orang kedua, maka hal ini para ulama sepakat bahwa tidak boleh, hanya saja kemudian para ulama khilaf kembali apakah tidak bolehnya makruh atau haram, namun pendapat yang benar adalah haram.
Permasalahannya di sini adalah lafal ini mirip penggunaannya terhadap Allah, meskipun dikatakan secara bahasa tidak mengapa, akan tetapi secara makna dikhawatirkan menyaingi Allah Subhanahu wa ta’ala, sehingga Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam melarang untuk mengucapkan demikian.

Inilah pembahasan kita terkait penggunaan kata الرَّبُّ. Adapun poin pembahasan kita adalah pada bentuk penggunaan kedua, pada kondisi kedua, yaitu ketika kata رَبُّ digunakan dalam bentuk mukhatabah terhadap manusia, dan tentunya ketika terjadi perbudakan. Ketika perbudakan itu terjadi, maka tidak boleh antara majikan dengan budak menggunakan kata-kata yang seakan-akan menunjukkan persaingan terhadap Allah Subhanhu wa ta’ala. Maka tidak boleh seorang majikan berkata kepada budaknya dengan mengatakan “Wahai Abdi (budak laki-lakiku)” dan “Wahai Amati (budak perempuanku)”, karena hal itu adalah kebiasaan Allah Subhanhu wa ta’ala dalam berkata kepada makhluk-Nya, akan tetapi hendaknya dia mengatakan “Wahai ghulami (budakku)”. Demikian juga seorang majikan tidak boleh mengatakan kepada budaknya dengan berkata “Wahai abdi (hambaku), beri makan rabb(tuan)mu”.
Oleh karena itu, lafal-lafal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam tersbeut diganti dengna lafal-lafal yang dibolehkan. Yaitu lafal رَبُّ diganti dengan سَيِّدِي atau مَوْلاَيَ yang maknanya sama dengan “Tuanku”. Kata سَيِّدِي juga tidak mengapa karena datang dalam banyak riwayat bahwa Rasululllah Shallallahu ‘alaihi wasallam menamakan seseorang dengan “sayyid”. Memang ada riwayat yang menyebutkan bahwa سَيِّدِ adalah Allah Subhanhu wa ta’ala, akan tetapi maksudnya adalah sayyid yang sempurna, karena di antara makna الصَّمَد adalah,
السيد الذي قد كمل في سؤدده
“Allah adalah pemilik yang paling sempurna dalam kemuliaan-Nya.”
Intinya, lafal “sayyid” boleh diberikan kepada selain Allah Subhanhu wa ta’ala, seperti Allah berkata tentang Nabi Yahya ‘alaihissalam dalam firman-Nya,
فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ
“Kemudian para malaikat memanggilnya (Zakaria), ketika dia berdiri melaksanakan shalat di mihrab, ‘Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran) Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat (firman) dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.” (QS. Ali-‘Imran: 39)
Contohnya pula Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
“Aku adalah pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat kelak.”([4])
Contohnya pula seperti Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam berkata tentang Hasan dan Husain radhiallahu ‘anhuma,
الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ
“Hasan dan Husain adalah dua pemimpin para pemuda penghuni surga.”([5])
Demikian pula Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam berkata tentang Abu Bakar dan ‘Umar radhiallahu ‘anhuma,
أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ
“Abu Bakar dan Umar adalah pemimpin orang-orang dewasa penduduk surga dari golongan terdahulu maupun yang terakhir, kecuali para nabi dan rasul.”([6])
Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam juga pernah berkata ketika Sa’ad bin Mu’adz radhiallahu ‘anhu datang,
قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ
“Berdirilah kalian untuk menghormati pemimpin kalian.”([7])
Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam juga berkata tentang Sa’ad bin ‘Ubadah radhiallahu ‘anhu,
اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ
“Dengarlah apa yang telah dikatakan oleh pemuka kalian ini!”([8])
Oleh karena itu, penggunaan lafal سَيِّدِي adalah tidak mengapa karena banyaknya dalil yang meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam menggunakan lafal tersebut untuk para sahabat. Kemudian lafal عَبْدِي atau وَأَمَتِي diganti dengan lafal فَتَايَ, وَفَتَاتِي, atau وَغُلاَمِي yang semuanya maknanya sama dengan “Hambaku”.
Pembahasan ini bisa kita katakan tidak begitu penting untuk saat ini karena sudah tidak ada lagi perbudakan. Perbudakan, salah satu sumber terjadinya adalah dengan adanya peperangan([9]). Perbudakan pada asalnya telah ada sebelum Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam diutus. Romawi, Persia, Afrika dan negara-negara lainnya telah mempraktikkan perbudakan. Maka kemudian Islam datang dalam rangka untuk mengatur perbudakan, bahkan datang untuk mengecilkan perbudakan, dan ini ditandai dengan banyaknya dalil yang mengajurkan kita untuk membebaskan budak dan keutamaan-keutamaannya. Kalaupun sekiranya seseorang menahan budaknya, maka Islam mengajarkan agar seseorang harus berbuat baik kepada budaknya, dan di antara wasiat Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam ketika meninggal dunia beliau mengatakan,
الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
“Perhatikan shalat, perhatikan shalat, dan perhatikan budak yang kalian miliki.”([10])
Wasiat Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam ini tentunya menggambarkan akan pentingnya menjaga budak dan memperlakukan mereka dengan baik. Maka jika sekiranya peperangan terjadi, dan perbudakan terjadi([11]), maka hendaknya kita memperhatikan hal-hal ini, karena ini berkaitan dengan tauhid seseorang.
Matan
Kandungan bab ini:
- Larangan mengatakan “Abdi” dan “Amati”
- Larangan bagi seorang hamba sahaya (budak) untuk memanggil majikannya dengan ucapan “Rabb”, dan larangan seorang majikan memanggil budaknya dengan berkata “Hidangkan makanan bagi rabbmu”
- Dianjurkan kepada majikan untuk memanggil budaknya dengan mengatakan “Fataya” atau “Gulami”
- Dianjurkan kepada budak untuk memanggil tuannya (majikannya) dengan panggilan “Sayyidi” dan “Maulaya”
- Tujuan dari anjuran di atas adalah untuk mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, sampai dalam hal ucapan
Artikel ini penggalan dari Buku Syarah Kitab At-Tauhid Karya Ustadz DR. Firanda Andirja, Lc. MA.
_______________________
([1]) Tafsir Ibnu Katsir 8/485
([2]) HR. Bukhari no. 2429
([3]) HR. Muslim no. 8
([4]) HR. Muslim no. 2278
([5]) HR. Ibnu Majah no. 118
([6]) HR. Ibnu Majah no. 95
([7]) HR. Bukhari no. 6262
([8]) HR. Muslim no. 1498
([9]) Jika kemudian perbudakan diadakan dengan cara meranmpas atau menculik orang di jalan lalu kemudian dijadikan budak, atau memperjual belikan, maka yang demikian tidak boleh karena bukan sebab terjadinya perbudakan.
([10]) Shahihul Jami’ wa Ziayadah no. 3873
([11]) Bisa jadi peperangan terjadi namun dunia Internasional bersepakat bahwa tetap tidak ada perbudakan, dan yang kalah hanya tinggal membayar atau yang semisalnya, maka ini tidak mengapa. Atau jika ada kesepakatan antara kaum muslimin dan orang kafir untuk tidak mengadakan perbudakan setelah peperangan maka tidak mengapa.