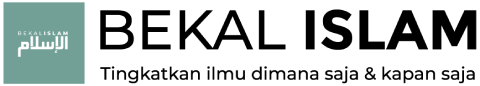قول الله تعالى: يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ
Mereka Mengetahui Nikmat Allah Kemudian Mengingkarinya Dan Kebanyakan Mereka Adalah Orang-orang Kafir
Oleh DR. Firanda Andirja, Lc. MA
Syarah
Maksud dari bab ini dan bab-bab setelahnya adalah tentang bagaimana seorang berhati-hati dalam berkata-kata, agar jangan sampai dia menodai tauhidnya dengan perkataan yang salah. Di antara perkataan yang bisa menodai tauhid kita adalah menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa ta’ala, atau menyandarkan nikmat kepada sebab dan bukan kepada Al-Musabbib (yang menciptakan sebab) yaitu Allah Subhanahu wa ta’ala. Pembahasan ini menjadi pembahasan yang juga penting karena tauhid harus bersih dan jangan sampai ternodai dengan sedikit noda pun. Oleh karena itu dalam berkata-kata pun kita harus berhati-hati karena salah berkata bisa menodai kemurnian tauhid kita.
Sikap Seseorang Yang Diberi Nikmat
Ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta’ala, maka ada tiga sikap yang harus kita kerjakan,
- الاِعْتِرَافُ بِالقَلْبِ (Al-I’tiraf Bilqalbi) – Mengakui dengan hati
Tatkala seseorang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta’ala, maka ada dua hal yang dia harus lakukan dengan hatinya:
Pertama, meyakini dengan hati bahwasanya seluruh nikmat semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta’ala. Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman,
وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ
“Dan segala nikmat yang ada padamu (datangnya) dari Allah, kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan.” (QS. An-Nahl : 53)
Dan di antara doa yang disyariatkan kepada kita untuk dibaca di pagi dan sore hari juga menyebutkan agar kita mengakui nikmat tersebut. Doa tersebut berbunyi,
اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ
“Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menepati perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan perbuatanku, aku mengakui dosaku kepada-Mu dan aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, maka ampunilah aku. Sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain-Mu.”([1])
Kedua, hendaknya seseorang tidak pernah merasa bahwa dirinya memang berhak mendapat nikmat tersebut. Artinya, ketika kita diberi nikmat dari Allah, jangan pernah merasa yakin dan percaya diri bahwasanya sudah sepantasnya diri kita mendapatkan nikmat tersebut karena kita rajin shalat atau rajin sedekah, karena yang demikian adalah tanda bahwa kita kurang bersyukur kepada Allah. Ketahuilah, jika sekiranya berusaha melakukan sesuatu adalah tolak ukur mendapatkan sebuah nikmat, maka hal itu adalah keliru, karena betapa banyak orang yang sudah berusaha dengan gigih namun kenyatannya tidak diberi nikmat oleh Allah, padahal mungkin orang tersebut jauh lebih saleh daripada diri kita.
Oleh karena itu, sikap hati kita ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta’ala adalah kita meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah semata dan meyakini bahwa nikmat tersebut terlalu besar dan banyak serta tidak sebanding dengan sedikit usaha yang kita lakukan.
- الاِعْتِرَافُ بِاللِّسَانِ (Al-I’tiraf Billisan) – Mengakui dengan lisan
Ada dua cara yang bisa dilakukan oleh seorang hamba dalam mengakui nikmat Allah melalui lisan:
Pertama, banyak memuji Allah Subhanahu wa ta’ala
Kedua, التحدث بالنعمة, yaitu senantiasa menyebut nikmat Allah dengan menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta’ala. Di antaranya adalah seperti perkataan Nabi Sulaiman ‘alaihissalam,
ﻫَﺬَﺍ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻞِ ﺭَﺑِّﻲ ﻟِﻴَﺒْﻠُﻮَﻧِﻲ ﺃَﺃَﺷْﻜُﺮُ ﺃَﻡْ ﺃَﻛْﻔُﺮُ
“Ini adalah karunia dari Rabbku untuk menguji diriku. Apakah aku bisa bersyukur ataukah justru kufur.” (QS. An-Naml : 40)
Oleh karena itu, tatkala menyebut nikmat-nikmat Allah, jangan kemudian kita menyandarkan nikmat tersebut pada sebab-sebab selain Allah Subhanahu wa ta’ala. Maka seseorang tidak boleh mengatakan “Kalau bukan karena dokter itu mungkin saya sudah meninggal” atau “Kalau bukan karena polisi itu mungkin rumah saya sudah kemalingan”. Kata-kata seperti ini bisa menodai tauhid kita. Adab yang seharusnya adalah seseorang yang diberi nikmat hendaknya mengatakan, “Kalau bukan karena Allah kemudian sebab polisi tersebut, mungkin rumah saya sudah kemalingan”. Demikian pula misalnya ungkapan terhadap nikmat pemahaman agama, kita tidak boleh mengatakan, “Kalau bukan karena ustaz tersebut maka saya mungkin tidak akan paham”, akan tetapi katakanlah, “Kalau bukan karena Allah yang memberi pemahaman kepada saya dan kemudian dengan sebab ustaz tersebut, mungkin saya tidak akan paham”. Oleh karena itu, dalam nikmat apa pun hendaknya kita menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta’ala, karena itu adalah adab ketika seseorang diberi nikmat.
- الاِعْتِرَافُ بِالْعَمَلِ (Al-I’tiraf Bil ’amal) – Mengakui dengan amalan
Ketika seseorang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta’ala, maka sikapnya melalui amalannya adalah dengan menggunakan nikmat Allah tersebut untuk ketaatan dan bukan untuk maksiat.
Allah Subhanahu wa ta’ala memberikan kita akal, maka jangan kita gunakan akal tersebut untuk berpikir bagaimana cara mencuri harta orang. Allah Subhanahu wa ta’ala memberikan kita mata, maka jangan kita gunakan mata tersebut untuk melihat hal-hal yang haram dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta’ala. Allah Subhanahu wa ta’ala memberikan kita pendengaran, maka jangan kita gunakan pendengaran tersebut untuk mendengar hal-hal yang haram seperti ghibah, namimah, dan musik-musik. Allah Subhanahu wa ta’ala memberikan kita jasad yang sehat, maka jangan kita gunakan jasad kita untuk bermaksiat seperti berzina, berjoget, dan yang lainnya. Sikap-sikap tersebut merupakan bentuk kita tidak bersyukur. Maka yang harus kita lakukan adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan dalam perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala.
Inilah penjelasan sederhana tentang bagaimana sikap-sikap seseorang ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta’ala. Adapun pembahasan kita dalam bab ini adalah kesalahan dalam sikap menyandarkan kenikmatan, yaitu menyandarkan nikmat kepada sebab-sebab. Orang yang melakukan hal tersebut telah melakukan kesalahan berupa kesyirikan, hanya saja pada derajat syirik kecil.
Sikap Seseorang Terhadap Sebab Nikmat

Setelah membahas tentang sikap kita tatkala diberi nikmat, kita beralih kepada pembahasan tentang bagaimana sikap kita terhadap sebab nikmat tersebut. Misalnya, ketika kita bisa sembuh dari suatu penyakit karena ditolong oleh seorang dokter, maka bagaimana sikap kita terhadap dokter tersebut yang merupakan sebab? Tentunya, jika sebab itu adalah manusia, maka kita berterima kasih kepadanya dengan mengucapkan,
جزاك اللهُ خَيْرًا
“Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik.”
Berterima kasih atas bantuan orang lain adalah suatu hal yang sangat dianjurkan. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ
“Tidak bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur (berterima kasih) kepada manusia.”([2])
Berterima kasih kepada manusia adalah sebuah keharusan, akan tetapi kita harus pahami bahwa orang tersebut hanyalah sebab, dan yang memberikan kenikmatan sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta’ala. Benar kita katakan bahwa dengan sebab dokter tersebut penyakit kita bisa sembuh. Akan tetapi siapa yang menjadikan dokter tersebut pintar? Allah Subhanahu wa ta’ala. Dialah Allah yang menjadikan operasinya berhasil. Maka dari itu, jangan kita menyandarkan kenikmatan atau kemudharatan yang kita terhindar darinya kepada sebab-sebab tersebut, karena itulah yang namanya syirik. Adapun kita menyandarkan hati kita ketika kepada Allah saat mendapatkan kenikmatan atau terhindar kemudharatan, maka itulah yang namanya tauhid.
Selain itu, yang harus menjadi perhatian kita juga adalah bahwasanya sebab yang sedang kita hadapi atas suatu nikmat merupakan rangkaian dari banyak sebab, dan yang merangkai sebab tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta’ala. Contoh sederhana, kita mendapat nikmat berupa diberi makanan oleh orang lain berupa nasi saat bertemu ke rumahnya, maka hendaknya kita merenungkan apa dibalik makanan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta’ala,
فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ
“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.” (QS. ‘Abasa : 24)
Orang yang memberikan makanan kepada kita, tentu kita berterima kasih kepadanya karena dialah yang menghidangkan makanan tersebut kepada kita. Akan tetapi sebenarnya hidangan nasi ini adalah hasil dari rangkaian banyak sebab. Coba kita renungkan, dari manakah nasi itu berasal? Nasi berasal dari para petani yang menanam. Kemudian petani tersebut membutuhkan air atau pupuk untuk keberhasilan tanamannya. Setelah berhasil panen, beras-beras yang ada membutuhkan mobil untuk mengangkutnya. Akan tetapi mobil tersebut butuh bahan bakar dari kilang minyak, kemudian kilang minyak tersebut butuh banyak pekerja agar mereka bisa memproduksi bahan bakar, sehingga jika tidak ada pekerja makan tidak ada bahan bakar, dan jika tidak ada bahan bakar maka tidak ada mobil yang bisa mengangkut beras. Sisi yang lain, kalau mobil tersebut memiliki bahan bakar, maka mobil tersebut butuh sopir untuk mengendarainya. Setelah itu, beras dibawa ke supermarket, namun supermarket tidak bisa jadi begitu saja, melainkan butuh tukang untuk membangunnya, butuh karyawan, dan yang lainnya. Tidak sampai hanya disitu, agar beras tersebut sampai di tangan kita, maka ada seseorang yang harus pergi membeli beras tersebut di supermarket. Jika telah sampai di rumah, maka beras tersebut harus dimasak terlebih dahulu. Adapun untuk memasak nasi membutuhkan panci, kompor, dan air. Setelah jadi, baru kemudian bisa dihidangkan kepada kita. Ini semua menunjukkan bahwa nasi yang kita makan memiliki banyak rangkaian sebab sehingga bisa sampai ke tangan kita. Oleh karena itu, maksud penulis adalah jangan sampai hati kita terfokus pada Al-Mubasyir (sebab yang langsung), akan tetapi lihatlah rangkaian yang ada dibalik sebab tersebut, terdapat banyak sekali sebab yang seandainya satu sebab saja dari rangkaian sebab tersebut hilang maka nasi itu tidak bisa jadi, dan yang merangkai itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta’ala.
Contoh kedua adalah dokter yang menyembuhkan kita. Bukankah dokter tersebut bisa menjadi dokter dengan banyak sebab? Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta’ala jadikan dia cerdas, Allah buat dia mendaftar kuliah dan kemudian lulus, kemudian Allah berikan orang tuanya rezeki yang banyak untuk membiayai kuliah anaknya, dan sebab-sebab yang lainnya hingga bisa bertemu kita. Intinya, untuk menjadikan dia sebagai dokter yang mengobati kita, dia harus melalui banyak rangkaian sebab-sebab, dan yang merangkai sebab-sebab tersebut tentu adalah Allah Subhanahu wa ta’ala.
Hal ini semakin menguatkan kita bahwa sumber kenikmatan yang sesungguhnya adalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta’ala. Demikianlah seharusnya cara kita berpikir, bahwasanya yang berhak kita syukuri adalah Allah, bukan sebab yang ada di hadapan kita.
Matan
Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman,
يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ
“Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah.” (QS. An-Nahl : 83)
Mujahid([3]) menafsirkan ayat tersebut dengan berkata,
هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: هَذَا مَالِي وَرِثْتُهُ عِن آبَائِي
“Maksudnya adalah perkataan seseorang, ‘Ini adalah harta kekayaan yang aku warisi dari nenek moyangku’.”
Aun bin Abdillah juga menafsirkan dengan berkata,
يَقُوْلُوْنَ: لَوْلَا فُلَان لَم يَكُنْ كَذَا
“Yaitu mereka berkata, ‘Kalau bukan karena fulan, tentu tidak akan menjadi begini’.”
Ibnu Qutaibah berkata,
يَقُوْلُوْنَ: هَذَا بِشَفَاعَة آلِهَتِنَا
“Yaitu mereka berkata, ‘Nikmat ini karena syafaat dari Tuhan-Tuhan kami’.”
Syarah
Ayat ini ada pada surah An-Nahl. Adapun surah An-Nahl, para ulama juga menyebutnya sebagai surah النِّعَم (nikmat-nikmat), karena di dalam surah tersebut Allah Subhanahu wa ta’ala banyak menyebutkan tentang nikmat-nikmat dari awal surah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta’ala kemudian menyebutkan kesimpulannya dengan ayat ini, yaitu mereka orang-orang musyrikin mengetahui nikmat-nikmat Allah namun kemudian mereka mengingkarinya.
Imam Ath-Thabari rahimahullah menyebutkan bahwa ada khilaf di kalangan Ahli Tafsir tentang makna nikmat Allah dalam ayat ini,
Pendapat pertama, yang dimaksud dengan nikmat Allah dalam ayat ini adalah nikmat duniawi, dalam hal ini seperti Allah Subhanahu wa ta’ala berikan rezeki berupa kesehatan, pakaian, keselamatan, dan banyak kenikmatan dunia lainnya, akan tetapi mereka mengingkari semua nikmat tersebut. Hal ini karena kebanyakan nikmat-nikmat yang disebutkan dalam surah An-Nahl adalah nikmat-nikmat duniawi, yang kemudian Allah sebutkan dalam ayat ini bahwa mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah tersebut.
Pendapat kedua, yang dimaksud dengan nikmat Allah dalam ayat ini adalah nikmat ukhrawi (agama), dalam hal ini yaitu nikmat diutusnya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Pendapat kedua ini sendiri dipilih oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari karena ayat sebelum dan sesudah ayat ini berbicara tentang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, dimana Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman,
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
“Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu (Muhammad) hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah. Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan seorang saksi (rasul) dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir (untuk membela diri) dan tidak (pula) dibolehkan memohon ampunan.” (QS. An-Nahl : 82-84)
Oleh karenanya Ibnu Jarir Ath-Thabari merajihkan (menguatkan) pendapat kedua ini, yaitu mereka orang-orang musyrikin diberikan banyak kenikmatan, namun mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.
Kkedua pendapat di atas sama-sama kuat, karena lafal نِعْمَتَ اللَّهِ dalam ayat ini merupakan الْمُفْرَدُ الْمُضَافُ yang memberikan faedah keumuman, dan pada dasarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta’ala mencakup keduanya.
Ada tiga atsar yang dibawakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah terkait apa yang dimaksud mengingkari nikmat Allah. Dari tiga atsar ini, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab lebih cenderung memilih pendapat pertama, hal ini dikarenakan atsar yang dibawakan oleh beliau menyebutkan tentang orang yang berkata perihal perkara dunianya. Inilah yang sering terjadi di masyarakat kita, sering kita dapati orang-orang yang menyandarkan kenikmatan kepada sebab. Oleh karena itu, inilah pentingnya bagi kita bahwa hendaknya kita berhati-hati dalam berucap. Ketika kita mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari kemudharatan, maka hendaknya langsung mengingat Allah Subhanahu wa ta’ala, karena di saat-saat seperti itulah kita perlu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta’ala, bukan kemudian kita menyebut sebab.
Atsar yang pertama dari Mujahid. Yaitu di antara bentuk mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta’ala adalah mengatakan bahwa harta yang dimiliki itu didapatkan dari warisan nenek moyang. Mengapa perkataan ini merupakan perkataan yang mungkar? Karena dia menyandarkan nikmat tersebut kepada sebab terdekat yaitu bapaknya (nenek moyangnya). Memang benar bahwa yang dia rasakan adalah dia mendapatkan harta dari ayahnya, akan tetapi dari manakah harta ayahnya tersebut? Maka seharusnya, seseorang itu sadar bahwa harta itu asalnya dari Allah Subhanahu wa ta’ala, hanya saja dititipkan melalui bapaknya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta’ala menyebutkan dalam Al-Quran bahwa harta itu hakikatnya miliki Allah, Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman,
وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ
“Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.” (QS. An-Nur : 33)
Ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya harta yang ada pada diri kita itu asalnya dari Allah Subhanahu wa ta’ala. Kemudian dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta’ala juga berfirman,
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ
“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu.” (QS. Al-Baqarah : 254)
Ayat ini juga menjelaskan bahwa harta yang ada pada diri kita asalnya dari Allah Subhanahu wa ta’ala, yang tentu saja harta tersebut datang dengan berbagai sebab. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta’ala,
آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ
“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.” (QS. Al-Hadid : 7)
Ini semakin menunjukkan bahwa harta yang kita miliki itu asalnya dari Allah Subhanahu wa ta’ala. Penulis sering menyampaikan logika sederhana tentang dalil bahwa harta yang kita miliki bukanlah milik kita. Ketika seseorang memiliki mobil, berada di mana mobil tersebut? Tentu berada di dealer mobil, yang kemudian dia membelinya dengan uang. Kemudian, uang tersebut dari mana? Tentu dari usaha-usaha yang dia lakukan, seperti bekerja atau jual beli. Contoh yang lain, ketika kita kehilangan barang yang kita miliki, kita tidak tahu dimana keberadaan barang tersebut. Ini menunjukkan bahwa barang tersebut hakikatnya bukan miliki kita, karena keberadaannya saja kita tidak tahu. Maka sangat jelas bahwa sejatinya harta itu berpindah-pindah, hanya saja kebetulan harta itu ada di tangan kita dan Allah Subhanahu wa ta’ala menjadikan kita menguasainya secara penuh atau pun tidak.
Jangankan harta yang kita miliki, jasad yang kita gunakan saja hakikatnya bukan miliki kita. Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman tentang perkataan seorang mukmin yang terkena musibah :
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
“Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali.” (QS. Al-Baqarah : 156)
Oleh karena itu kita harus sadar bahwa sesungguhnya harta yang ada pada diri kita bukanlah miliki kita, akan tetapi pemilik sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta’ala, kita hanya sekadar ditipkan harta tersebut. Jika ketika kita sadar bahwa harta tersebut hanyalah titipan, maka kita harus menggunakannya sesuai aturan sang pemilik sesungguhnya, yaitu aturan Allah Subhanahu wa ta’ala. Akan tetapi ketika seseorang meyakini bahwa sebab ayahnya atau nenek moyangnyalah dia mendapatkan harta tersebut dan tidak menyandarkannya kepada Allah maka dia telah terjatuh pada syirik kecil.
Atsar yang kedua dari Aun bin Abdillah. Yaitu di antara bentuk mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta’ala adalah mengatakan “Tanpa si fulan maka tidak akan terjadi demikian”, perkataan ini juga termasuk syirik kecil. Oleh karena itu, ketika kita mendapat kenikmatan atau terlepas dari kemudharatan dengan sebab seseorang, hendaknya kita langsung ingat Allah dengan berkata, “Kalau bukan karena Allah, kemudian sebab si fulan maka pasti tidak akan terjadi demikian”.
Atsar yang ketiga dari Qutaibah. Yaitu di antara bentuk mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta’ala adalah sebagaimana perkataan orang-orang musyrikin yang mengatakan bahwa nikmat yang mereka dapatkan itu berasal dari sembahan mereka. Perkataan ini jauh lebih buruk dan berbahaya dari dua perkataan sebelumnya, karena selain menyandarkan nikmat kepada selain Allah, mereka juga melakukan kesyirikan. Oleh karena itu, derajat perkataan ini bukan hanya sampai pada derajat syirik kecil, akan tetapi sudah bisa masuk kategori syirik akbar.
Matan
Berkata Abul Abbas([4]) setelah membahas hadits yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid([5]),
أَنَّ الله تَعَالَى قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرُ – وَهَذَا كَثِيْرٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّة، يَذُمُّ سُبْحَانَهُ مَنْ يُضِيْفُ إِنْعَامَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَيُشْركُ بِه. قَالَ بَعْضَ السَّلَف: هُوَ كَقَوْلِهِمْ: كَانَتِ الرِّيح طَيِّبَة، وَالْمَلَّاحُ حَاذِقًا، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ جَارٍ عَلَى أَلْسِنَة كَثِيْرٍ
“(Dalam hadits tersebut) Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman, ‘Pagi ini sebagian hamba-Ku ada yang beriman kepada-Ku dan ada yang kafir’. Hal ini banyak terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, Allah Subhanahu wa ta’ala mencela orang yang menyekutukan-Nya dengan menisbatkan nikmat yang telah diberikan kepada selain-Nya. Berkata sebagian ulama salaf, ‘Yaitu seperti ucapan mereka: anginnya bagus, nahkodanya pandai, dan sebagainya yang itu banyak muncul dari lisan banyak orang’.”
Syarah
Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menukil perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang contoh orang yang termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta’ala dalam sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam,
أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرُ
“Pagi ini sebagian hamba-Ku ada yang beriman kepada-Ku dan ada yang kafir.”([6])
Maka Syaikhul Islam membawakan contoh di antara orang yang kafir dalam firman Allah tersebut adalah orang yang berkata: “Karena anginnya tenang dan nahkodanya pandai”. Perkataan seperti ini termasuk dalam kesyirikan, meskipun kita sama-sama paham bahwa sebabnya telah benar, yaitu karena angin yang tenang dan nahkodanya pandai maka selamat, akan tetapi secara hakikat yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa ta’ala.
Oleh karena itu, perkara ini (berhati-hati dalam berucap) menjadi perkara yang penting karena kita sangat sering terjerumus dalam hal seperti ini. Kita sering lupa bahwa semua asalnya karena Allah Subhanahu wa ta’ala, akhirnya seringnya kita menyandarkan kenikmatan dan terhindarnya dari kemudharatan kepada sebab dengan ungkapan-ungkapan seperti: “Kalau bukan karena engkau maka tidak akan begini”, atau “Kalau engkau tidak datang maka akan begini”, atau “Karena dokter itu akhirnya saya bisa sembuh”. Bentuk-bentuk perkataan ini adalah bentuk perkataan yang syirik, maka jangan kita menyadarkan kenikmatan yang kita dapatkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta’ala.
Inilah peringatan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa perkataan mengingkari nikmat seperti itu banyak berlaku pada lisan-lisan banyak orang. Bahkan sampai saat ini pun masih kita dapatkan betapa banyak orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta’ala, termasuk diri kita yang mungkin sudah sering hadir dalam majelis ilmu. Maka sekali lagi bahwa yang benar untuk diucapkan ketika kita mendapat kenikmatan atau terhindar dari kemudharatan adalah “Alhamdulillah”, lalu kemudian boleh menyebutkan sebab yang ada di hadapan kita.
Perkara yang boleh dalam hal ini
Kita telah menyebutkan bahwa menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa ta’ala merupakan hal yang tidak diperbolehkan karena merupakan kesyirikan. Akan tetapi ada hal lain yang semisal dengan itu, namun diperbolehkan, yaitu seperti seseorang yang menceritakan sebab bukan dalam rangka untuk menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Contohnya seperti sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam kepada ‘Aisyah radhiallahu ‘anha,
لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ، وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ، فَإِنَّ قُرَيْشًا حِينَ بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَقْصَرَتْ، وَلَجَعَلْتُ لَهَا خَلْفًا
“Kalau bukanlah karena kaummu yang baru saja meninggalkan kekufuran (masuk Islam), akan kurombak Ka’bah dan kubangun di atas pondasi Ibrahim. Sebab, dahulu orang-orang Quraisy memperkecil saat mereka membangunnya. Dan aku akan membuatkannya pintu belakang.”([7])
Perkataan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam “Kalau bukan karena…”, ini bukanlah termasuk perkataan kesyirikan, karena perkataan beliau bukan dalam rangka untuk menyebutkan nikmat atau terhindar dari kemudharatan, bahkan beliau tidak menyebutkan sama sekali tentang nikmat yang beliau rasakan, akan tetapi hanya sekadar kabar (berita), dan kalimat seperti ini tidak mengapa.
Contoh kasus yang lain adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, dan juga dalam Musnad Imam Ahmad, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah berkata tentang pengabaran,
لَوْلاَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْلاَ حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا
“Seandainya bukan karena perbuatan Bani Israil maka daging tidak akan membusuk, dan seandainya bukan karena Hawa’ (istri Nabi Adam alaihissalam) tentu wanita tidak akan mengkhianati suaminya.”([8])
Ibnu Hajar rahimahullah berkata bahwasanya dahulu Bani Israil itu diberi Al-Manna wa As-Salwa.([9]) Aturan waktu itu, mereka tidak boleh tidak boleh menyimpan daging (As-Salwa) untuk kemudian hari, melainkan mereka harus memakan saat itu juga. Akan tetapi karena ketamakan, mereka mengambil daging yang banyak dan menyimpannya karena khawatir besok burung tersebut susah untuk ditangkap. Sebab mereka melanggar aturan tersebut, daging yang dahulunya jika disimpan tidak busuk akhirnya menjadi busuk. Dan itu pula di antara sebab mengapa Allah Subhanahu wa ta’ala menjadikan daging mudah untuk busuk.
Adapun tentang Hawa, maka tidak datang dalam al-Qurán maupun hadits yang menunjukan bahwa maksud dari pengkhianatan tersebut adalah Hawwa yang menggoda Adam untuk memakan buah -sebagaimana yang diyakini oleh Ahlul Kitab-. Akan tetapi bisa saja maksudnya :
Pertama : Karena perangai Hawwa yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok maka menyebabkan wanita memiliki potensi untuk berkhianat, dan perangai ini terwariskan kepada putri-putri Adam.
Kedua : Yang dimaksud dengan berkhianat di sini maksudnya Hawwa membiarkan Adam untuk memakan buah tersebut dan tidak menasihatinya. Sikap mendiamkan ini adalah bentuk khianat dan tidak menasihati. Al-Waziir ibn Hubairoh (wafat 560 H) berkata :
إن خيانتها لزوجها، أنها لما رأت آدم قد عزم على الأكل من الشجرة تركت نصحه في النهي له؛ لأن ذلك كان ترك النصح له خيانة
“Sesungguhnya pengkhianatan Hawwa kepada suaminya (Adam) adalah ketika ia melihat Adam sudah bertekad untuk memakan dari pohon tersebut Hawwa membiarkannya dan tidak menasihatinya dan tidak melarangnya. Oleh karenanya bentuk tidak menasihati Adam adalah bentuk berkhianat kepadanya” ([10])
Ini juga pendapat Ibnul Jauzi (wafat 597 H) beliau berkata :
وَأما خِيَانَة حَوَّاء زَوجهَا فَإِنَّهَا كَانَت فِي ترك النَّصِيحَة فِي أَمر الشَّجَرَة لَا فِي غير ذَلِك
“Dan adapun pengkhianatan Hawwa kepada suaminya adalah ia tidak menasihati Adam dalam urusan pohon tersebut, bukan pada perkara yang lainnya” ([11])
Intinya, dengan sebab itu maka sebagian wanita berkhianat terhadap suaminya. Adapun maksud dari berkhianat di sini bukan maksudnya sang istri melakukan zina, akan tetapi maksudnya adalah kalau wanita ingin sesuatu maka mereka akan melakukan trik apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, karena mereka keturunan Hawa.
Intinya, sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ini bukan berbicara tentang kenikmatan atau terhindarnya dari kemudharatan, akan tetapi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam hanya sedang menceritakan pengabaran. Tentu kita yakini bahwa itu semua terjadi karena Allah Subhanahu wa ta’ala, akan tetapi apa yang dikatakan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bukan dalam rangka untuk menceritakan tentang nikmat atau terhindarnya dari kemudharatan.
Contoh yang lain adalah kisah jawaban Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam terhadap pamannya Al-‘Abbas bin Abdul Muthalib([12]). Diriwayatkan bahwa Al-‘Abbas bin Abdul Muthalib berkata kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam,
مَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمِّكَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَلَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ
“Apa yang kamu lakukan untuk menolong pamanmu Abu Thalib, padahal dia dahulu yang melindungimu dan marah demi membelamu?” Beliau bersabda, ‘Sesungguhnya dia berada di tepian neraka (azabnya ringan). Seandainya bukan karena aku, dia tentu sudah berada di dasar neraka’.”([13])
Di dalam hadits ini, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menyebutkan tentang kenikmatan, yaitu kenikmatan yang dialami oleh Abu Thalib berupa berkurangnya siksa yang dia dapatkan. Bahkan dalam hadits lain disebutkan,
أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ، وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ
“Penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib, dia memakai kedua sandal sementara otaknya mendidih karena panasnya.”([14])
Lantas apakah perkataan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ini ada kesyirikan karena menyandarkan nikmat yang didapat oleh Abu Thalib kepada diri beliau? Tentu jawabannya adalah tidak. Beliau adalah seorang Rasul, maka tidak mungkin beliau salah dalam berucap. Adapun jawaban yang tepat bahwa perkataan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tersebut bukanlah perkataan syirik adalah karena pengabaran tentang nikmat tersebut bukan disampaikan oleh yang mendapatkan nikmat, akan tetapi orang lain. Dalam kasus ini, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam hanya mengabarkan tentang nikmat yang didapat oleh Abu Thalib. Adapun jika Abu Thalib yang berbicara langsung dengan berkata, “Kalau bukan karena Muhammad, pasti saya sudah berada di neraka paling bawah”, maka kalimat seperti ini adalah kekufuran karena Abu Thalib menyandarkan nikmat tersebut kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Adapun ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang mengabarkan maka kalimat pengabaran itu tidak menjadi perkataan syirik.
Oleh karena itu, tidak mengapa bagi seseorang yang misalnya melakukan presentasi perkembangan usaha perkebunan perusahannya, kemudian dia menyebutkan sebab-sebab seperti pada bulan tertentu kondisi curah hujan yang bagus menyebabkan tanaman memiliki produksi tinggi dan pada bulan tertentu lainnya produksi berkurang karena curah hujan rendah, maka hal seperti itu tidak mengapa karena pada hakikatnya dia hanya mengabarkan dan bukan dalam rangka menyandarkan nikmat lancarnya produksi kepada hujan.
Perhatikanlah, pembahasan perkara ini merupakan tanda bahwa agungnya tauhid. Syariat Islam ingin agar tauhid seseorang benar-benar bersih dan kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta’ala, bahkan dalam perkara seperti ini saja kita dianjurkan untuk berhati-hati dalam berbicara, karena barangsiapa yang salah dalam berbicara meskipun dia tidak bermaksud atau karena ketidaksengajaan maka dia bisa terjerumus dalam syirik kecil. Jika demikian, sekadar berkata menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa ta’ala sudah termasuk syirik, maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang datang ke kuburan dan meminta-minta kepada penghuni kubur? Tentu yang seperti itu juga termasuk kesyirikan karena meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta’ala. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa menjaga dan membersihkan tauhid kita dari segala noda kesyirikan, baik noda yang besar maupun noda yang kecil.
Matan
Kandungan bab ini:
- Penjelasan tentang adanya orang yang mengetahui nikmat Allah namun mereka mengingkarinya
- Hal itu sering terjadi dalam banyak ucapan orang-orang
- Ucapan seperti ini dianggap sebagai pengingkaran terhadap nikmat Allah
- Adanya dua hal yang kontradiksi (mengetahui nikmat Allah dan mengingkarinya), bisa terjadi dalam diri manusia
Artikel ini penggalan dari Buku Syarah Kitab At-Tauhid Karya Ustadz DR. Firanda Andirja, Lc. MA.
_______________________
([3]) Dia adalah seorang tabi’in dan merupakan murid dari Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhu.
([4]) Yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
([5]) Yaitu hadits yang telah disebutkan pada bab ke-29 tentang orang-orang yang mengisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang
([6]) HR. Bukhari no. 1038 dan HR. Muslim no. 125
([8]) HR. Bukhari no. 3330 dan HR. Muslim no. 1470
([9]) Al-Manna adalah istilah makanan yang diperoleh dengan cara yang mudah, adapun As-Salwa adalah burung kecil yang memiliki daging yang lembut. Lihat Tafsir As-Sa’di 1/52
([10]) Al-Ifshooh án maáani as-Shihaah 7/230
([11]) Kasyf al-Musykil min Hadiits As-Shahihain 3/504
([12]) Dia adalah paman Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang juga merupakan saudara Abu Thalib, paman Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam