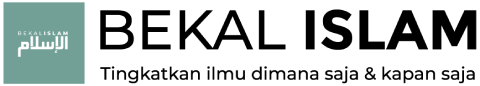مَا جَاءَ فِي الاِسْتِسْقَاءِ بَالأَنْوَاءِ
Mengisbatkan Turunnya Hujan Kepada Bintang
Oleh DR. Firanda Andirja, Lc. MA.
Syarah
Pada bab sebelumnya kita telah membahas tentang mengaitkan gerakan-gerakan bintang dengan masa depan yang merupakan bagian dari ilmu perdukunan, dan hukumnya adalah syirik akbar. Adapun kaitan bab sebelumnya dengan bab ini adalah juga sama-sama kesyirikan, namun bab ini hanya sampai pada derajat syirik kecil, karena mengisbatkan turunnya hujan dengan bintang-bintang tertentu. Namun kita akan bahas beberapa bentuk kesyirikan yang terjadi dengan mengisbatkannya turunnya hujan terhadap bintang.
Mengaitkan turunnya hujan dengan bintang terjadi dalam dua bentuk.
- Menggunakan kata بِ, seperti kalimat مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا (Kami diturunkan hujan karena bintang itu)
Bentuk kalimat seperti ini akan memberikan dua makna yang akan menunjukkan hukum perbuatan tersebut.
- Makna pertama adalah bintang tersebut ikut menurunkan hujan. Dan keyakinan seperti ini hukumnya adalah kufur akbar, karena meyakini bahwa ada mudabbir (pengatur) selain Allah Subhanahu wa ta’ala. ([1])
- Makna kedua adalah muncul dan tenggelamnya bintang tertentu merupakan sebab turunnya hujan. Keyakinan seperti hukumnya adalah kufur ashgar, atau dalam bahasa kita adalah kufur nikmat. Dikatakan sebagai kufur nikmat adalah karena asalnya hujan adalah kenikmatan, dan kenikmatan hujan tersebut harusnya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala dan bukan kepada bintang. Maka tatkala seseorang menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa ta’ala, maka dikatakan dia kufur nikmat. Dan pada makna kedua ini, terdapat dua kesalahan,
- Menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan, padahal bintang bukanlah sebab turunnya hujan.
- Jika sekiranya bintang tersebut merupakan sebab turunnya hujan, maka tetap nikmat tersebut (hujan) harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala dan bukan kepada bintang.
Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta’ala,
يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ
“Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah.” (QS. An-Nahl : 83)
Ayat ini turun kepada sekelompok orang yang berada di tengah lautan dan ombak yang besar. Kemudian mereka memiliki nakhoda yang pandai dalam mengendalikan kapal dalam situasi tersebut sehingga akhirnya mereka selamat dari badai di tengah lautan tersebut. Maka orang-orang yang berada di kapal tersebut mengatakan bahwa mereka selamat karena nakhoda yang pandai tersebut. Sesungguhnya inilah bentuk kufur nikmat. Karena justru dalam kondisi seperti ini seseorang harusnya langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta’ala. Memang benar bahwa nahkoda tersebut adalah sebabnya, akan tetapi penyelamat sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta’ala. Maka seharusnya dalam kondisi seperti itu seseorang harusnya berkata, “Kalau bukan karena Allah lalu dengan sebab orang itu, kita tidak akan selamat”. Akan tetapi masih banyak orang yang lupa akan hal ini, sehingga tatkala mereka mendapati kondisi seperti ini maka mereka langsung menyandarkan nikmat kepada makhluk yang dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa ta’ala.
- Menggunakan kata فِي, seperti pada kalimat مُطِرْنَا فِيْ نَوْءِ كَذَا (Kami diturunkan hujan pada saat munculnya bintang itu)
Para ulama mengatakan bahwa mengaitkan antara turunnya hujan dan bintang dengan menggunakan kata فِي tidaklah mengapa. Dan ini adalah pendapat madzhab Syafi’i, Hanbali ([2]) Karena فِي dalam hal ini merupakan bentuk zharfu Az-Zaman, yaitu menunjukkan waktu terjadinya kejadian. Oleh karenanya kalimat seperti مُطِرْنَا فِيْ نَوْءِ كَذَا (Kami diturunkan hujan pada saat munculnya bintang itu) adalah tidak mengapa karena dalam kalimat tersebut tidak bentuk mengaitkan sebab hujan dengan bintang tertentu. Sama halnya ketika kita mengatakan bahwa musim hujan tiba pada bulan Desember dan ketika muncul suatu bintang tertentu. Artinya bintang tersebut muncul pada bulan tertentu yang kebetulan juga waktu itu musim hujan. Maka ungkapan-ungkapan seperti ini tidak mengapa.
Dan ini merupakan dalil bahwasanya syariat jika telah berbicara tentang masalah tauhid, maka pasti akan detail pembahasannya. Oleh karenanya jangan sampai seseorang salah dalam berucap, karena meskipun maksudnya bukanlah kesyirikan, akan tetapi jika lafalnya ada berbau syirik maka hendaknya dijauhi. Sebagaimana yang telah Allah ‘Azza wa Jalla firmankan:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ
“Wahai orang yang beriman: “janganlahengkau katakan “Ro’ina”, akan tetapi katakanlah “Unzhurna” dan dengarkanlah, sesungguhnya bagi orang kafir itu adzab yang pedih”. ([3])
Dan Syariat ini melarang untuk mengucapkan hal-hal yang mengandung makna yang terlarang. Dahulunya orang-orang Yahudi menggunakan kalimat tersebut (Ro’ina) untuk mencela, dan orang-orang muslim kala itu (sahabat) tidak meniatkan apa yang dilakukan orang kafir, dan bahkan mustahil ada sahabat yang berani demikian. Ini merupakan dalil yang sangat kuat untuk tidak melakukan atau mengatakan sesuatu yang mengandung kemungkinan yang terlarang. ([4])
Adapun yang disunnahkan bagi seseorang ketika terjadi adalah mengucapkan apa yang Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah ajarkan. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berdoa,
اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا
“Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat.”[5]
Dan dalam kesempatan lain Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengabarkan tentang firman Allah Subhanahu wa ta’ala bahwa orang-orang beriman jika turun hujan mereka akan berkata,
مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ
“Hujan turun kepada kita karena karunia dan rahmat-Nya.”[6]
Jika seseorang mengatakan sebagaimana yang disunnahkan ini, maka ini menunjukkan bahwa dia telah menyandarkan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala.
Oleh karenanya dari sini kita paham bahwa pembahasan pada bab ini tidak sama dengan pembahasan pada bab sebelumnya. Pada bab sebelumnya kita membahas perbintangan yang digunakan dalam perdukunan yang merupakan syirik akbar, adapun bab ini berbeda dan memerlukan beberapa perincian sebagaimana yang telah disebutkan.
Matan
Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman,
وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ
“Dan kalian membalas rezeki (yang telah dikaruniakan) kepadamu dengan mendustakan-Nya.” (QS. Al-Waqi’ah : 82)
Syarah
Maksud dari ayat ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dan At-Tirmdzi dalam sunannya, dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
{وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} قَالَ: شُكْرُكُمْ، تَقُولُونَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا وَبِنَجْمِ كَذَا وَكَذَا
“(firman Allah) ‘Kamu mengganti rezeki (yang Allah berikan) dengan mendustakan Allah’. (QS. Al-Waqi’ah : 82). Beliau bersabda, ‘(maksud ayat tersebut) wujud syukur kalian dengan cara mengatakan: Kami diberi hujan karena bintang ini dan ini’.”[7]
Dan ayat ini ditafsirkan oleh para ulama berdasarkan hadits dan riwayat yang datang dengan mengatakan,
وَتَجْعَلُوْنَ شُكْرَ رِزْقِكُمْ بِأَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ الله بِنِسْبَة الرِّزْق إِلَى غَيْرِ الله
“Kalian menjadikan bentuk bersyukur terhadap rezeki dengan mengisbatkan rezeki tersebut kepada selain Allah (kepada bintang).” ([8])
Matan
Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy’ari radhiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ. النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ
“Ada empat perkara jahiliah yang masih melekat pada umatku dan mereka belum meninggalkannya; Bangga dengan nasab, mencela nasab (garis keturunan), mengaitkan hujan dengan bintang-bintang tertentu, dan niyahah (meratapi mayat). Orang yang meratapi mayat, jika ia belum bertaubat sebelum ajalnya tiba maka pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang berlumuran tembaga dan mantel yang bercampur dengan penyakit kudis.” (HR. Muslim)
Syarah
Dalam hadits ini, terdapat empat perkara yang Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sebutkan sebagai perkara tercela karena Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menisbatkannya kepada bentuk perkara jahiliah. Akan tetapi perkara-perkara tersebut ternyata dikabarkan belum ditinggalkan oleh umat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Oleh karenanya ini adalah dalil bahwa terkadang pada diri seorang muslim ada perkara jahiliah. Akan tetapi orang yang memiliki di dalam dirinya perkara jahiliah tersebut tidak dikatakan bahwa dirinya adalah seorang yang jahil. Hanya saja kita katakan bahwa dia melakukan perkara yang merupakan sisa-sisa perkara jahiliah. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada Abu Dzar yang telah mencela Bilal, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata,
يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ
“Wahai Abu Dzar, apakah kamu menghinanya dengan menghina ibunya? Sesungguhnya dalam dirimu masih terdapat sifat jahiliah.”([9])
Mencela nasab adalah bagian dari perkara jahiliah. Demikian juga di antara perkara jahiliah adalah wanita yang keluar dari rumahnya dengan berhias. Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman,
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى
“Dan hendaklah kamu (para wanita) tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu.” (QS. Al-Ahzab : 33)
Dan betapa banyak kita lihat para wanita zaman sekarang yang jika hendak keluar rumah pasti berhias terlebih dahulu dengan sebaik-baik hiasan. Padahal yang demikian adalah salah satu perkara jahiliah. Maka jika sekiranya para wanita tinggal di rumah-rumah mereka karena Allah dan tidak berhias sebagaimana berhiasnya wanita-wanita jahiliah tatkala hendak keluar rumah, maka tentu dia akan mendapatkan pahala karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta’ala ini.
Di sini, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menyebutkan empat perkara jahiliah yang ada pada umat beliau, dan perkara tersebut belum ditinggalkan.
- الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ (Berbangga dengan nasab)
Para ulama mengartikan الْأَحْسَابِ dengan dua makna. Makna pertama, Al-Ahsab disini maksudnya adalah nasab atau nenek moyang. Makna kedua, Al-Ahsab disini adalah kedudukan di masyarakat. Artinya orang-orang tersebut membanggakan nasab atau kedudukannya. Dan perkara ini masih banyak terjadi di tengah-tengah kita. Padahal kita tahu bahwasanya manusia tidak akan mulia kecuali dengan takwa. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda,
يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى
“Wahai sekalian manusia, Rabb kalian satu, dan ayah kalian satu. Ingat, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang ‘ajam (selain Arab), dan tidak pula bagi orang ‘ajam atas orang Arab, tidak ada kelebihan bagi orang berkulit kemerah-merahan (putih) atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit kemerah-merahan kecuali dengan ketakwaan.”([10])
Oleh karenanya jika seseorang dikaruniai keturunan yang mulia dan disertai dengan takwa, maka dia akan semakin menjadi mulia. Akan tetapi jika ternyata dia memiliki keturunan yang mulia namun dia tidak bertakwa, maka tidak manfaat keturunannya tersebut.
Berbangga dengan nasab merupakan penyakit manusia secara umum. Sehingga terkadang sebagian mereka mencela nasab suku yang lain, padahal suku yang lain tersebut juga mencela nasab mereka. Bahkan terkadang dalam satu suku yang terdapat beda marga, akhirnya sebagian membanggakan marganya atas sebagian yang lainnya sehingga timbul saling cela mencela. Padahal yang demikian tidaklah diperbolehkan.
Adapun yang dibolehkan dari mencela orang lain adalah ketika dia tidak bertakwa. Jika dia dilahirkan dari keturunan tertentu dan dengan kondisi tertentu, maka itu di luar dari kemampuan dia untuk menentukannya, sehingga tidak boleh mereka dicela dari sisi itu. Adapun ketakwaan, dia bisa berusaha untuk meraihnya sehingga dia bisa dicela jika tidak bisa mengusahakannya. Oleh karenanya tidak boleh mencela seseorang dari sisi suku atau keturunannya. Lihatlah Salman Al-Farisi, dia menjadi mulia meskipun dia bukan orang Arab, bahkan dia berasal dari Persia. Oleh karenanya dikatakan,
فَقَدْ رَفَعَ الْإِسْلَامُ سَلْمَانَ فَارِسٍ، وَقَدْ وَضَعَ الْكُفْرُ الشَّرِيفَ أَبَا لَهَبٍ
“Sungguh Salman Al-Farisi diangkat (dimuliakan) oleh Islam (karena ketakwaannya), dan sungguh Abu Lahab menjadi hina karena kekufurannya.”([11])
Oleh karena itu, hendaknya kita berhati-hati agar jangan sampai kita terjebak dalam berbangga-bangga dengan nasab dan keturunan, terlebih lagi jika sampai pada mencela nasab orang yang lain. Karena jangankan kita sombong dengan nasab, sombong dengan apa yang ada pada diri sendiri seperti harta atau kepintaran saja diharamkan oleh Islam. Maka tentu jika bangga dengan diri sendiri saja telah dilarang, maka tentu berbangga diri dengan nasab lebih tidak diperbolehkan lagi. Dan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda,
إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ
“Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, hendaklah kalian bersikap rendah diri, hingga seseorang tidak berbuat aniaya kepada yang lain, dan seseorang tidak berlaku sombong kepada yang lain.”([12])
Dan sebagian orang terkadang menjadi sombong ketika telah memiliki sesuatu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman,
وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
“Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.” (QS. Luqman : 18)
صَعِّر adalah penyakit yang diderita oleh unta di bagian leher, sehingga ketika dia berjalan kepalanya akan menghadap ke kanan dan ke kiri. Sehingga seakan-akan Allah Subhanahu wa ta’ala mengatakan dalam ayat ini agar seseorang itu jangan seperti itu unta tersebut karena itu adalah bentuk kesombongan bagi manusia, terkecuali bagi yang memiliki uzur. Dan ketahuilah bahwa sombong itu asalnya ada di dalam hati, akan tetapi dia akan terekspresikan dengan perkataan maupun perbuatan.
- الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ (mencela nasab/keturunan)
Para ulama membagi mencela nasab menjadi dua bagian,
Pertama adalah mencela suku atau nasab orang lain. Hal ini tentu tidak diperbolehkan. Mencela sebagian mereka karena kesalahannya adalah hal yang tidak mengapa, akan tetapi jika kita katakan kesalahannya tersebut berkaitan dengan suku atau nasabnya maka yang seperti ini tidak boleh. Karena ketahuilah bahwa tidak semua orang dari suku tertentu tersebut buruk. Kita akui bahwa sebagian dari mereka ada yang buruk, akan tetapi sebagian yang lain juga ada orang-orang yang baik, dan yang seperti ini berlaku pada semua suku. Sehingga tidak boleh kita mencela dengan suku atau nasabnya, akan tetapi kita boleh mencela dengan kesalahannya.
Kedua adalah mencela seseorang karena meragukan nasabnya. Mungkin ada orang yang mengaku dari suku atau nasab tertentu, kemudian kita mencelanya karena meragukan dan tidak percaya bahwa dia dari suku atau nasab tersebut. Ketahuilah bahwa sikap yang seperti ini adalah tidak boleh. Dan kaidah para ulama menyebutkan,
النَّاسُ مُؤْتَمَنُوْنَ عَلَى أَنْسَابِهِمْ
“Manusia diamanahkan/dipercaya atas nasab mereka.”
Artinya jika seseorang telah mengatakan bahwa dirinya dari suku atau nasab tertentu, maka tugas kita adalah membenarkannya dan tidak boleh mendustakannya. Adapun jika dia berbohong maka itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta’ala. Karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda,
مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ
“Barangsiapa menasabkan diri kepada selain ayahnya padahal ia tahu bukan ayahnya maka surga haram baginya.”([13])
Intinya tidak boleh seseorang meragukan pengakuan seseorang tentang suku atau nasabnya. Terkecuali jika dibalik itu ada perkara syar’i atau ada hak yang harus ditunaikan, maka tidak mengapa untuk bertanya dan meragukan suku seseorang. Dan yang seperti ini banyak terjadi di Arab Saudi. Contoh, jika seseorang membuat wakaf untuk suku tertentu, maka jika ada orang yang mengaku dari suku tersebut maka kita bisa meminta untuk mendatangkan bukti-buktinya. Adapun jika tidak ada keperluan dibalik pernyataannya tentang sukunya, maka tidak mengapa kita membenarkannya dan tidak mendustakannya.
- الْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ (Mengaitkan hujan dengan bintang tertentu)
Perkara mengaitkan turunnya hujan dengan bintang-bintang tertentu ini yang dibahas pada bab ini. Dan ini telah kita bahas pada awal bab ini tentang keharamannya.
- النِّيَاحَةُ (meratapi mayat)
Meratapi mayat menunjukkan ketidaksabaran dan bentuk protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta’ala, padahal hal itu adalah dosa besar. Sebab Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda,
النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ
“Orang yang meratapi mayat, jika ia belum bertaubat sebelum ajalnya tiba maka pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang berlumuran tembaga dan mantel yang bercampur dengan penyakit kudis.”([14])
Yang diingatkan tentang meratap di dalam hadits ini adalah manusia pada umumnya. Akan tetapi para ulama menyebutkan bahwa wanita yang seharusnya memiliki perhatian yang besar terhadap ini. Karena memang pada dasarnya wanita sangatlah lemah sehingga sangat mudah meratap dan bersedih. Karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh ziarah kubur karena lemahnya hati mereka. Karena bisa jadi ketika para wanita ziarah ke kuburan maka dia akan menangis dan meratap yang berkepanjangan, sehingga terkadang banyak maslahat-maslahat yang tidak bisa dia kerjakan karena kesedihannya.
Matan
Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Khalid radhiallahu ‘anhu, ia berkata,
صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengimami kami pada shalat subuh di Hudaibiyah setelah semalam turun hujan. Ketika selesai melaksanakan shalat, beliau balik menghadap kepada manusia (jemaah). Kemudian beliau bersabda, ‘Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian?’ Mereka berkata, ‘Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui’. Beliau bersabda, ‘(Allah berfirman) Di pagi ini ada hamba-hamba-Ku yang beriman kepada-Ku dan ada yang kafir. Orang yang berkata, “Hujan turun kepada kita karena karunia Allah dan rahmat-Nya”, maka dia adalah yang beriman kepada-Ku dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun yang berkata, “Hujan turun disebabkan bintang ini atau itu”, maka dia telah kafir kepada-Ku dan beriman kepada bintang-bintang’.”
Syarah
Pada sebagian riwayat, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat dengan lafal,
هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ اللَّيْلَةَ؟
“Tahukah kalian apa yang dikatakan (difirmankan) oleh Rabb kalian tadi malam?”([15])
Dalam hadits ini, terdapat beberapa penekanan terhadap dalil. Pertama, hadits ini merupakan dalil akan sunnahnya seorang imam untuk berbalik menghadap jemaah. Kedua, hadits ini merupakan dalil akan sunnahnya seorang imam untuk memberi nasihat setelah shalat jika memang diperlukan, karena hal ini sebagaimana sering dilakukan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Ketiga, hadits merupakan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman pada waktu yang Dia tentukan. Tidak seperti apa yang diyakini oleh sebagian orang-orang Asy’ariyah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta’ala berkata dengan kalam qadim yang mereka maknai bahwa Allah sudah berbicara sejak zaman azali dengan suatu topik yang tidak pernah berubah, dan tidak berkata lagi sesudahnya, karena mereka menolak sifat Allah bisa berbicara kapan saja. Adapun Ahlussunnah menyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman (berbicara) kapan saja Dia kehendaki, dengan topik apa yang Dia kehendaki, dan kepada siapa pun yang Dia kehendaki.
Matan
Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhu yang semakna dengan hadits sebelumnya. Dalam hadits tersebut Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhu meriwayatkan,
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا. فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَات: فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ َتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ
“Dan berkata sebagian dari mereka, ‘Sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu’. Maka turunlah ayat, ‘Lalu Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui, dan (ini) sesungguhnya Alquran yang sangat mulia, dalam Kitab yang terpelihara (Lauhil Mahfuzh), tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini (Alquran), dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima (dari Allah) justru untuk mendustakan-Nya’.”
Syarah
Sebagaimana telah kita jelaskan di awal pembahasan bab ini, yaitu sebagian mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta’ala berupa hujan, akan tetapi mereka mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa ta’ala tersebut dengan menisbatkan rezeki tersebut kepada bintang-bintang.
Matan
Pelajaran yang terkandung dalam bab ini,
- Penjelasan (tafsir) ayat dari surah Al-Waqi’ah.
- Adanya empat perkara yang termasuk perbuatan jahiliah.
- Pernyataan bahwa salah satu dari empat perkara jahiliah adalah termasuk perbuatan kufur.
- Ada dari perbuatan kufur yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam.
- Firman Allah dalam hadits qudsi, “Di pagi ini ada hamba-hamba-Ku yang beriman kepada-Ku dan ada yang kafir”, sebab turunnya adalah tentang nikmat.
- Perlunya pemahaman yang mendalam tentang iman dalam hal tersebut.
- Perlunya pemahaman yang mendalam tentang kekufuran dalam hal tersebut.
- Di antara perkataan kekufuran adalah “Sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu”.
- Metode pengajaran kepada orang yang tidak mengerti masalah dengan memberikan pertanyaan sebagaimana perkataan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, “Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian?”.
- Ancaman terhadap wanita yang meratapi orang yang telah mati.
Artikel ini penggalan dari Buku Syarah Kitab Tauhid Karya Ustadz DR. Firanda Andirja, Lc. MA.
_________________________
([1]) At-Taudhih Fi Tauhid Al-Khollaq, Sulaiman bin ‘Abdillah, 1/183
([2]) Lihat Mughni Al-Muhtaj, As-Syirbini, 1/611, Al-Inshof, Al-Mardawi, 5/439
Meskipun sebagian ulama seperti Al-Amidi Al-Hanbali memandangnya makruh, begitu juga Syaikh Sulaiman bin ‘Abdillah bin Muhammad bin ‘Abdil Wahhab (Lihat At-Taudhih ‘An Tauhiid Al-Khollaq, Sulaiman bin ‘Abdillah, 1/183). Dengan alasan: “Bahwa kalimat tersebut yang bisa bermakna kufur dan tidak, sehingga dikhawatirkan orang-orang berperasangka buruk kepada yang mengatakannya. Dan yang demikian itu juga termasuk kebiasaan dan syiar jahiliyyah, dan orang-orang yang mengikuti mereka.
([4]) Hadzihi Mafahimuna, Sholeh bin ‘Abdul ‘Aziz Alus-Syaikh, 21-22
[5] HR. Bukhari no. 1032
[6] HR. Bukhari 1038 dan HR. Muslim no. 71
([7]) HR. At-Tirmidzi no. 3295, beliau mengatakan hadits ini hasan.
([8]) Zad Al-Masir, Ibnu Al-Jauzi, 4/229 dengan semakna, dan beliau nisbatkan kepada mayoritas ahli tafsir.
([11]) Adhwaul Bayan 7/417. Dan ucapan ini dinisbatkan kepada ‘Ali bin Abi Tholib radhiallahu’anhu, dan disebutkan sanadnya (terlepas dari keshohihan sanadnya) oleh imam Ibnu ‘Asakir, dalam Tarikh Dimasyq, 21/426
([12]) HR. Bukhari no. 428 dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad
[15] HR. Ath-Thabrani no. 5212 dalam Mu’jam Al-Kabiir