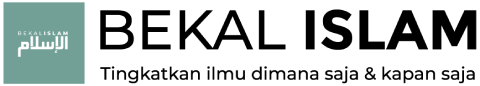9. وَدُّوا۟ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
waddụ lau tud-hinu fa yud-hinụn
9. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).
Tafsir :
Mereka orang-orang kafir Quraisy menginginkan agar Nabi ber-mudahanah, yaitu jika Nabi berhenti mencela sembahan dan nenek moyang mereka, serta menghentikan dakwahnya, maka mereka juga akan berhenti dan tidak akan mencela Nabi ﷺ lagi sebagai orang gila([1]). Artinya mereka memberi tawaran karena merasa terganggu ketika mereka disebut sebagai orang musyrik. Bahkan mereka mengatakan,
إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ
“(Orang-orang musyrikin berkata) Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka.” (QS. Az-Zukhruf : 22)
Akan tetapi Nabi ﷺ membantah mereka dengan mengatakan bahwa mereka itu sesat, dan nenek moyang mereka pun dahulu dalam kesesatan. Tentu hal ini hanya menambah kemarahan orang-orang musyrikin.
Di hadapan kita ada istilah الْمُدَاهَنَةُ mudahanah dan الْمُدَارَاةُ mudarah. Mudahanah adalah mencari kemaslahatan duniawi dengan mengorbankan agama. Contohnya adalah seseorang yang ingin berteman dengan seorang kawannya yang bermain musik, maka dia ikut bermain musik agar bisa berteman dengan orang tersebut meskipun dia tahu akan haramnya musik. Misalnya pula warga di lingkungan tempat tinggal kita sering bermain judi, maka agar bisa enak bergaul dan mengobrol dengan mereka maka kita pun ikut bermain judi meskipun kita sadar bahwa judi itu haram. Misalnya lagi seseorang yang bertanya tentang bolehnya suatu perkara, maka kita pun memperbolehkan agar orang tersebut tidak marah, meskipun kita tahu hal tersebut tidak boleh dalam syariat. Inilah yang disebut dengan mudahanah, dan hal seperti ini tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, kita hendaknya menyampaikan syariat dengan sebaik-baiknya dan selembut-lembutnya, akan tetapi yang syirik tetap kita katakan sebagai syirik, yang bid’ah tetap kita katakan sebagai bid’ah, yang maksiat tetap kita katakan sebagai maksiat. Jangan kemudian kita ber-mudahanah sehingga yang maksiat kita katakan sebagai halal, yang bid’ah menjadi sunnah, dan yang syirik menjadi tauhid. Kita harus menyampaikan syariat Islam sesuai dengan apa yang Allah ﷻ kehendaki dan telah dijelaskan oleh Rasul-Nya, bukan syariat yang kita modifikasi dengan dalih agar diterima masyarakat. Tentunya hal syariat tersebut harus kita sampaikan seadanya, namun dengan kata-kata yang baik, serta dalil yang jelas.
Mudaraah adalah mengorbankan sedikit dari kemaslahatan dunia demi untuk agama. Contoh mudarah adalah apabila ada orang yang memaki-maki kita maka kita tetap sikapi dengan sabar dan tetap berusaha mendekati hatinya agar dakwah tetap berlangsung. Hal seperti ini (mudarah) adalah hal yang dianjurkan. Contohnya seorang da’i yang sedang berbicara masalah tauhid, lalu para jemaahnya merokok di depannya sehingga sang da’i merasa terganggu dengan hal tersebut. Tetapi dia tetap bersabar menyampaikan dakwahnya, bahkan dia tetap bersabar meskipun kesehatannya tersebut terganggu, demi agar dakwah bisa sampai kepada orang tersebut. Ini adalah salah satu contoh sikap mudarah, mengorbankan sebagian maslahat duniawi demi kemaslahatan agama. Sikap mudarah adalah hal yang dibolehkan, adapun mudahanah adalah sikap yang tidak diperbolehkan. ([2])
Dalam kehidupan bermasyarakat, terkadang ada yang berbeda dengan kita. Maka kita boleh bersikap lembut kepada mereka tanpa harus mengatakan bahwa kesalahan mereka sebagai kebenaran. Bukan bersikap lembut kepada mereka dengan mengikuti kesalahan yang mereka lakukan. Kalau ada seseorang yang bermaksiat maka kita harus katakan itu sebagai maksiat, yang syirik tetap syirik, dan yang haram tetap haram. Jangan sampai karena slogan “toleransi” sehingga kita ikut-ikut dalam kemaksiatan mereka. Karena yang demikianlah yang disebut sebagai sikap ber-mudahanah, yaitu sikap yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin terhadap Nabi ﷺ.
_______________________
Footnote :
([1]) Lihat: Tafsir Al-Baghawiy 8/192.
([2]) Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar perbedaan keduanya dan hukum keduanya dalam kitabnya Fathul Bari 10/528